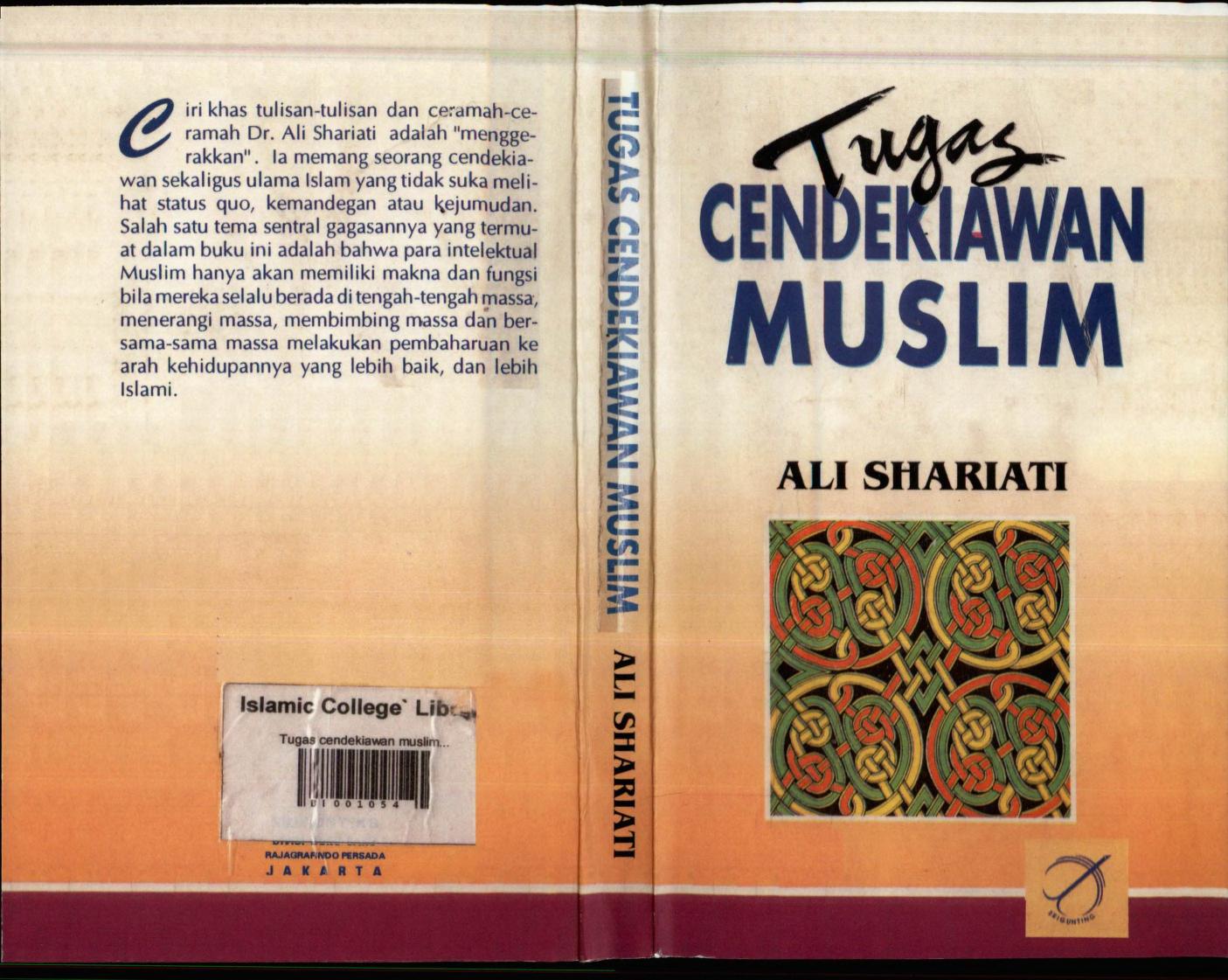Buku Tugas Cendekiawan Muslim merupakan salah satu manifestasi paling jelas dari panggilan aksi Syariati. Karya ini bukan hanya sebuah teks akademis atau teologis, melainkan sebuah manifesto yang bergelora, sebuah seruan langsung kepada kaum intelektual untuk meninggalkan kejumudan dan status quo. Analisis yang akan disajikan dalam laporan ini berargumen bahwa buku tersebut berfungsi sebagai “detonator” intelektual, dirancang secara sadar oleh Syariati untuk memicu perubahan mentalitas dan aksi nyata. Hal ini berbeda dari karya akademik tradisional yang seringkali mengidealkan netralitas. Tujuannya adalah transformasi, bukan sekadar transfer informasi, yang tercermin dari deskripsi berulang yang menyebut karyanya “menggerakkan” dan “menerangi massa”.
Oleh karena itu, Resensi ini melampaui batasan resensi buku konvensional. Laporan ini menggunakan Tugas Cendekiawan Muslim sebagai titik tolak untuk membedah proyek intelektual Syariati secara holistik. Kami akan menelusuri biografi intelektualnya, mengupas fondasi teologis dan sosiologis dari pemikirannya, mengeksplorasi kontroversi yang melingkupinya, dan menimbang warisan serta relevansinya, terutama dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan bernuansa kepada pembaca yang memiliki minat serius terhadap pemikiran Islam modern dan dinamika sosial-politik.
Ali Syariati lahir pada 24 November 1933, di desa Mazinan, provinsi Khurasan, Iran. Ia berasal dari keluarga miskin namun terhormat, yang ditandai oleh tradisi keulamaan orang tuanya. Ayahnya, Muhammad Taqi Syariati, bukanlah ulama konservatif, melainkan seorang tokoh progresif yang memandang Islam sebagai doktrin sosial dan filsafat yang relevan dengan zaman modern, bukan sebagai keyakinan pribadi yang memikirkan diri sendiri. Latar belakang keluarga ini menjadi landasan yang kuat bagi Ali Syariati untuk mengembangkan pemikiran yang berorientasi pada perubahan sosial.
Masa kecil Syariati dihabiskan dengan cara yang unik. Ia digambarkan sebagai sosok yang pendiam, tidak suka diatur di sekolah, tetapi sangat rajin membaca buku-buku di rumah hingga larut malam, terutama di bidang filsafat dan mistisisme. Sifat ini menunjukkan adanya dimensi spiritual yang mendalam, yang kemudian ia sintesiskan dengan analisis sosialnya. Pendidikan formalnya di Kolese Pendidikan Guru Masyahad dan Fakultas Sastra Persia di Masyhad, Iran, memberinya gelar BA. Karena kecerdasannya, pada tahun 1959, ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi ke Prancis.
Pendidikan di Sorbonne University, Paris, menjadi titik balik penting dalam pembentukan pemikirannya. Di sinilah Syariati mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan ide-ide dari pemikir Barat terkemuka seperti Franz Fanon, Jean-Paul Sartre, dan Karl Marx. Ia berhasil memperoleh gelar doktor di bidang Sosiologi dan Sejarah Agama, sebuah pencapaian yang membekalinya dengan alat analitis modern untuk mengkaji realitas sosial dari perspektif yang berbeda.
Di Prancis, Ali Syariati berhasil menyatukan ide-ide revolusioner Marxisme tentang perjuangan kelas dengan ajaran Islam Syiah. Perpaduan ini menjadi fondasi bagi “ideologi Islam revolusioner” yang ia ciptakan, yang merupakan respons terhadap kondisi Dunia Ketiga yang terjebak dalam cengkeraman imperialisme. Ia secara khusus terpengaruh oleh gerakan “Third Worldism” yang menekankan pentingnya perjuangan anti-kolonialisme.
Syariati mengembangkan pandangan baru terhadap Syi’ah yang ia sebut “Syi’ah Merah” (revolusioner), yang ia bedakan dari “Syi’ah Hitam” atau Syi’ah Safawi yang ia anggap konservatif, tidak revolusioner, dan didominasi oleh ulama tradisional. Ia berpendapat bahwa Syi’ah sejati tidak boleh hanya menunggu kedatangan Imam Mahdi yang ke-12, tetapi harus secara aktif berjuang untuk keadilan sosial, bahkan hingga mencapai mati syahid. Pandangan ini terangkum dalam ungkapan terkenalnya, “Setiap hari adalah Ashura, setiap tempat adalah Karbala,” yang menempatkan perjuangan Imam Husain sebagai model abadi bagi umat yang tertindas.
Kehidupan Syariati mencerminkan sintesis paradoksal yang menjadi ciri khas pemikirannya. Ia adalah seorang spiritualis yang mendalami mistisisme, namun juga seorang sosiolog yang memadukan ajaran agama dengan teori revolusi. Alih-alih memilih salah satu kubu, ia dengan sengaja menggabungkan keduanya melalui proses dialektika yang disengaja. Pengalaman di Prancis memberinya alat analitis Barat, sementara latar belakang keluarganya yang progresif memberinya keleluasaan untuk menafsirkan Islam secara kritis. Hasil dari dialektika ini adalah sebuah “pandangan dunia integralis” yang ia sebut sebagai jahanbini-yi tawhidi, sebuah teologi pembebasan yang melampaui dikotomi Timur-Barat atau spiritual-material.
Lakon Politik dan Kematian Misterius
Setelah kembali ke Iran, Syariati menjadi intelektual yang mempopulerkan gagasan revolusionernya di kalangan mahasiswa dan kaum muda. Di Prancis, ia telah mengorganisir Front Nasional Iran, sebuah organisasi yang menyatukan orang-orang Iran di Eropa dan Amerika untuk menentang rezim yang berkuasa. Dengan keberaniannya membongkar kezaliman dan kediktatoran Iran, Syariati dengan cepat menjadi target intelijen rahasia rezim, SAVAK.
Akibat aktivitasnya, Syariati dijebloskan ke penjara beberapa kali. Meskipun demikian, penindasan ini tidak memadamkan semangatnya, melainkan justru menguatkan posisinya sebagai pahlawan bagi kaum lemah dan tertindas. Pada tahun 1976, ia berhasil melarikan diri ke Paris dan kemudian ke London. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan perjalanannya ke Amerika Serikat, ia meninggal secara misterius di rumah temannya pada Juni 1977 Kematiannya diduga kuat disebabkan oleh kerja rapi intelijen SAVAK, menjadikannya salah satu syuhada dalam sejarah pergerakan rakyat Iran. Meskipun ia meninggal sebelum revolusi terjadi, gagasan-gagasannya tetap menjadi pemicu dan pondasi ideologis yang memimpin Imam Khomeini untuk diterima sebagai pemimpin revolusioner.
“Tugas Cendekiawan Muslim”: Anatomis Panggilan Aksi Syariati
Tugas Cendekiawan Muslim bukanlah sebuah buku tunggal dalam arti konvensional, melainkan kumpulan ceramah dan artikel yang disampaikan oleh Ali Syariati. Salah satu artikel sentral di dalamnya berjudul “Peranan Cendekiawan Muslim: Mencari Masa Depan Kemanusiaan; Sebuah Wawasan Sosiologis”. Di Indonesia, buku ini menjadi sangat populer berkat terjemahannya yang dilakukan oleh M. Amien Rais, seorang tokoh Islam modernis terkemuka. Buku ini pertama kali diterbitkan di Indonesia pada tahun 1980-an dan berhasil terjual habis dalam waktu singkat, menunjukkan resonansi pemikirannya di kalangan aktivis dan mahasiswa pada masa itu.
Sinopsis buku ini menekankan sebuah gagasan sentral: intelektual Muslim hanya akan memiliki makna dan fungsi bila mereka selalu berada di tengah-tengah rakyat, menerangi massa, dan melakukan pembaharuan ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih Islami. Syariati berargumen bahwa peran ini harus dipegang teguh, karena tanpa intelektual yang berkomitmen, masyarakat akan terjebak dalam kejumudan dan status quo.
Konsepsi Cendekiawan (Roushanfikr)
Di dalam karyanya, Syariati secara tegas mendefinisikan ulang makna seorang cendekiawan. Ia memperkenalkan istilah Roushanfikr, atau “cendekiawan tercerahkan,” sebagai sosok yang berbeda secara fundamental dari dua tipologi intelektual lain yang dominan di zamannya. Dua tipologi tersebut adalah:
- Akademisi/Intelektual Sekuler ala Barat: Tipe ini berfokus pada ilmu pengetahuan teknis dan profesionalisme, seringkali tanpa tanggung jawab moral atau sosial yang mendalam. Syariati mengkritik mereka sebagai individu yang rentan menjadi “budak uang dan kepentingan pribadi” karena pendekatan materialistik dan konsumtif yang mendominasi pemikiran Barat.
- Ulama Tradisional/Konservatif: Tipe ini cenderung terjebak dalam kejumudan (taqlid) dan ritual keagamaan yang pasif, seringkali mengabaikan isu-isu ketidakadilan sosial. Syariati mengkritik mereka karena gagal melihat Islam sebagai ideologi yang dinamis dan revolusioner, dan bahkan menuduh beberapa dari mereka menutup mata terhadap kemiskinan dan korupsi.
Sebaliknya, seorang Roushanfikr yang ia deskripsikan adalah seseorang yang memiliki “kesadaran kemanusiaan di masanya” dan “tanggung jawab sosial”. Mereka tidak harus berasal dari kalangan kaya atau memiliki gelar akademis yang tinggi; mereka bisa muncul dari kalangan rakyat jelata yang tidak diperhitungkan. Ciri utamanya adalah kesadaran kritis yang mendalam dan komitmen untuk menjadi agen perubahan.
Tabel 1: Perbandingan Tipe-Tipe Intelektual dalam Pandangan Ali Syariati
| Aspek Perbandingan | Ulama Tradisional | Akademisi Sekuler | Roushanfikr (Cendekiawan Tercerahkan) |
| Sumber Otoritas | Teks-teks keagamaan tradisional, ijma’ ulama konservatif | Sains, rasionalitas, teori-teori Barat | Wahyu (Al-Qur’an) dan akal kritis, berpihak pada rakyat |
| Peran Utama | Menjaga ritual dan tradisi, menjaga status quo | Mengembangkan ilmu pengetahuan teknis, profesionalisme | Agen perubahan sosial, pemicu kesadaran kritis |
| Fokus Utama | Masalah fikih, ritual, moralitas individual | Objektivitas ilmiah, akumulasi pengetahuan, karier | Keadilan sosial, pembebasan, perjuangan ideologis |
| Sikap terhadap Perubahan | Cenderung statis dan anti-perubahan (kejumudan) | Berorientasi pada evolusi teknologis, kurang sensitif terhadap masalah sosial | Revolusioner, aktif, positif, dan konstruktif |
| Hubungan dengan Massa | Terpisah atau elitis, seringkali berpihak pada penguasa | Terisolasi di menara gading, tidak terlibat dalam masalah rakyat | Menyatu dengan massa, menerangi dan memobilisasi rakyat |
| Tujuan Akhir | Keselamatan pribadi dan kepasifan sosial | Kemajuan teknologis dan material | Terwujudnya masyarakat ideal (ummah) yang adil dan berkeadilan |
Tanggung Jawab Moral dan Sosial Cendekiawan
Bagi Syariati, tugas utama seorang cendekiawan adalah memimpin masyarakat dari kondisi statis dan kejumudan menuju progresivisme dan dinamisme. Mereka harus menjadi “nabi sosial” yang mampu membawa rakyat menuju cita-cita mulia, yaitu kesejahteraan sosial dan pembebasan dari segala bentuk penindasan. Ini adalah sebuah konsep teologis dari peran kenabian, di mana intelektual modern mengambil alih tugas para nabi dalam membimbing umat dan menentang kezaliman.
Syariati secara tegas menyatakan bahwa ideologi, bukan sekadar ilmu atau filsafat, adalah pendorong revolusi yang sesungguhnya Ideologi menuntut kaum intelektual untuk memiliki komitmen, keyakinan, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif. Konsep ini adalah cara Syariati untuk “mengislamisasi” ideologi revolusioner, menempatkannya dalam kerangka spiritual-historis yang kuat. Keberadaan intelektual yang hanya cerdas secara teknologis tetapi lemah secara moral, yang tunduk pada materialisme, adalah ironi modern yang harus ditentang oleh seorang Roushanfikr.
Inti dari seluruh pemikiran Ali Syariati adalah Tauhid, yang ia tafsirkan secara radikal. Bagi Syariati, Tauhid bukanlah sekadar keyakinan teologis tentang keesaan Tuhan, melainkan sebuah pandangan dunia (worldview) yang utuh dan ideologi pembebasan yang komprehensif. Pandangan dunia Tauhid menolak adanya dikotomi atau pemisahan antara Tuhan, manusia, dan alam. Semua eksistensi terhubung dalam satu kesatuan organik.
Dalam kerangka ini, ketidakadilan sosial, penindasan, dan diskriminasi bukanlah masalah sekadar politik, melainkan manifestasi dari syirk, yaitu menyekutukan Tuhan. Dengan kata lain, setiap bentuk ketidaksetaraan adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar Tauhid. Oleh karena itu, Islam, yang didasarkan pada Tauhid, adalah satu-satunya ideologi revolusioner yang mampu membebaskan umat dari segala bentuk penindasan, baik politik, ekonomi, maupun kultural, yang dibawa oleh kolonialisme dan neokolonialisme Barat.
Dialektika Sejarah Habil dan Qabil
Ali Syariati mengembangkan filsafat sejarahnya dengan menginterpretasi ulang narasi Al-Qur’an tentang Habil dan Qabil. Ia melihat sejarah manusia sebagai “perjuangan abadi” yang terus-menerus antara dua kekuatan yang berlawanan. Qabil melambangkan kaum penindas (mustakbirin), yang terdiri dari raja, pemodal, dan aristokrat, yang berupaya menguasai dan menindas. Sebaliknya, Habil melambangkan kaum tertindas (mustadh’afin), yaitu rakyat biasa yang menjadi korban penindasan. Konflik ini, menurut Syariati, adalah mesin penggerak utama dalam sejarah manusia.
Konsep dialektika Habil dan Qabil ini merupakan kritik dan reinterpretasi yang brilian terhadap teori perjuangan kelas Karl Marx. Syariati mengganti basis ekonomi Marx dengan basis moral dan spiritual. Dengan demikian, ia berargumen bahwa Islam telah memiliki kerangka analisis sosialnya sendiri yang lebih unggul karena tidak hanya mempertimbangkan faktor materi, tetapi juga dimensi rohani dan moral manusia. Upaya “mengislamisasi” dialektika sejarah ini menunjukkan bahwa Syariati tidak menolak alat analisis Barat secara total, melainkan secara kritis mengadaptasinya untuk menciptakan sebuah ideologi yang relevan dengan zaman modern tanpa meninggalkan akar Islamnya.
Kritik terhadap Humanisme Barat dan Tradisionalisme Islam
Ali Syariati adalah seorang pemikir kritis yang pemikirannya bertentangan dengan penafsiran keagamaan tradisional dan pandangan sekuler Barat. Ia menargetkan kritik tajamnya kepada dua kubu ini:
- Kritik atas Humanisme Barat: Syariati mengkritik keras humanisme Barat—yang diwakili oleh liberalisme, Marxisme, dan eksistensialisme—karena ia menganggapnya mereduksi manusia menjadi homo economicus. Humanisme liberalisme, misalnya, dianggap mengarahkan pandangan manusia hanya pada hal-hal keduniaan dan mencampakkan yang bersifat metafisik, sehingga manusia lebih mengutamakan nafsu material dan konsumsi. Syariati menyebut fenomena ini sebagai “malapetaka modern” yang telah membawa manusia ke arah kerusakan dan kemerosotan kemanusiaan, membuat jiwa dan kultur spiritual manusia menjadi kering dan hampa.
- Kritik atas Islam Tradisional: Di sisi lain, Syariati juga tidak ragu mengkritik ulama konservatif yang ia anggap pasif dan terjebak dalam kejumudan. Ia membedakan antara “Islam yang dipeluk rakyat tertindas” dengan “Islam yang dipeluk ulama konservatif dan penguasa”. Ia menyerukan agar umat Islam kembali kepada Islam yang sejati, Islam yang memimpin perjuangan untuk keadilan dan persamaan, bukan Islam yang hanya terhenti pada ritual dan dogma yang ambigu. Kritik ini membuatnya bermusuhan dengan ulama konservatif yang menuduhnya menyimpang dari paradigma Syiah murni.
Peran Penerjemahan oleh M. Amien Rais
Masuknya pemikiran Ali Syariati ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran penting M. Amien Rais. Terjemahan buku Tugas Cendekiawan Muslim yang ia lakukan pada tahun 1980-an menjadi jembatan utama yang memperkenalkan gagasan-gagasan Syariati kepada publik Indonesia, terutama di kalangan aktivis dan mahasiswa. Buku ini mencapai popularitas yang luar biasa; edisi pertamanya terjual habis dalam waktu relatif singkat, sebuah indikasi kuat betapa pemikiran ini resonan di tengah-tengah masyarakat intelektual pada masa itu.
- Amien Rais sendiri dalam kata pengantarnya mengakui kebrilianan dan semangat “menggerakkan” dari Syariati, meskipun ia juga secara jujur mencantumkan perbedaan latar belakang mazhab (Syiah vs. Sunni), sebuah pengakuan yang menunjukkan pentingnya kejujuran intelektual dalam menyerap gagasan baru.
Pengaruh pada Gerakan Mahasiswa dan Intelektual Muslim Indonesia
Pemikiran Ali Syariati menawarkan sebuah alternatif ideologis yang sangat dibutuhkan bagi gerakan mahasiswa dan intelektual Muslim di Indonesia. Pada masa itu, mereka seringkali terjepit di antara pilihan-pilihan yang dianggap buntu: ideologi sekuler-nasionalis, komunis-Marxis, dan Islam fundamentalis yang pasif. Syariati menyediakan “jalan keempat,” yaitu ideologi Islam revolusioner yang didasarkan pada Tauhid sebagai fondasi pembebasan.
Konsep Roushanfikr dan Islam sebagai ideologi pembebasan memberikan inspirasi kuat bagi aktivis untuk berjuang melawan ketidakadilan dan tirani yang ada di Indonesia. Pemikiran Syariati relevan dengan upaya umat Islam di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan karakter dan mengislamisasi ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dibahas dalam beberapa kajian. Gagasan-gagasannya mendorong terbentuknya kesadaran kritis dan semangat perjuangan di kalangan kaum muda.
Relevansi di Era Kontemporer
Gagasan-gagasan Syariati, meskipun dirumuskan pada konteks Iran, tetap relevan untuk menghadapi problematik kontemporer di Indonesia. Konsep Roushanfikr sangat diperlukan untuk menantang “empat penjara sosial” (sifat dasar, sejarah, masyarakat, dan ego manusia) yang masih membelenggu masyarakat. Cendekiawan tercerahkan dibutuhkan untuk memimpin perjuangan melawan korupsi, ketidakadilan sosial, dan krisis moral yang masih mendera.
Seruan Syariati untuk “kembali kepada Islam” yang sejati—Islam yang berpihak kepada rakyat, yang menentang kezaliman, dan yang mempromosikan keadilan—masih bergema dan relevan dalam perdebatan tentang peran agama dalam politik dan masyarakat kontemporer. Pemikirannya membantu mengisi kekosongan intelektual bagi kaum muda yang tidak puas dengan pendekatan Islam tradisional yang pasif, tetapi juga menolak mentah-mentah ideologi Barat. Ini adalah bukti bahwa pemikiran Syariati berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan dialog antara ide-ide modern dan doktrin Islam, menciptakan sebuah kerangka kerja yang dinamis untuk perubahan.
Menakar Kritik dan Kontroversi seputar Ali Syariati
Ali Syariati adalah sosok pemikir yang kontroversial, pemikirannya bertentangan dengan ulama konservatif maupun pandangan sekuler Barat. Ia sering dituduh sebagai seorang Marxis yang bersembunyi di balik jubah Islam karena pendekatannya yang dialektis dan fokus pada perjuangan kelas. Namun, perlu dipahami bahwa Syariati tidak mengadopsi Marxisme secara mentah-mentah. Ia menggunakan teori perjuangan kelas Marx sebagai alat analisis untuk mengkritik kapitalisme, tetapi menolaknya sebagai pandangan dunia, karena ia melihatnya gagal dalam menjelaskan dimensi spiritual dan moral manusia.
Di sisi lain, Syariati juga dipandang menyimpang oleh mayoritas ulama Syiah. Kritik ini muncul karena pandangan-pandangannya yang non-tradisional, seperti penafsirannya tentang syura sebagai cara memilih pemimpin yang paling tepat, yang bertentangan dengan dogma Syiah tentang imamah sebagai warisan kenabian. Ia juga menafsirkan “buah terlarang” di surga sebagai pengetahuan simbolis, sebuah pandangan yang dianggap mirip dengan interpretasi Kristen. Tuduhan ini, yang bahkan sampai pada cap “Sunni, Baha’i, dan Wahhabi” oleh ulama konservatif, menunjukkan betapa radikal dan beraninya pemikiran Syariati dalam menantang institusi keagamaan tradisional.
Kesimpulan: Warisan Abadi Sang Cendekiawan Pemberontak
Analisis ini menyimpulkan bahwa Ali Syariati adalah seorang ideolog revolusioner yang berhasil menyintesiskan teologi, sosiologi, dan filsafat sejarah menjadi sebuah kerangka kerja yang kohesif dan dinamis. Kontribusi terbesarnya adalah merumuskan kembali Islam sebagai sebuah ideologi pembebasan dan mendefinisikan peran baru bagi intelektual Muslim sebagai Roushanfikr, atau cendekiawan tercerahkan.
Buku Tugas Cendekiawan Muslim adalah sebuah seruan abadi yang tetap relevan bagi para intelektual di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Ia mengingatkan bahwa ilmu dan gelar akademis tidak berarti tanpa kesadaran kritis, tanggung jawab moral, dan keberpihakan pada kaum tertindas. Gagasan-gagasan Syariati, seperti Tauhid sebagai pandangan dunia integral, dialektika Habil dan Qabil sebagai motor sejarah, dan kritik terhadap kejumudan ulama serta materialisme Barat, memberikan alat analisis yang kuat bagi siapa saja yang ingin memahami dan mengubah realitas sosial.
Meskipun Syariati meninggal dalam keadaan tragis, gagasan-gagasannya terus hidup dan berdialog dengan tantangan zaman. Warisan intelektualnya menginspirasi gerakan-gerakan sosial dan intelektual untuk memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan yang sejati. Ia adalah bukti bahwa seorang intelektual dapat menjadi kekuatan yang menggerakkan, asalkan ia berani menantang status quo, memiliki komitmen moral, dan tetap berpihak pada rakyat yang tertindas.