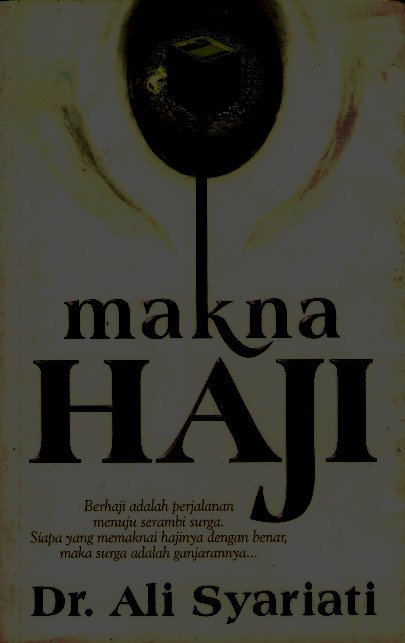Ali Syariati, seorang pemikir Muslim kontemporer yang berpengaruh, dikenal luas karena interpretasinya yang mendalam dan revolusioner terhadap Islam. Karyanya, “Makna Haji”, bukan sekadar panduan ritual, melainkan sebuah eksplorasi filosofis yang mengupas esensi ibadah haji sebagai drama eksistensial dan katalisator perubahan sosial. Untuk memahami kedalaman pandangan Syariati dalam buku ini, penting untuk menelusuri latar belakang intelektual dan konteks pemikiran yang membentuknya.
Latar Belakang Penulis: Biografi Singkat dan Konteks Intelektual Ali Syariati
Ali Syariati dilahirkan pada tahun 1933 di Mazinan, sebuah desa dekat Kota Sabzavar, Provinsi Khurasan, Iran. Beliau berasal dari keluarga terpandang yang memiliki garis keturunan pemuka agama. Ayahnya, Muhammad Taqi Syariati, adalah seorang pembaru yang bersemangat dalam studi agama, yang secara signifikan membentuk dimensi batin dan mengajarkan seni berpikir serta seni menjadi manusia kepada Ali Syariati muda. Ayahnya juga mendirikan “Pusat Penyebaran Kebenaran Islam” yang secara aktif mengkampanyekan Islam sebagai agama yang sarat dengan kewajiban dan komitmen sosial.
Pendidikan formal Ali Syariati dimulai di sekolah swasta Ibn Yamin pada tahun 1941, tempat ayahnya bekerja. Sejak kecil, ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam, sulit diatur, namun sangat rajin dan cenderung menyendiri. Perjalanan intelektualnya mencapai puncaknya pada tahun 1960 ketika ia meraih gelar doktor di bidang sosiologi dan sejarah Islam dari Universitas Paris, Prancis (Sorbonne), dengan beasiswa dan prestasi akademik yang memuaskan. Selama di Paris, ia berinteraksi dan menimba ilmu dari berbagai intelektual terkemuka, termasuk Louis Massignon, Jean-Paul Sartre, “Che” Guevara, Jacques Berque, Henri Bergson, dan Albert Camus. Pengalaman akademisnya dalam sosiologi Barat, ditambah dengan paparan terhadap pemikir revolusioner, tidak hanya bersifat teoretis. Pengalaman langsungnya dipenjara karena aktivitas politik dan pengaruh awal ayahnya tentang Islam sosial, membentuk jalur intelektual yang unik. Ini menunjukkan bahwa pengejaran ilmiahnya secara langsung diresapi dengan komitmen mendalam terhadap keadilan sosial dan pembebasan politik. Ia tidak hanya mempelajari sosiologi; ia menerapkannya untuk menganalisis dan mengkritik struktur masyarakat yang menindas pada masanya, mengubah konsep abstrak menjadi kerangka kerja untuk tindakan revolusioner yang konkret. Perpaduan mendasar antara ketelitian akademis dan semangat revolusioner inilah yang menjadikan “Makna Haji” lebih dari sekadar teks keagamaan.
Sepulangnya ke Iran, Syariati menghadapi penangkapan dan pemenjaraan beberapa kali akibat aktivitas politiknya dan kritik tajamnya terhadap rezim Syah Pahlevi. Meskipun demikian, ia tetap gencar menyuarakan kritikannya, yang membuatnya sangat populer di berbagai lapisan masyarakat dan kalangan mahasiswa. Ia wafat di Inggris pada tahun 1977, dua tahun sebelum Revolusi Iran, dalam keadaan yang menimbulkan kecurigaan.
Pemikiran Ali Syariati mengusung pandangan bahwa Islam adalah sebuah energi dan spirit yang membebaskan, sangat kontras dengan pandangan Karl Marx yang cenderung sinis terhadap agama. Ia secara meyakinkan menunjukkan bahwa Islam dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial dan politik. Syariati memperkenalkan konsep rausyan fikr, atau intelektual yang tercerahkan, yang memiliki peran krusial dalam membela kaum terpinggirkan dan tertindas. Pemikiran-pemikirannya tetap sangat berpengaruh di kalangan intelektual hingga saat ini. Berbagai sumber menegaskan pandangan Syariati tentang Islam sebagai “spirit yang membebaskan” dan “motor penggerak perubahan sosial maupun perubahan politik”. Ini secara langsung menentang pemahaman agama yang pasif dan ritualistik. Perjuangan pribadi dan pemenjaraannya bukan sekadar fakta biografis, melainkan bukti implikasi dari interpretasi radikalnya. Jika Islam adalah alat untuk perubahan sosial, maka menantang rezim yang menindas menjadi keharusan agama. Ini menunjukkan bahwa “Makna Haji” bukan hanya tafsir teologis tetapi juga manifesto politik, yang menawarkan pembenaran agama untuk perlawanan dan revolusi, menjadikannya teks yang berbahaya bagi kekuasaan otoriter.
Informasi Buku: Judul, Penerbit, dan Data Teknis
Buku yang menjadi objek resensi ini berjudul lengkap “Makna Haji” karya Ali Syariati. Diterbitkan oleh Zahra, Jakarta, pada tahun 2007. Buku ini memiliki ketebalan 260 halaman dan diidentifikasi dengan ISBN 9789792665185.
Posisi Buku dalam Pemikiran Islam Kontemporer: Sebuah Karya Istimewa“Makna Haji” merupakan salah satu karya monumental Ali Syariati yang secara tegas menunjukkan kepeduliannya terhadap dilema kehidupan modern, seperti industrialisasi, kolonialisme, komunisme, dan konsumerisme. Buku ini bukanlah sebuah kajian sosiologis murni terhadap ritual haji, melainkan sebuah risalah kontemplatif yang memuat pengalaman dan pemahamannya setelah menunaikan ibadah haji sebanyak tiga kali.
Syariati sendiri dengan jelas menyatakan tujuan bukunya: “Jika anda ingin tahu bagaimana cara haji, bacalah buku-buku fiqih. Jika anda ingin memahami makna haji, hargailah kemanusiaan universal. Dan jika anda hanya ingin mengetahui bagaimana saya memahami haji, bacalah buku ini. Barangkali membaca buku ini akan mendorong anda memahami haji, atau, setidaknya, dalam merenungkan barang sedikit tentang haji”. Pernyataan eksplisit Syariati yang membedakan karyanya dari buku-buku fiqh adalah indikator penting dari pendekatan metodologisnya. Ia tidak tertarik pada aspek prosedural (“bagaimana cara”) tetapi pada makna filosofis dan sosiologis (“mengapa” dan “untuk apa”). Ini menunjukkan upaya yang disengaja untuk mendekonstruksi pemahaman haji yang tradisional dan seringkali kaku sebagai ritual semata, dan memberikan makna baru yang lebih dalam dan luas, relevan dengan tantangan kemanusiaan dan masyarakat kontemporer. Tindakan menulis buku ini sendiri merupakan intervensi intelektual, yang berusaha membebaskan makna haji dari apa yang mungkin ia anggap sebagai interpretasi reduksionis.
Fokus buku pada “dilema kehidupan modern” menyiratkan bahwa Syariati melihat haji bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi sebagai penawar atau kerangka kerja potensial untuk menavigasi kompleksitas dan keterasingan modernitas. Dengan membingkai haji sebagai jalan menuju “hidup secara autentik (murni)”, ia menyarankan bahwa ziarah ini menawarkan cetak biru spiritual dan sosial untuk melawan kekuatan dehumanisasi dari industrialisasi, kolonialisme, dan konsumerisme. Hal ini meningkatkan signifikansi haji dari perjalanan spiritual pribadi menjadi respons kolektif masyarakat terhadap tantangan global.
Esensi Haji dalam Pandangan Ali Syariati: Melampaui Ritual Formal
Ali Syariati dalam “Makna Haji” tidak hanya menjelaskan tata cara ibadah, melainkan menggali inti filosofis di balik setiap ritual, mengangkat haji dari sekadar kewajiban formal menjadi sebuah perjalanan transformatif yang mendalam.
Haji sebagai Evolusi Eksistensial Manusia Menuju Allah
Menurut Ali Syariati, esensi ritual haji adalah evolusi eksistensial manusia menuju Allah. Ia menggambarkan haji sebagai drama simbolik dari filsafat penciptaan anak-cucu Adam. Dalam pandangannya, eksistensi manusia tidak memiliki makna kecuali jika tujuan hidupnya adalah untuk mendekati Roh Allah. Konsep “evolusi eksistensial manusia menuju Allah” yang dipadukan dengan “drama simbolik dari filsafat penciptaan anak-cucu Adam” menunjukkan bahwa Syariati memandang haji sebagai reka ulang simbolis yang terkondensasi dari seluruh perjalanan manusia dari penciptaan hingga tujuan akhirnya. Ini bukan hanya serangkaian tindakan, tetapi pengalaman ulang yang mendalam tentang asal-usul ilahi kemanusiaan dan takdir akhirnya. Hal ini menyiratkan bahwa ziarah adalah alat yang ampuh untuk penemuan diri dan pemahaman tempat seseorang dalam desain kosmik yang agung.
Haji sebagai Gerakan Pulang kepada Allah yang Mutlak
Syariati secara konsisten menyebut gelombang haji sebagai sebuah gerakan pulang kepada Allah Yang Maha Mutlak, yang tidak memiliki keterbatasan. “Pulang kepada Allah” ini dimaknai sebagai sebuah gerakan progresif menuju kesempurnaan, kebaikan, keindahan, kekuatan, pengetahuan, dan nilai absolut. Lebih dari sekadar tugas keagamaan, haji, menurut Syariati, adalah sebuah tujuan yang dengannya Tuhan memperbarui masyarakat. Bagi Syariati, ibadah haji merupakan sebuah “gerakan” yang mengandung makna ikhtiar (usaha), gerakan (aktivitas), kemajuan (progress), dan tujuan (purpose).
Penggunaan berulang kata “gerakan” dan makna-makna terkaitnya (usaha, kemajuan, tujuan) secara fundamental menggeser haji dari ritual statis menjadi proses dinamis. Ini adalah langkah konseptual yang disengaja untuk menekankan tindakan dan transformasi daripada sekadar kepatuhan. Implikasi paling signifikan di sini adalah hubungan eksplisit antara “gerakan” spiritual individu dan niat Tuhan untuk “memperbarui masyarakat”. Hal ini membangun rantai sebab-akibat langsung: dinamisme spiritual individu mengarah pada pembaharuan masyarakat secara kolektif, menempatkan haji sebagai tindakan mendasar untuk perubahan sosial. Jika haji adalah gerakan menuju “kesempurnaan, kebaikan, keindahan, kekuatan, pengetahuan dan nilai absolut” dan dimaksudkan untuk “memperbarui masyarakat”, maka secara implisit haji menjadi cetak biru bagi masyarakat manusia yang adil dan ideal. Ini menunjukkan bahwa Syariati membayangkan haji sebagai katalisator revolusi humanis, di mana pengejaran atribut ilahi oleh individu secara kolektif diterjemahkan menjadi masyarakat yang dibangun di atas keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia, secara aktif menantang sistem apa pun yang menyimpang dari nilai-nilai absolut ini.
Simbolisme Mendalam dalam Setiap Ritual Haji
Ali Syariati secara cermat menguraikan setiap tahapan ibadah haji, mengungkap makna simbolis yang melampaui dimensi ritualistik semata, dan mengaitkannya dengan transformasi diri serta perubahan sosial.
Niat: Pelepasan Ego dan Pencarian Cinta Ilahi
Niat dalam haji, menurut Syariati, bukan hanya sekadar tekad batin untuk beribadah, melainkan sebuah upaya tulus untuk menunaikan kewajiban, memastikan bahwa harta yang digunakan adalah halal, dan membawa jiwa yang berserah diri kepada Tuhan, bukan demi status sosial atau sanjungan duniawi. Simbolisme niat sangatlah luas: ia melambangkan tindakan meninggalkan rumah untuk menuju rumah umat manusia, meninggalkan hidup untuk memperoleh cinta ilahi, meninggalkan keakuan dan egoisme untuk berserah diri kepada Allah, meninggalkan penghambaan untuk memperoleh kemerdekaan, serta meninggalkan diskriminasi rasial untuk mencapai persamaan, ketulusan, dan kebenaran yang sejati. Syariati memperluas konsep niat melampaui sekadar niat internal untuk beribadah. Dengan secara eksplisit memasukkan “harta halal” dan “meninggalkan diskriminasi rasial” dalam makna simbolis niat, ia menanamkan tindakan mendasar ibadah ini dengan implikasi etika dan sosial yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa titik awal dari ziarah menuntut komitmen terhadap keadilan dan anti-diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, membuat perjalanan spiritual tidak terpisahkan dari tanggung jawab sosial.
Miqat: Kesadaran Kolektif dan Peleburan Identitas Duniawi
Miqat adalah simbol pelepasan diri dari sifat egoisme. Ini menandai tahap akhir usaha meninggalkan kebiasaan lama dan melepaskan diri secara totalitas dari kaitan-kaitan serta status duniawi dari masa lalu dan dari dosa. Di Miqat, setiap manusia harus berganti pakaian, melepaskan semua jenis ras, suku, dan identitas pakaian yang melekat, baik secara lahiriah maupun batiniah. Pakaian, dalam pandangan Syariati, melambangkan pola, preferensi, status, dan perbedaan yang menciptakan batas palsu dan perpecahan di antara manusia. Syariati menegaskan bahwa di Miqat, setiap orang “meleburkan” dirinya dan mengambil bentuk baru sebagai “manusia,” di mana semua ego dan kecenderungan individual terkubur, dan semua orang menjadi satu “bangsa” atau satu “ummah”. Ini juga mencakup pelepasan sifat-sifat kebinatangan seperti kekejaman (serigala), kelicikan (tikus), tipu daya (anjing), dan penghambaan (domba). Tindakan melepaskan semua pakaian dan identitas duniawi di Miqat bukan hanya persyaratan ritualistik untuk kesucian, tetapi tindakan simbolis radikal dari pemerataan sosial. Dengan menyamakan “pakaian” dengan “status, dan perbedaan” , Syariati berpendapat bahwa ini adalah konstruksi artifisial yang memecah belah kemanusiaan. Transformasi kolektif menjadi “satu ‘bangsa’ atau satu ‘ummah'” menandakan penolakan revolusioner terhadap stratifikasi sosial dan seruan untuk persatuan manusia sejati yang berakar pada identitas spiritual bersama. Ini adalah tantangan langsung terhadap divisi kelas, ras, dan nasionalisme.
Ihram: Kesucian, Kesetaraan, dan Pengingat Kematian
Ihram adalah rukun pertama haji, yaitu niat memasuki ibadah haji dengan menanggalkan pakaian biasa dan mengenakan pakaian ihram. Mengenakan pakaian ihram berarti melepaskan semua atribut duniawi dan menggantinya dengan pakaian takwa, serta melepaskan kebanggaan terhadap atribut duniawi yang sering melupakan Allah dan akhirat. Ritual ini melambangkan persamaan derajat kemanusiaan dan menimbulkan pengaruh psikologis bahwa kondisi ini adalah bagaimana seseorang akan menghadap Tuhan saat kematiannya. Pada titik ini, semua kesenangan dan kepemilikan dunia tidak lagi berlaku. Simbolisme Ihram melampaui kesucian ritual semata menuju pernyataan mendalam terhadap materialisme dan keterikatan duniawi. Tindakan “melepaskan semua atribut duniawi” dan “kebanggaan terhadap atribut duniawi” menyiratkan kritik terhadap masyarakat yang didorong oleh konsumerisme dan status. Dampak psikologis dari menyerupai keadaan seseorang saat kematian semakin memperkuat sifat sementara dari kepemilikan materi, mendesak para peziarah untuk memprioritaskan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan di atas akumulasi duniawi.
Tawaf: Rotasi Kosmis Menuju Pusat Eksistensi (Allah)
Tawaf adalah ritual berputar mengelilingi Ka’bah berlawanan arah jarum jam, dimulai dari Hajar Aswad sebanyak tujuh kali. Tawaf mengajarkan bahwa seorang yang beriman hendaknya berthawaf dengan hati mengikuti orbit ridha Allah, sebagaimana seluruh alam berkeliling mengelilingi orbit yang telah ditentukan Allah. Ka’bah melambangkan ketidakberubahan dan keabadian Allah, sementara lingkaran yang bergerak menunjukkan aktivitas dan transisi yang berkesinambungan dari makhluk-Nya. Syariati merumuskan Tawaf sebagai: “Ketidakberubahan + gerakan + disiplin = Tawaf”. Allah adalah pusat eksistensi, dan manusia adalah partikel bergerak yang harus mempertahankan jarak konstan dengan Ka’bah atau dengan Allah.Tawaf juga mengandung makna bahwa manusia harus menjadikan Allah sebagai titik orientasi dalam setiap gerak dan langkahnya, bergerak menuju kesempurnaan, merindukan keabadian, dan tidak pernah berhenti berproses. Rumus Syariati “Ketidakberubahan + gerakan + disiplin = Tawaf” adalah abstraksi filosofis yang kuat. “Ketidakberubahan” (Ka’bah/Allah) mewakili prinsip-prinsip ilahi yang tidak berubah, sedangkan “gerakan” (peziarah) dan “disiplin” (gerakan melingkar) mewakili aktivitas manusia. Ini menyiratkan hubungan sebab-akibat: tindakan manusia yang disiplin, ketika diorientasikan pada prinsip-prinsip ilahi yang tidak berubah, mengarah pada keberadaan yang harmonis dan terarah, mencerminkan tatanan kosmik. Ini adalah seruan untuk pendekatan yang terstruktur dan berprinsip terhadap kehidupan dan organisasi masyarakat, di mana semua tindakan pada akhirnya diarahkan pada kehendak Tuhan, memupuk persatuan dan kemajuan dalam umat.
Ka’bah: Simbol Ketetapan, Keabadian, Monoteisme, dan Universalitas
Bangunan Ka’bah yang berbentuk kubus segi empat, dalam pandangan Syariati, penuh dengan makna simbolik. Ka’bah menyimbolkan ketidakberubahan dan keabadian Allah. Ka’bah tampak kosong karena Allah tidak memiliki ‘bentuk’, tidak berwarna, dan tidak ada yang menyerupai-Nya. Ka’bah juga berfungsi sebagai simbol penunjuk arah, yang merepresentasikan sifat Tuhan yang tidak berpihak tetapi merahmati seluruh alam semesta. Ini secara kuat menyimbolkan monoteisme dan universalitas Allah. Ka’bah adalah tempat bertemunya Allah SWT, Nabi Ibrahim AS, Nabi Muhammad SAW, dan umat manusia, sehingga mereka yang berada di sana hendaknya tidak terpikat oleh pikiran egosentris. Lebih lanjut, Ka’bah adalah awal pergerakan abadi menuju Allah, bukan menuju Ka’bah itu sendiri. Ka’bah disebut “Rumah Allah” bukan berarti Allah bertempat di sana, melainkan karena orang yang berhaji adalah tamu istimewa Allah. Simbolisme Ka’bah sebagai “penunjuk arah” dan simbol “monoteisme dan universalitas” sangat penting. Kekosongannya menekankan transendensi Tuhan, mencegah penyembahan berhala. Ini menyiratkan bahwa Ka’bah berfungsi sebagai titik fokus universal yang melampaui semua pembagian buatan manusia (ras, nasional, kelas). Dengan mengarahkan semua doa dan ritual haji ke titik tunggal dan abstrak ini, Syariati memperkuat konsep tauhid tidak hanya sebagai keyakinan teologis tetapi sebagai prinsip untuk persatuan sosial dan egalitarianisme, di mana semua berdiri setara di hadapan Tuhan Yang Esa.
Hajar Aswad: Sumpah Setia dan Perjanjian dengan Tuhan
Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, yang melambangkan manusia telah memasuki sistem alam semesta. Di Hajar Aswad, manusia harus berjabat tangan dengan Allah dengan menyentuh atau melambaikan tangan, bersumpah setia untuk menjadi sekutu Allah, dan membebaskan setiap sumpah yang pernah dilakukan dengan pihak selain Allah di masa sebelumnya. Hajar Aswad dilambangkan sebagai tangan kekuasaan Allah, bentuk keabsahan tertinggi yang mengikat perjanjian hanya dengan Tuhan. Tindakan “membebaskan setiap sumpah yang pernah dilakukan dengan pihak selain Allah” adalah perpecahan simbolis yang kuat. Ini menyiratkan bahwa para peziarah tidak hanya menyatakan kesetiaan kepada Tuhan tetapi juga secara implisit menolak kesetiaan sebelumnya kepada sistem yang menindas, penguasa yang tidak adil, atau ideologi materialistis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilahi. Ini mengubah gerakan ritualistik menjadi deklarasi kemerdekaan spiritual dan politik, menjadikannya tindakan mendasar komitmen revolusioner.
Maqam Ibrahim: Realitas Sejarah dan Perjuangan Kenabian
Maqam Ibrahim adalah batu dengan jejak kaki Nabi Ibrahim saat meletakkan batu landasan Ka’bah. Berada di Maqam Ibrahim berarti memainkan peran Nabi Ibrahim dalam pertunjukan simbolis ini, bercermin dan mengikuti tahap-tahap sejarah kehidupannya yang penuh perjuangan, seperti menghancurkan berhala, perang melawan Namrud, menghadapi api, berjuang melawan iblis, dan mengorbankan Nabi Ismail. Ini melambangkan perjalanan dari fase kenabian menuju kepemimpinan, dari individualitas ke kolektivitas, dan dari penghuni rumah Azar menjadi pembangunan rumah tauhid (Ka’bah). Interpretasi Syariati tentang Maqam Ibrahim sebagai “memainkan peran Nabi Ibrahim” mengubah sejarah dari catatan statis menjadi cetak biru yang dinamis dan dapat ditindaklanjuti. Dengan mengajak para peziarah untuk menghidupkan kembali perjuangan Ibrahim melawan “berhala” dan tirani, ia secara implisit mendorong mereka untuk menghadapi bentuk-bentuk penyembahan berhala dan penindasan modern. Ini membangun hubungan sebab-akibat di mana narasi sejarah berfungsi sebagai panduan moral dan strategis untuk aktivisme sosial dan politik kontemporer, mendesak peziarah untuk mewujudkan semangat kenabian perlawanan.
Sa’i: Optimisme Hidup dan Perjuangan Mencari Kebenaran
Sa’i melambangkan perjuangan fisik dan usaha manusia mencari hidup, seperti Siti Hajar mencari air. Proses pencarian air ini melambangkan pencarian kehidupan materi di bumi. Dilakukan setelah tawaf, sa’i mengisyaratkan bahwa kehidupan dunia dan akhirat adalah satu kesatuan. Sa’i mengajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, manusia harus berusaha terlebih dahulu. Ini adalah isyarat kesediaan manusia untuk bertanggung jawab ke arah hal-hal positif dan bermanfaat guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Lebih dari itu, sa’i juga merupakan simbol perjuangan fisik totalitas dan kepasrahan manusia yang diwujudkan dengan usaha kuat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, logika, kebutuhan, hidup, fakta, materi, alam, hak istimewa, akal pikiran, sains, industri, keuntungan, kesenangan, kemauan, kekuasaan, ekonomi, dan peradaban di dunia ini. Urutan Tawaf (pengabdian spiritual) diikuti oleh Sa’i (perjuangan duniawi) tidaklah acak. Penekanan Syariati pada “kehidupan dunia dan akhirat adalah satu kesatuan” secara langsung menantang pemisahan dualistik antara kehidupan beragama dan keterlibatan duniawi. Daftar ekstensif tentang apa yang disimbolkan Sa’i (ilmu pengetahuan, industri, ekonomi, peradaban) menyiratkan hubungan sebab-akibat: komitmen spiritual yang tulus harus terwujud dalam keterlibatan aktif, cerdas, dan bertanggung jawab dengan dunia materi untuk membangun peradaban yang adil dan makmur. Ini adalah seruan untuk pengembangan manusia secara holistik, di mana iman mendorong kemajuan.
Arafah: Ilmu Pengetahuan dan Kearifan
Gerakan pertama haji dimulai dari Arafah dengan wukuf pada siang hari tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf berarti beristirahat, dan selama wukuf di Arafah, manusia mestinya mengistiratkan tenaga dan pikirannya dari aktivitas duniawi dengan melakukan kontemplasi dan bertafakkur kepada Allah. Wukuf di Arafah adalah momen untuk berpikir, berhenti dari kesenangan dunia agar mengerti hakikat hidup sesuai ketentuan Allah, di mana mengetahui dirinya dan Tuhannya adalah puncak tertinggi yang diraih melalui wukuf sebagai puncaknya ibadah haji. Jamaah haji harus melakukan perenungan, membuka diri dengan kejujuran di hadapan Allah untuk meraih kasih sayang-Nya. Di Arafah, jamaah haji harus menemukan ma’rifat (pengetahuan) sejati tentang jati dirinya dan akhir perjalanan hidupnya. Wukuf di Arafah dikatakan sebagai simbol pengetahuan, di mana evolusi pengetahuan menimbulkan kesadaran, melahirkan sains, dan meningkatkan pengertian serta kesadaran manusia. Di tempat ini, jabatan, pangkat, harta, dan kesuksesan duniawi tidak menjamin diterimanya amal. Arafah, yang sering dianggap sebagai momen doa yang intens, ditafsirkan ulang oleh Syariati sebagai “puncaknya ibadah haji” melalui lensa “ilmu pengetahuan dan kearifan”. Penekanan pada ma’rifat (gnosis/pengetahuan) dan gagasan bahwa “evolusi pengetahuan menimbulkan kesadaran, melahirkan sains” membangun hubungan sebab-akibat antara kontemplasi spiritual dan pencerahan intelektual. Ini menyiratkan bahwa keberhasilan sejati haji terletak pada peningkatan kesadaran kritis dan pemahaman peziarah tentang realitas sosial, bukan hanya kesalehan pribadi, sehingga mempersiapkan mereka untuk tindakan sosial yang terinformasi.
Muzdalifah (Masy’aril Haram): Kesadaran dan Intuisi untuk Masa Depan
Setelah matahari terbenam, jamaah haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, bermalam di sana sampai shalat subuh. Muzdalifah adalah simbol kesadaran dan intuisi, fase setelah mendapatkan pengetahuan, dimulai dengan ilmu baru kemudian kesadaran manusia untuk menyikapi pengetahuan tersebut. Wukuf di Masy’aril Haram dilakukan pada malam hari karena kesadaran adalah hubungan subjektif antara berbagai pemikiran, dan kekuatan pemahaman yang melahirkan kesadaran ini lebih mudah diperoleh dengan konsentrasi dalam kegelapan dan keheningan malam. Kesadaran yang harus dimunculkan adalah kesadaran untuk membangun hari esok yang lebih baik, tidak mengulangi kesalahan masa lalu, dan lebih kuat membuat perisai diri di tengah tantangan dan godaan setan. Muzdalifah berfungsi sebagai jembatan penting antara pencerahan intelektual Arafah dan perjuangan aktif Mina. Syariati menekankan “kesadaran dan intuisi” sebagai penerapan pengetahuan, yang mengarah pada komitmen untuk “membangun hari esok yang lebih baik”. Ini membangun hubungan sebab-akibat: pemahaman teoretis (Arafah) harus diinternalisasi menjadi kesadaran praktis (Muzdalifah) untuk menginspirasi perubahan proaktif yang berorientasi masa depan. Kontemplasi malam yang tenang dibingkai sebagai hal yang esensial untuk integrasi mendalam ini, mempersiapkan peziarah untuk “pertempuran” melawan kejahatan internal dan eksternal.
Mina: Cinta, Kesyahidan, dan Medan Pertempuran Melawan Godaan
Mina adalah negeri keyakinan dan cinta, harapan dan kebutuhan, sekaligus medan tempur untuk memperoleh kemenangan. Secara harfiah, Mina berarti tempat menumpahkan darah, atau Muna berarti tercapainya harapan. Ritual di Mina berkaitan erat dengan ketekatan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar dalam membuktikan ketinggian cita-cita mereka dan mengalahkan godaan setan. Peristiwa di Mina ini adalah tanda harapan, cita-cita, idealisme, dan cinta, di mana jamaah haji merenungkan apa yang paling diagungkan di hatinya (jabatan atau harta), dan siap mengorbankan segalanya hanya untuk Allah. Di sini, jamaah haji bertemu dengan Allah sekaligus setan, dan harus menentukan pilihan antara mengikuti panggilan Allah atau menuruti bujuk rayu setan. Mina secara eksplisit dibingkai sebagai “medan tempur” 12, mengubah ruang ritual menjadi medan perang simbolis. Makna ganda “Mina” (menumpahkan darah/mencapai harapan) merangkum semangat revolusioner: pengorbanan diperlukan untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Dengan mengharuskan para peziarah untuk menghadapi apa yang “paling diagungkan di hatinya” Syariati menyiratkan bahwa perjuangan adalah melawan keterikatan internal (materialisme, kekuasaan) yang menghalangi penyerahan diri yang tulus kepada Tuhan. Ini menjadikan Mina ujian komitmen tertinggi, di mana pengorbanan pribadi menjadi prasyarat untuk pembebasan kolektif.
Melempar Jumroh: Jihad Melawan Trinitas Kabilisme
Mina adalah garis depan pertempuran, dan tiga monumen jamarat adalah tiga berhala yang melambangkan setan yang menggoda manusia. Berhala pertama adalah ketamakan (Firaun), berhala kedua adalah mementingkan diri sendiri (Qarun), dan berhala ketiga adalah ketidakikhlasan (Bal’am). Ketiga berhala ini melambangkan satu entitas setan dengan tiga wajah atau tiga entitas dengan sumber yang sama. Melempar jumroh menjadi simbol sikap tegas manusia untuk melakukan perlawanan dan melepaskan diri dari segala sifat buruk, permusuhan abadi dengan setan dan pengaruhnya, serta siap menolak godaan dan bisikan setan dalam menjalankan tugas dari Allah SWT. Setelah melempar jumroh, pertempuran selesai, dan jamaah haji merayakan kemenangan dengan berkurban, menanggalkan ihram, memotong rambut, dan kembali menjadi manusia seperti Nabi Ibrahim yang hidupnya berorientasi pada ibadah, amal shalih, dakwah, dan perjuangan. Identifikasi Syariati terhadap tiga jumrah dengan “Firaun (ketamakan), Qarun (mementingkan diri sendiri), dan Bal’am (ketidakikhlasan)” adalah reinterpretasi yang langsung, kuat, dan revolusioner. Tokoh-tokoh ini masing-masing mewakili tirani politik, eksploitasi ekonomi, dan kemunafikan agama. Ini menyiratkan bahwa tindakan merajam bukan hanya melawan setan yang abstrak tetapi melawan kejahatan sistemik yang melanda masyarakat. Hubungan kausal ini mengubah ritual menjadi tindakan simbolis jihad melawan struktur penindasan, mendesak para peziarah untuk membawa semangat perlawanan ini ke dalam kehidupan sehari-hari mereka setelah kembali.
Tahallul (Memotong Rambut): Syukur, Pembersihan Dosa, dan Pemikiran Positif
Memotong rambut atau tahallul adalah perwujudan rasa syukur dan kegembiraan setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Ibadah ini melambangkan keamanan dan kedamaian. Rambut yang tumbuh di kepala diibaratkan dosa-dosa yang telah dilakukan, dan mencukurnya ibarat menanggalkan dosa-dosa itu. Tahallul memberikan isyarat pembersihan, penghapusan sisa-sisa cara berfikir kotor, dan mengajarkan umat manusia untuk memiliki dan mengorbitkan pikiran yang baik dan positif. Meskipun Tahallul tampak sebagai tindakan pemurnian pribadi yang sederhana, Syariati memperluas maknanya untuk mencakup “penghapusan sisa-sisa cara berfikir kotor, dan mengajarkan umat manusia untuk memiliki dan mengorbitkan pikiran yang baik dan positif”. Ini menyiratkan bahwa pembersihan spiritual bukanlah tujuan akhir, melainkan persiapan untuk keterlibatan yang diperbarui dan positif dengan dunia. Pikiran yang dimurnikan kemudian mampu berkontribusi secara konstruktif kepada masyarakat, menghubungkan ritual pribadi dengan manfaat sosial yang lebih luas.
Kurban: Kepasrahan Mutlak dan Peleburan Sifat Kebinatangan
Pada fase kurban, jamaah haji diajak berperan sebagai Nabi Ibrahim yang membawa anaknya untuk dikorbankan, karena kecintaan beliau terhadap Nabi Ismail telah menyibukkannya dari tanggung jawab kepada Allah. Fase ini adalah peperangan terbesar melawan diri sendiri (jihad akbar), di mana Nabi Ibrahim dihadapkan pada konflik memilih antara Allah dan putranya. Peristiwa ini mengingatkan bahwa yang dikurbankan bukanlah manusia, melainkan sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia. Penyembelihan hewan kurban adalah simbolisasi jihad akbar, yaitu menyertakan niat untuk menyembelih nafsu kebinatangan (keegoisan, kerakusan, keserakahan, ketamakan, dan sifat buruk lainnya). Dengan berkurban, berarti berpihak kepada hati nurani yang diterangi cahaya keilahian, mengungkapkan rasa syukur atas karunia Allah, dan bersedekah kepada fakir miskin dengan niat ikhlas demi Allah dan kesejahteraan mereka. Reinterpretasi Syariati tentang kurban sebagai jihad akbar (jihad yang lebih besar) melawan “sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia” adalah langkah filosofis yang krusial. Ia berpendapat bahwa mengatasi keburukan internal (egoisme, keserakahan) adalah prasyarat untuk secara efektif memerangi ketidakadilan eksternal. Ini membangun hubungan sebab-akibat: transformasi moral pribadi adalah fondasi bagi tindakan sosial dan politik yang bermakna. Tindakan amal kepada kaum miskin lebih lanjut menghubungkan perjuangan internal ini dengan hasil keadilan sosial yang konkret.
Tahap Pasca Pelaksanaan: Haji sebagai Keberlanjutan Transformasi
Berhaji, dalam pandangan Syariati, adalah sarana untuk mengubur hasrat dan ambisi duniawi. Setiap ritual haji dari awal hingga akhir memiliki rahasia untuk melatih manusia agar mampu menjalankan nilai hajinya dalam kehidupan. Haji adalah tindak mujahadah (perjuangan) untuk memperoleh musyahadah (penyaksian tentang Tuhan). Haji melambangkan egalitarianisme, yaitu pengamalan nilai-nilai kemanusiaan universal yang mencakup kesamaan, tenggang rasa, tawadu’, dan nilai Islam yang melahirkan patriotisme, nasionalisme, dan semangat persatuan. Setelah pulang, nilai-nilai yang didapatkan harus dijaga agar hajinya menjadi haji yang mabrur, yaitu menjadi insan yang semakin dekat dengan Allah dan menjadi manusia yang rahmatan lil’alamin (rahmat bagi seluruh alam). Ini berarti menjadi muslim yang memiliki karakter Islam sejati dan mukmin yang memiliki karakter iman sejati, senantiasa beraqidah tauhid, ikhlas, dzikrullah, dan muttaqin, serta selalu menjaga diri dari hal yang merusak dan berusaha melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara lahiriah maupun batiniah. “Tahap Pasca Pelaksanaan” bukanlah sekadar tambahan, melainkan puncak dari filosofi Syariati. Dengan menekankan bahwa “nilai hajinya” harus “dijalankan dalam kehidupan” dan mengarah pada menjadi rahmatan lil’alamin , ia mengubah haji dari peristiwa yang terbatas menjadi keadaan kesadaran revolusioner dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Ini menyiratkan bahwa ziarah adalah tempat pelatihan untuk komitmen seumur hidup terhadap keadilan, persatuan, dan kemajuan manusia, menjadikan haji mabrur bukan hanya status spiritual tetapi keharusan sosial dan etika.
Tabel 1: Simbolisme Ritual Haji dalam Perspektif Ali Syariati
| Ritual Haji | Simbolisme Utama | Makna Filosofis/Sosiologis |
| Niat | Pelepasan Ego dan Pencarian Cinta Ilahi | Meninggalkan egoisme, mencari cinta, kemerdekaan, persamaan, ketulusan; memastikan harta halal dan menolak diskriminasi rasial. |
| Miqat | Kesadaran Kolektif dan Peleburan Identitas Duniawi | Melepaskan atribut duniawi, ego, sifat kebinatangan (kekejaman, kelicikan, tipu daya, penghambaan), menjadi satu ummah yang setara. |
| Ihram | Kesucian dan Kesetaraan | Melepaskan atribut duniawi, mengenakan pakaian takwa, melambangkan persamaan derajat kemanusiaan, dan pengingat kematian. |
| Tawaf | Rotasi Kosmis Menuju Pusat Eksistensi (Allah) | Berputar mengelilingi Ka’bah, Allah sebagai pusat; manusia bergerak menuju kesempurnaan dengan disiplin, menjadikan Allah orientasi setiap langkah. |
| Ka’bah | Simbol Ketetapan, Keabadian, Monoteisme, dan Universalitas | Pusat agama, arah sholat, cinta, hidup, kematian; penunjuk arah yang tidak berpihak, tempat bertemu umat manusia, awal pergerakan abadi menuju Allah. |
| Hajar Aswad | Sumpah Setia dan Perjanjian dengan Tuhan | Berjabat tangan dengan Allah, bersumpah setia, membebaskan diri dari sumpah/allegiance kepada pihak selain Allah (misalnya, penguasa zalim). |
| Maqam Ibrahim | Realitas Sejarah dan Perjuangan Kenabian | Memainkan peran Nabi Ibrahim; merefleksikan perjuangan melawan berhala, tirani, dari individualitas ke kolektivitas. |
| Sa’i | Optimisme Hidup dan Perjuangan Mencari Kebenaran | Perjuangan fisik mencari kehidupan materi di bumi; dunia dan akhirat adalah satu kesatuan; usaha untuk ilmu, materi, dan pembangunan peradaban. |
| Arafah | Ilmu Pengetahuan dan Kearifan | Wukuf sebagai kontemplasi; menemukan ma’rifat diri dan Tuhan; evolusi pengetahuan yang menimbulkan kesadaran dan sains; humility di hadapan Allah. |
| Muzdalifah (Masy’aril Haram) | Kesadaran dan Intuisi untuk Masa Depan | Fase setelah mendapatkan pengetahuan; kesadaran untuk menyikapi pengetahuan tersebut; membangun hari esok yang lebih baik, tidak mengulangi kesalahan masa lalu. |
| Mina | Cinta, Kesyahidan, dan Medan Pertempuran Melawan Godaan | Negeri keyakinan, cinta, harapan, dan medan tempur; siap berkorban segalanya untuk Allah; memilih antara panggilan Allah atau godaan setan. |
| Melempar Jumroh | Jihad Melawan Trinitas Kabilisme | Perlawanan terhadap ketamakan (Firaun), mementingkan diri sendiri (Qarun), dan ketidakikhlasan (Bal’am); simbol perlawanan terhadap penindasan dan sifat buruk. |
| Tahallul (Memotong Rambut) | Syukur, Pembersihan Dosa, dan Pemikiran Positif | Perwujudan rasa syukur; menanggalkan dosa; pembersihan cara berfikir kotor; mengajarkan untuk memiliki dan mengorbitkan pikiran yang baik dan positif. |
| Kurban | Kepasrahan Mutlak dan Peleburan Sifat Kebinatangan | Peperangan terbesar melawan diri sendiri (jihad akbar); menyembelih nafsu kebinatangan (keegoisan, kerakusan, keserakahan); berpihak pada hati nurani; beramal kepada fakir miskin. |
Tabel ini sangat berharga karena Ali Syariati menyajikan interpretasi haji yang kaya, berlapis, dan seringkali abstrak. Menyajikan informasi ini dalam narasi linier dapat menjadi terlalu banyak bagi pembaca. Sebuah tabel segera memecah kompleksitas ini menjadi informasi yang terstruktur dan mudah dicerna. Untuk setiap ritual haji, tabel dengan jelas menggambarkan simbolisme utamanya dan makna filosofis/sosiologisnya yang lebih dalam. Hal ini memungkinkan pembaca, terutama mereka yang kurang akrab dengan pemikiran Syariati, untuk dengan cepat memahami reinterpretasi inti dari setiap tahapan tanpa harus menyaring prosa yang panjang. Ini berfungsi sebagai panduan referensi cepat. Penerapan yang konsisten dari makna filosofis, sosiologis, dan revolusioner di seluruh ritual dalam tabel secara visual memperkuat tesis menyeluruh Syariati: bahwa haji jauh lebih dari sekadar serangkaian ritual formal. Ini menggarisbawahi pendekatannya yang konsisten untuk menanamkan setiap tindakan dengan implikasi mendalam bagi keberadaan manusia, keadilan sosial, dan transformasi kolektif, membuat keterkaitan ide-idenya menjadi jelas.
Dimensi Sosial, Politik, dan Revolusioner Haji
Salah satu kontribusi paling signifikan Ali Syariati dalam “Makna Haji” adalah penekanannya pada dimensi sosial, politik, dan revolusioner dari ibadah ini. Ia menolak pandangan haji yang semata-mata ritualistik, melainkan menempatkannya sebagai inti dari gerakan pembebasan dan persatuan umat.
Haji sebagai Ideologi Emansipasi dan Pembebasan
Syariati memandang Islam sebagai sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan, sangat berbeda dengan pemahaman mainstream pada masanya yang cenderung membatasi Islam hanya pada agama ritual dan fiqh yang tidak menjangkau persoalan politik dan sosial kemasyarakatan Baginya, Islam adalah kekuatan dinamis yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, menyediakan strategi melawan kezaliman, dan memberikan petunjuk untuk membela kaum tertindas.
Syariati secara tajam membedakan antara “Islam Abu Zar” dan “Islam Khalifah/Marwan”. “Islam Abu Zar” adalah Islam keadilan, kepemimpinan yang pantas, kebebasan, kemajuan, kesadaran, dan perjuangan. Sebaliknya, “Islam Khalifah/Marwan” adalah Islam yang melayani penguasa, aristokrasi, perbudakan, penawanan, pasivitas, dan ulama yang pasif. Kesyahidan Imam Husein di Karbala menjadi sumber inspirasi vital bagi kaum tertindas untuk memelihara Islam yang otentik, yaitu Islam Syi’ah revolusioner. Diskursus Syariati dalam “Makna Haji” tidak hanya menyentuh makna esoterik rukun ibadah haji, tetapi juga secara eksplisit berbicara tentang penderitaan, penindasan, dan kesyahidan, serta membangun gagasan pembebasan, kemerdekaan, dan perjuangan. Haji, dalam pandangannya, adalah sebuah “gerakan” yang mengandung makna ikhtiar, gerakan, kemajuan, dan tujuan. Perbedaan tajam Syariati antara “Islam Abu Zar” dan “Islam Marwan” adalah kritik langsung terhadap quietisme politik dan lembaga keagamaan yang dianggap terlibat dalam rezim yang menindas. Dengan secara eksplisit menghubungkan ritual haji dengan tema “penderitaan, penindasan, dan kesyahidan” dan membingkai Islam sebagai “ideologi emansipasi dan pembebasan” , ia secara efektif mempolitisasi kembali ibadah. Ini menyiratkan hubungan sebab-akibat di mana perjalanan spiritual haji dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran revolusioner yang secara aktif menantang dan membongkar struktur kekuasaan yang tidak adil.
Konsep Ummah dan Persatuan dalam Haji
Syariati menegaskan bahwa haji dimulai dengan menghimpun kesadaran individual menjadi kesadaran kelompok di Miqat. Pada titik ini, setiap orang “meleburkan” dirinya dan mengambil bentuk baru sebagai “manusia,” di mana semua ego dan kecenderungan individual terkubur, dan yang ada kini hanyalah “kita,” menjadi satu “bangsa” atau satu “ummah”. Dalam haji, Allah telah mengundang manusia dari tempat yang jauh untuk datang ke rumah-Nya sebagai tamu pribadi, tetapi kemudian, dalam tawaf, Allah menyuruh manusia untuk menyatu dengan
ummah. Syariati menyimpulkan bahwa Islam tidak menganggap hubungan darah, tanah, perkumpulan, atau kesamaan tujuan/pekerjaan sebagai dasar persatuan, melainkan monoteisme. Haji, dalam pandangannya, melambangkan egalitarianisme, yaitu pengamalan nilai-nilai kemanusiaan universal yang mencakup kesamaan, tenggang rasa, tawadu’, dan nilai Islam yang melahirkan patriotisme, nasionalisme, dan semangat persatuan. Transformasi dari “ego dan kecenderungan individual” menjadi “satu ‘bangsa’ atau satu ‘ummah'” di Miqat adalah tindakan simbolis yang kuat dalam membongkar fragmentasi masyarakat. Dengan menyatakan bahwa dasar persatuan Islam adalah monoteisme, bukan darah, tanah, atau suku , Syariati menawarkan visi universalistik yang melampaui nasionalisme sempit dan divisi etnis. Ini menyiratkan bahwa haji berfungsi sebagai realisasi praktis, meskipun sementara, dari komunitas global yang ideal (ummah), memberikan cetak biru tentang bagaimana kemanusiaan seharusnya berinteraksi, memupuk rasa tanggung jawab kolektif dan solidaritas melawan musuh bersama (misalnya, ketidakadilan, penindasan).
Perlawanan terhadap Penindasan dan Ketidakadilan melalui Spirit Haji
Melempar Jumroh di Mina adalah simbol jihad melawan trinitas Kabilisme, yang diidentifikasi sebagai ketamakan (Firaun), mementingkan diri sendiri (Qarun), dan ketidakikhlasan (Bal’am). Ini adalah sikap tegas untuk melakukan perlawanan dan melepaskan diri dari segala sifat buruk dan pengaruh setan. Syariati berpendapat bahwa jika tauhid (kesatuan Tuhan-Manusia-Lingkungan) adalah dasar, maka kondisi masyarakat yang memiliki diskriminasi sosial, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan dapat diklasifikasikan sebagai syirk (menentang tauhid). Ide-ide Syariati menjadi dasar kesadaran kolektif yang menentang rezim Syah Pahlevi dan menjadi jembatan bagi gerakan oposisi pra-revolusi. Islam, baginya, adalah pendorong perjuangan, ideologi, dan penggerak revolusioner, bukan sekadar ajaran ritual. Redefinisi syirk (politeisme) untuk mencakup “diskriminasi sosial, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan” adalah inovasi teologis yang radikal. Ini menyiratkan hubungan sebab-akibat langsung: jika Tuhan itu Esa, maka segala bentuk perpecahan atau ketidakadilan di antara umat manusia adalah penghinaan langsung terhadap Keesaan itu. Hal ini mengubah
tauhid dari konsep yang murni teologis menjadi prinsip sosio-politik yang kuat yang mewajibkan perlawanan aktif terhadap segala bentuk penindasan. Landasan teologis ini memberikan legitimasi moral dan agama untuk tindakan revolusioner, menjadikan haji sebagai tempat pelatihan untuk perjuangan ini.
Penerimaan, Relevansi Kontemporer, dan Kritik
Pemikiran Ali Syariati, khususnya yang tertuang dalam “Makna Haji”, telah memicu diskusi yang luas dan beragam, menempatkannya sebagai figur sentral dalam wacana Islam kontemporer.
Dampak dan Relevansi Pemikiran Syariati di Era Modern
Ali Syariati adalah sebuah fenomena dalam wacana pemikiran Islam kontemporer. Keistimewaannya terletak pada kemampuannya menawarkan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan fundamental tentang bagaimana umat Islam dapat hidup secara autentik (murni) di tengah pengalaman modern yang kompleks, seperti industrialisasi, kolonialisme, komunisme, konsumerisme, dan kebebasan berekspresi. Teologi makna Haji-nya dianggap relevan untuk mempertahankan kemurnian akidah di tengah tekanan ideologis modern.
Pemikirannya masih sangat berpengaruh di kalangan intelektual dan menjadi dasar kesadaran kolektif yang menentang rezim Syah Pahlevi. Bahkan, ide-idenya membuka jalan bagi Imam Khomeini untuk diterima sebagai pemimpin revolusioner. Teologi pembebasan Ali Syariati yang bercorak revolusioneristik memiliki relevansi yang kuat terhadap problematika yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Fokus Syariati pada “dilema kehidupan modern” dan tawarannya tentang haji sebagai sarana untuk “hidup secara autentik” menunjukkan bahwa ia melihat ziarah ini sebagai benteng budaya dan ideologis yang kuat melawan kekuatan modernitas Barat yang homogen dan mengasingkan. Ini menyiratkan bahwa haji, yang ditafsirkan melalui lensanya, menyediakan kerangka kerja bagi umat Islam untuk terlibat dengan modernitas tanpa kehilangan integritas spiritual dan budaya mereka, menawarkan “jalan ketiga” yang unik di luar kapitalisme atau Marxisme Barat.
Perbandingan dengan Pandangan Fiqh Tradisional dan Ulama Lain
Pemahaman Islam yang ditawarkan Ali Syariati sangat berbeda dengan pemahaman mainstream pada saat itu, yang ia anggap hanya sebatas agama ritual dan fiqh yang tidak menjangkau persoalan politik dan sosial. Syariati menyatakan ketidakpuasannya terhadap pandangan tradisional para ulama, yang menurutnya telah teracuni oleh skolastikisme yang abstrak. Ia memposisikan dirinya sebagai seorang pembaru yang bersemangat menerapkan metode baru dalam studi agama.
Sebagai seorang filosof, Syariati memandang haji di Mekah dari sudut yang tidak biasa. Baginya, haji bukan hanya realisasi formal rukun dan syarat, tetapi sebuah ritual suci dengan makna yang sangat dalam sebagai ekspresi diri dalam kehidupan manusia. Ia mengkritik ulama tradisional karena apatis terhadap ketidakadilan, sebagian karena oportunisme dan sebagian lagi karena pasif menunggu Imam Mahdi yang tersembunyi.
Syariati secara terus-menerus menghadapi tantangan dari ulama, terutama karena ia mengusulkan pendekatan baru terhadap paradigma Syiah. Banyak ulama Syiah memiliki pandangan yang berbeda dengan ide-ide Syariati, yang mereka anggap menyimpang dari model Syiah murni. Beberapa ulama fundamentalis merasa terganggu oleh kritik Syariati terhadap majelis mereka dan pandangannya bahwa ulama tertentu telah mengkhianati Islam dengan hanya memperluas pemahaman akhirat dan bersembunyi dari konflik duniawi seperti industrialisme, kapitalisme, imperialisme, dan Zionisme. Syariati berpendapat bahwa ulama semacam itu lebih suka melihat ke masa lalu daripada masa depan, sehingga menghambat kemajuan Muslim.
Ia juga mengkritik upaya ulama tertentu untuk menguasai analisis Islam, membuat kitab suci tidak dapat dipahami oleh orang awam, dan mendorong pengikut untuk meniru ulama secara buta, yang ia sebut sebagai “kejahatan psikis”.Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua ulama fundamentalis menentang pemikirannya. Imam Khomeini, misalnya, merupakan contoh ulama fundamentalis yang tidak anti-politik dan yang pemikirannya sejalan dengan beberapa gagasan revolusioner Syariati, meskipun ada perbedaan dalam pandangan kepemimpinan. Khomeini percaya bahwa politik, filsafat, sufisme, dan fiqh adalah bagian integral dari Islam.
Kritik terhadap Pemikiran Haji Ali Syariati
Meskipun pemikiran Ali Syariati tentang haji sangat berpengaruh dan revolusioner, terdapat beberapa kritik yang muncul, terutama dari kalangan ulama tradisional. Kritik utama seringkali berpusat pada penafsiran Syariati yang dianggap terlalu sosiologis dan filosofis, sehingga berpotensi menggeser fokus dari aspek fiqh dan ritualistik haji yang telah mapan dalam tradisi Islam. Beberapa ulama merasa bahwa pendekatan Syariati dapat mengurangi penekanan pada ketaatan formal dan syarat-syarat ibadah yang telah ditetapkan.
Selain itu, pandangan Syariati yang progresif dan terkadang kontroversial, seperti penafsirannya tentang tauhid yang mencakup perlawanan terhadap ketidakadilan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap syirk, juga memicu perdebatan. Beberapa ulama Syiah secara khusus menantang Syariati karena pendekatannya yang baru terhadap paradigma Syiah, bahkan melarang pembelian, penjualan, dan pembacaan tulisannya, serta menyerukan pengikut untuk tidak menghadiri ceramahnya. Kritik ini seringkali menyoroti perbedaan antara gagasan Syariati yang revolusioner dan pandangan yang lebih tradisional atau konservatif dalam Islam, terutama dalam kaitannya dengan peran ulama dan interpretasi teks-teks keagamaan.
Kesimpulan
Buku “Makna Haji” karya Ali Syariati adalah sebuah karya monumental yang melampaui batas-batas panduan ritualistik ibadah haji. Melalui lensa filosofis dan sosiologisnya, Syariati berhasil mendekonstruksi pemahaman konvensional tentang haji dan merekonstruksinya sebagai sebuah drama simbolik dari evolusi eksistensial manusia menuju Allah, sebuah gerakan pulang yang dinamis menuju kesempurnaan dan pembaruan masyarakat.
Pemikiran Syariati menegaskan bahwa setiap ritual haji, mulai dari niat hingga kurban, sarat dengan makna mendalam yang relevan dengan kehidupan sosial dan politik. Ia mengubah Miqat menjadi ruang egalitarianisme radikal, Ihram menjadi proklamasi anti-materialisme, Tawaf sebagai model disiplin kosmis, Ka’bah sebagai manifestasi tauhid sosial, Hajar Aswad sebagai deklarasi kemerdekaan spiritual dan politik, Maqam Ibrahim sebagai pemandu aksi kontemporer dari sejarah kenabian, Sa’i sebagai integrasi spiritual dan material untuk pembangunan peradaban, Arafah sebagai puncak pencerahan intelektual, Muzdalifah sebagai translasi pengetahuan menjadi komitmen aksi, Mina sebagai teater jihad akbar, Melempar Jumroh sebagai aksi simbolis anti-sistemik terhadap ketamakan, egoisme, dan kemunafikan, Tahallul sebagai pembaruan diri untuk kontribusi sosial, dan Kurban sebagai jihad internal yang menjadi prasyarat bagi jihad eksternal.
Secara keseluruhan, “Makna Haji” adalah sebuah seruan untuk re-politisasi ibadah, menjadikan haji sebagai ideologi emansipasi dan pembebasan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, persatuan (ummah), dan perlawanan terhadap penindasan. Buku ini tidak hanya relevan di era modern sebagai model ketahanan budaya dan ideologis terhadap tantangan global, tetapi juga menjadi landasan teologis bagi revolusi sosial. Meskipun menghadapi kritik dari pandangan fiqh tradisional dan ulama tertentu yang menganggap interpretasinya terlalu filosofis dan berpotensi menggeser fokus ritual, “Makna Haji” tetap menjadi salah satu karya terpenting dalam pemikiran Islam kontemporer yang terus menginspirasi dan memprovokasi refleksi mendalam tentang hubungan antara spiritualitas, keadilan sosial, dan perubahan revolusioner.
Daftar Pustaka :
- HUMANISTIK DAN TEOLOGI PEMBEBASAN ALI SYARIATI (TELAAH ATAS PEMIKIRAN ALI SYARIATI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP KAJIAN ISLAM KONTE, diakses Agustus 17, 2025, https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/viewFile/11737/7227
- 25 BAB III PEMBAHASAN KONSEP ISLAM REVOLUSI DALAM …, diakses Agustus 17, 2025, http://digilib.uinsa.ac.id/880/6/Bab%203.pdf
- Pemikiran Ali Syari’ati dalam Sosiologi (Dari Teologi Menuju Revolusi) Faiq Tobroni – Neliti, diakses Agustus 17, 2025, https://media.neliti.com/media/publications/131769-ID-pemikiran-ali-syariati-dalam-sosiologi-d.pdf
- bab iii biografi dan pemikiran ali syariati, diakses Agustus 17, 2025, https://eprints.ummetro.ac.id/853/4/BAB%20III.pdf
- Pemikiran Ali Syari’ati dalam Sosiologi (Dari Teologi Menuju Revolusi), diakses Agustus 17, 2025, https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/1144
- Makna Haji /Ali Syariati – OPAC – Perpustakaan UT – Universitas Terbuka, diakses Agustus 17, 2025, https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=20385
- Menyingkap Hakikat Makna Haji – NU Online, diakses Agustus 17, 2025, https://nu.or.id/pustaka/menyingkap-hakikat-makna-haji-ePypF
- bab iv refleksi ritual haji dalam pandangan ali syari’ati, diakses Agustus 17, 2025, https://idr.uin-antasari.ac.id/864/2/BAB%20IV.pdf
- KONSEP HAJI DALAM HUKUM ISLAM (Studi Pemikiran Ali Syari …, diakses Agustus 17, 2025, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/22525/1/2020_Ilham%20Rissing.pdf
- Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati – Journal, diakses Agustus 17, 2025, https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/356/236/
- Makna Haji di Mata Ali Syariati (3) – beritajatim.com, diakses Agustus 17, 2025, https://beritajatim.com/makna-haji-di-mata-ali-syariati-3
- PEMIKIRAN ALI SYA’RIATI DAN PERJUANGANNYA DALAM REVOLUSI ISLAM IRAN (1933-1977) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mempero – Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, diakses Agustus 17, 2025, http://digilib.uinsa.ac.id/47123/2/Muhammad%20Thoriqul%20Ihsan_A92216090.pdf
- ISLAM DAN PEMBERONTAKAN.pdf – Repository UIN Mataram, diakses Agustus 17, 2025, https://repository.uinmataram.ac.id/1935/1/ISLAM%20DAN%20PEMBERONTAKAN.pdf
- TEOLOGI PEMBEBASAN ALI SYARI’ATI (Kajian Humanisme dalam Islam) LIBERATION THEOLOGY OF ALI SYARI’AT I – INSTIKA, diakses Agustus 17, 2025, https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/download/131/84
- Relevansi Teologi Pembebasan Ali Syari’ati dalam Mengatasi …, diakses Agustus 17, 2025, https://journal.stfsp.ac.id/index.php/media/article/download/493/168/2065
- Haji Humanis – Kementerian Agama RI, diakses Agustus 17, 2025, https://kemenag.go.id/opini/haji-humanis-zQdU3