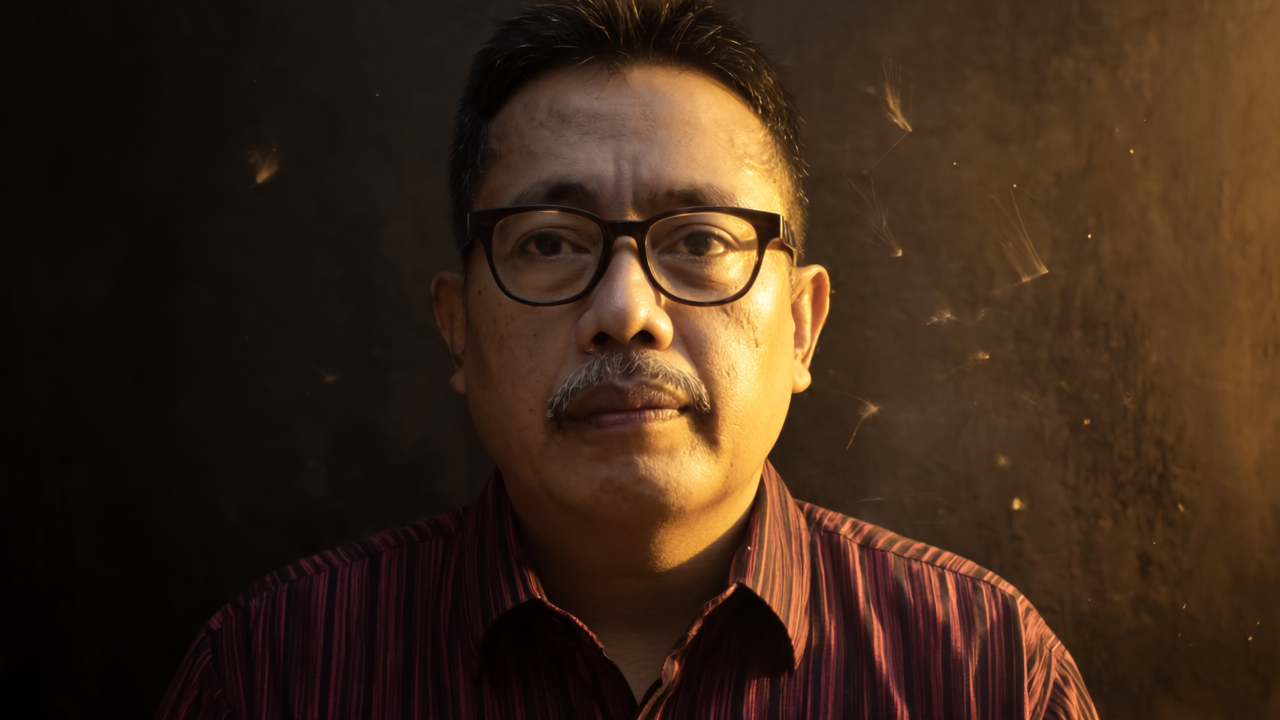PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKSISTENSIALISME DI INDONESIA
Abstrak
Filsafat eksistensialisme, yang berakar dari krisis eksistensial pasca-perang dunia di Barat, telah menemukan resonansi yang mendalam dalam lanskap intelektual Indonesia pasca-kemerdekaan. Laporan ini mengkaji perjalanan pemikiran eksistensialisme di Indonesia, mulai dari sejarah masuknya, saluran penyebarannya melalui institusi pendidikan dan penerbitan, hingga manifestasinya dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sastra, seni, dan pemikiran keagamaan. Analisis mendalam terhadap kontribusi tokoh-tokoh kunci seperti Driyarkara, Chairil Anwar, dan Iwan Simatupang menyoroti adaptasi unik filsafat ini dalam konteks budaya Indonesia, sering kali menghasilkan sintesis yang khas. Laporan ini juga membahas kritik-kritik yang muncul, khususnya dari perspektif keagamaan, serta relevansi berkelanjutan eksistensialisme dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti krisis identitas di era digital. Ditemukan bahwa eksistensialisme di Indonesia tidak hanya diadopsi, tetapi juga diinovasi, membentuk kerangka pemikiran yang dinamis untuk pemahaman diri, kebebasan, dan tanggung jawab dalam masyarakat yang terus berkembang.
Pendahuluan
Filsafat eksistensialisme merupakan salah satu aliran pemikiran besar yang muncul sebagai respons terhadap kondisi dunia yang tidak menentu, khususnya akibat perang dunia pada abad ke-20, yang menimbulkan kegelisahan dan ancaman terhadap eksistensi manusia. Gerakan pemikiran ini menonjolkan subjektivitas dan kebebasan manusia sebagai jalan keluar dari krisis tersebut, menekankan bahwa manusia harus menyadari keberadaannya untuk menguasai dirinya dan bertindak atas namanya sendiri. Secara historis, eksistensialisme berkembang pesat di Barat sejak awal abad ke-19, secara fundamental menentang doktrin esensialisme dari metafisika tradisional Barat yang menyamakan kebenaran dengan akal. Kaum eksistensialis berjuang untuk menegaskan sifat khas dan unik pribadi manusia yang sadar diri dan konkret sebagai individu, menekankan pentingnya kehendak dan kebebasan.
Konteks global yang ditandai oleh gejolak dan ketidakpastian pasca-perang dunia berfungsi sebagai katalisator kuat bagi penerimaan pemikiran eksistensialisme di Indonesia. Keadaan yang tidak menentu ini menciptakan resonansi universal, di mana pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, kebebasan, dan makna hidup menjadi sangat relevan. Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya, bangsa ini juga sedang menavigasi periode ketidakpastian yang besar, pembentukan identitas, dan keinginan untuk melepaskan diri dari esensialisme kolonial. Sifat “protes” eksistensialisme terhadap sistem tradisional yang mereduksi manusia menjadi objek atau roda gigi dalam mesin (seperti mekanisasi dan totaliterisme) secara alami menarik bagi sebuah negara yang baru merdeka dan sedang berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri serta agen individu warganya. Oleh karena itu, gejolak sosial-politik global secara kausal berkontribusi pada daya tarik dan adaptasi filsafat eksistensialisme dalam lanskap intelektual Indonesia pasca-kolonial.
Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perkembangan pemikiran eksistensialisme di Indonesia. Secara spesifik, laporan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
- Bagaimana sejarah masuknya pemikiran eksistensialisme ke Indonesia dan saluran penyebarannya?
- Siapa saja tokoh-toketokoh kunci di Indonesia yang berkontribusi dalam pengembangan dan adaptasi pemikiran eksistensialisme?
- Bagaimana manifestasi dan adaptasi eksistensialisme terlihat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sastra, seni, dan pemikiran keagamaan di Indonesia?
- Apa saja kritik-kritik yang dilontarkan terhadap eksistensialisme di Indonesia, khususnya dari perspektif keagamaan?
- Bagaimana relevansi eksistensialisme dalam konteks kontemporer Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan era modern?
Ruang Lingkup Pembahasan
Laporan ini akan membahas konsep dasar eksistensialisme dan tokoh-tokoh utamanya di Barat, diikuti dengan penelusuran sejarah masuk dan saluran penyebarannya di Indonesia. Bagian selanjutnya akan menguraikan kontribusi tokoh-tokoh kunci Indonesia dalam adaptasi pemikiran ini, serta manifestasinya dalam bidang pendidikan, sastra, seni, dan pemikiran keagamaan. Diskusi mengenai kritik dan relevansi kontemporer eksistensialisme di Indonesia akan melengkapi analisis ini.
I. Eksistensialisme: Konsep Dasar dan Akar Pemikiran
Definisi dan Ciri Utama Eksistensialisme
Eksistensialisme adalah sebuah ajaran filosofis yang memandang segala fenomena dari sudut pandang keberadaan (existence) manusia, menekankan bagaimana manusia “ada” di dunia atau yang dikenal dengan istilah Dasein. Berbeda secara fundamental dengan objek material yang tidak disadari, hanya manusia yang bereksistensi dan memiliki kesadaran akan keberadaannya. Manusia adalah subjek sekaligus objek, memiliki kemampuan untuk keluar dari dirinya dan menempatkan diri di dunia sebagai diri yang sadar.
Prinsip fundamental eksistensialisme adalah “eksistensi mendahului esensi”. Premis ini berarti bahwa manusia pertama-tama ada, muncul di dunia, dan baru setelah itu ia menentukan dirinya sendiri melalui pilihan dan tindakan yang ia buat. Implikasi dari prinsip ini sangat mendalam: manusia sepenuhnya bebas dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan apa yang ia ciptakan dari dirinya. Kebebasan ini bukanlah pemberian, melainkan suatu “kutukan” yang mewajibkan manusia untuk terus-menerus memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya.
Ciri-ciri penting lainnya dari eksistensialisme meliputi bereksistensi secara dinamis atau aktif menciptakan diri. Manusia dipandang sebagai realitas yang belum selesai dan terus dibentuk melalui perbuatan dan perencanaan. Ada penekanan kuat pada pengalaman eksistensial yang konkret, yang berbeda-beda pada setiap individu. Bersamaan dengan kebebasan ini, muncul pula pengalaman kegelisahan, ketakutan, dan absurditas yang tak terhindarkan, karena manusia dihadapkan pada ketiadaan makna yang inheren dan harus menciptakan maknanya sendiri. Konsep otentisitas juga menjadi inti, yang berarti hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan sejati diri, bukan sekadar mengikuti harapan sosial.
Eksistensialisme juga muncul sebagai bentuk protes terhadap metafisika tradisional, mekanisasi manusia, dan nilai-nilai budaya kontemporer yang dianggap mereduksi individualitas manusia. Aliran ini menentang reduksi realitas oleh batasan akal dan menyerukan resolusi kehendak dan kebebasan. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai pusat pemikiran dan kekuatan sejati, menolak objektivitas dan impersonalitas dalam bidang-bidang yang mengenai manusia.
Eksistensialisme, dengan penekanan berulang pada “manusia sebagai subjek” , prinsip inti “kebebasan dan tanggung jawab”, dan sifat eksistensi manusia yang dinamis dan belum selesai , secara kolektif menggambarkan filsafat ini bukan hanya sebagai disiplin akademis, melainkan sebagai gerakan humanistik yang mendalam. Karakterisasinya sebagai “protes” terhadap kekuatan-kekuatan seperti metafisika tradisional, industrialisasi, atau totaliterisme yang mereduksi manusia menjadi objek atau sekrup dalam sistem, mengungkapkan tujuan yang lebih dalam. Identitas fundamentalnya sebagai filsafat yang mengadvokasi pembebasan diri dan penciptaan diri manusia sangat penting untuk memahami daya tariknya dan adaptasi selanjutnya dalam berbagai konteks budaya, termasuk Indonesia, di mana kekhawatiran serupa tentang agen individu versus tekanan kolektif mungkin muncul.
Tokoh-tokoh Utama Eksistensialisme Barat
Pemikiran eksistensialisme di Barat dikembangkan oleh sejumlah filsuf terkemuka, masing-masing dengan penekanan dan nuansa yang berbeda, menunjukkan bahwa eksistensialisme bukanlah doktrin yang tunggal dan kaku, melainkan arus filosofis yang beragam. Keragaman ini memberikan banyak titik masuk dan interpretasi, yang memungkinkan berbagai aspek eksistensialisme beresonansi dengan konteks intelektual, budaya, dan keagamaan yang berbeda di Indonesia.
- Søren Kierkegaard (1813-1855): Diakui secara luas sebagai “Bapak Eksistensialisme” , Kierkegaard adalah seorang teolog dan filsuf Denmark yang menekankan eksistensi manusia yang konkret dan individual. Baginya, eksistensi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan suatu proses “menjadi” yang melibatkan perpindahan dari “kemungkinan” menuju “kenyataan” melalui pilihan dan keberanian. Ia adalah tokoh kunci dalam eksistensialisme teistik, yang berfokus pada hubungan individu dengan Tuhan dan pentingnya iman dalam menghadapi kecemasan eksistensial.
- Friedrich Nietzsche (1844-1900): Dikenal sebagai filsuf utama aliran eksistensialisme ateistik modern, Nietzsche menyoroti keberpihakan pada manusia setelah proklamasi “kematian Tuhan”. Pemikirannya berpusat pada konsep kebebasan manusia untuk menentukan diri dan menciptakan nilai-nilai baru dalam menghadapi kehampaan eksistensial.
- Jean-Paul Sartre (1905-1980): Sartre adalah salah satu tokoh eksistensialisme yang paling populer dan secara eksplisit menyebut dirinya sebagai eksistensialis. Ia memberikan premis dasar “Eksistensi mendahului esensi” , yang berarti manusia sepenuhnya bebas dan “terhukum untuk bebas”. Manusia bertanggung jawab penuh atas pilihan-pilihan yang dibuatnya, dan pandangannya tentang relasi antarmanusia berkembang dari konflik menuju cinta otentik.
- Martin Heidegger (1889-1976): Heidegger merumuskan istilah eksistensialisme pada masa awalnya, dengan akar metodologi dari fenomenologi Edmund Husserl. Ia menekankan keberadaan manusia (Dasein) di dunia dan bahwa manusia, meskipun “dilemparkan ke dalam keberadaan” tanpa menciptakan dirinya sendiri, tetap memiliki tanggung jawab atas eksistensinya.
- Albert Camus (1913-1960): Meskipun sering dikaitkan dengan eksistensialisme, Camus lebih dikenal dengan filsafat absurditasnya. Ia mengeksplorasi tema absurditas kehidupan dan pemberontakan manusia terhadapnya, menyoroti ketidakmungkinan menemukan makna inheren dalam alam semesta yang acuh tak acuh.
- Gabriel Marcel (1889-1973): Marcel adalah seorang eksistensialis Kristen yang menekankan pengalaman keagamaan dan dimensi transendental dalam eksistensi manusia. Ia berfokus pada misteri keberadaan, kesetiaan, dan harapan, yang kontras dengan pandangan ateistik.
- Karl Jaspers (1883-1969): Jaspers, seorang eksistensialis Jerman, menyoroti pengalaman pertentangan dalam eksistensi yang sulit didamaikan, serta kesadaran akan keterbatasan manusia seperti penderitaan, perjuangan, kesalahan, dan kematian (situasi perbatasan). Baginya, filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri melalui ilmu pengetahuan.
- Paul Tillich (1886-1965): Seorang teolog dan filsuf eksistensialis Kristen, Tillich mengartikan eksistensialisme sebagai pandangan hidup, ungkapan, dan gerakan, yang menegaskan universalitas eksistensi manusia dan perjuangan melawan dehumanisasi di masyarakat industri.
Keragaman ini, dengan berbagai fokus (teistik vs. ateistik, penekanan pada kematian, kebebasan, absurditas, pengalaman religius, atau situasi perbatasan) , menunjukkan bahwa eksistensialisme bukanlah doktrin yang tunggal dan kaku, melainkan arus filosofis yang beragam. Fleksibilitas dan multiplisitas interpretasi ini berarti bahwa ketika eksistensialisme diperkenalkan ke Indonesia, ia menawarkan berbagai titik masuk dan nuansa, memungkinkan aspek-aspek yang berbeda untuk beresonansi dengan konteks intelektual, budaya, dan keagamaan yang beragam di Indonesia. Kemampuan adaptasi ini berkontribusi signifikan terhadap pengaruhnya yang luas di berbagai domain (filsafat, sastra, pendidikan, agama) di Indonesia, karena dapat diadopsi dan ditafsirkan ulang secara selektif daripada menjadi proposisi monolitik.
II. Sejarah Masuk dan Perkembangan Awal Eksistensialisme di Indonesia
Konteks Sosial-Politik Pasca-Kemerdekaan yang Mendorong Penerimaan Filsafat Barat
Filsafat Barat Kontemporer, termasuk eksistensialisme, lahir di Eropa pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap pendewaan rasionalisme dan kritik terhadap dekonstruksi nilai-nilai yang ada. Setelah Perang Dunia II, eksistensialisme menjadi sangat populer dan meluas pengaruhnya ke berbagai bidang di luar filsafat, seperti teologi, drama, seni, sastra, dan psikologi.
Di Indonesia, pemikiran eksistensialisme mulai dikenal secara signifikan pasca-Perang Dunia II atau setelah kemerdekaan, khususnya setelah tahun 1949. Kondisi dunia yang tidak menentu akibat perang dunia menjadi pendorong utama munculnya eksistensialisme sebagai gerakan pemikiran yang menonjolkan subjektivitas dan kebebasan manusia di Indonesia. Paralel antara asal mula eksistensialisme di Barat yang lahir dari kondisi dunia yang tidak menentu akibat perang dunia dan periode pasca-kemerdekaan Indonesia sangat jelas. Kedua konteks tersebut ditandai oleh ketidakstabilan yang mendalam, pertanyaan tentang tatanan lama, dan pencarian makna baru. Bagi Indonesia, melepaskan diri dari kekuasaan kolonial berarti tidak hanya kemerdekaan politik, tetapi juga pencarian identitas nasional dan individu yang berbeda. Penekanan eksistensialisme pada “subjektivitas dan kebebasan manusia” dan sifatnya sebagai “protes” terhadap dehumanisasi akan sangat beresonansi dengan sebuah bangsa yang sedang mendefinisikan penentuan nasibnya sendiri dan agen warganya. Konteks sosial-politik ini menciptakan lahan intelektual yang subur, menjadikan eksistensialisme kerangka filosofis yang sangat relevan untuk memahami dan menavigasi kompleksitas Indonesia yang baru merdeka.
Periode Awal Diskusi dan Penerimaan (1950-an dan 1960-an)
Diskusi filsafat eksistensialisme mulai aktif dan menonjol di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Periode ini menandai keterlibatan formal awal dengan pemikiran eksistensialisme dalam lingkaran intelektual Indonesia. Fakta bahwa diskusi-diskusi ini terjadi dalam lingkungan akademis menunjukkan bahwa universitas dan komunitas ilmiah berfungsi sebagai inkubator penting bagi ide-ide ini, memindahkannya dari sekadar kesadaran menjadi perdebatan intelektual yang aktif dan penerimaan kritis. Institusionalisasi awal ini meletakkan dasar yang penting bagi penyebaran dan adaptasi eksistensialisme yang lebih luas ke berbagai domain masyarakat di dekade-dekade berikutnya.
Saluran Penyebaran: Peran Universitas, Penerbitan Buku, dan Majalah Ilmiah
Penyebaran pemikiran eksistensialisme di Indonesia tidak terlepas dari peran aktif berbagai saluran intelektual.
Peran Universitas: Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi pusat penting dalam penyebaran filsafat di Indonesia, termasuk eksistensialisme. Universitas Indonesia, misalnya, menekankan pandangan manusia sebagai subjek pemikiran, bukan objek, yang sejalan dengan inti eksistensialisme. Fakultas Filsafat UGM, yang berdiri kembali pada tahun 1967, secara aktif mengkaji pemikiran Barat, termasuk melacak perkembangan pemikiran filosofis dari masa ke masa, menunjukkan komitmen terhadap studi filsafat yang mendalam. Peran konsisten lembaga-lembaga utama ini dalam memfasilitasi studi dan diskusi filsafat menunjukkan bahwa pembentukan dan pertumbuhan infrastruktur intelektual formal sangat diperlukan untuk penyebaran ide-ide filosofis Barat yang kompleks seperti eksistensialisme di Indonesia. Platform-platform ini menyediakan ruang akademis yang diperlukan untuk studi, penerjemahan, publikasi, dan wacana kritis, secara efektif mengubah eksistensialisme dari konsep asing yang abstrak menjadi topik yang dapat diakses dan diperdebatkan dalam lingkaran intelektual Indonesia. Pendekatan terstruktur terhadap transfer pengetahuan ini merupakan faktor kunci bagaimana filsafat asing mendapatkan daya tarik yang mendalam dan beradaptasi secara lokal.
Penerbitan Buku: Penerbitan buku-buku tentang eksistensialisme memainkan peran vital dalam memperluas jangkauan pemikiran ini. Contoh signifikan adalah buku “Eksistensialisme Jean Paul Sartre” oleh H. Muzairi yang diterbitkan Pustaka Pelajar. Selain itu, terjemahan “Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre” oleh A. Setyo Wibowo yang diterbitkan Kanisius juga menjadi karya penting. Kanisius dan Pustaka Pelajar adalah penerbit awal yang signifikan dalam menyebarkan karya-karya ini, menjadikan teks-teks fundamental eksistensialisme lebih mudah diakses oleh pembaca Indonesia.
Majalah Ilmiah: Majalah Driyarkara, sebuah publikasi yang terafiliasi dengan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, berfungsi sebagai forum penting untuk diskusi eksistensialisme. Kontribusi dari intelektual seperti A. Setyo Wibowo dalam majalah ini menunjukkan perannya sebagai platform untuk wacana filosofis yang mendalam.
Identifikasi berulang terhadap penerjemah spesifik, seperti A. Setyo Wibowo , menyoroti peran penting mereka dalam transmisi ide-ide. Penerjemah lebih dari sekadar saluran linguistik; mereka bertindak sebagai jembatan budaya dan intelektual yang vital. Dengan menerjemahkan teks-teks filosofis Barat yang kompleks ke dalam bahasa Indonesia, mereka membuat ide-ide ini dapat diakses oleh khalayak yang jauh lebih luas, termasuk mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat umum, yang mungkin tidak memiliki akses ke bahasa aslinya. Tanpa upaya gigih mereka, keterlibatan langsung dengan karya-karya fundamental eksistensialisme akan sangat terbatas, sehingga secara signifikan menghambat pemahaman yang lebih dalam, keterlibatan kritis, dan adaptasi lokal pemikiran eksistensialisme di Indonesia. Ini menggarisbawahi peran yang sering diremehkan tetapi vital dari penerjemahan dalam membentuk tradisi filosofis nasional.
III. Tokoh Kunci dan Kontribusi dalam Pemikiran Eksistensialisme Indonesia
A. Driyarkara
Pengaruh Eksistensialisme dalam Pemikirannya: Driyarkara adalah seorang filsuf asli Indonesia yang pemikirannya sangat dipengaruhi oleh eksistensialisme. Ia memandang cara keberadaan manusia itu khas, yaitu “berada dalam dunia” (in der welt sein), yang merupakan kesatuan dan sekaligus dualitas yang paradoksal. Dalam kesadarannya, manusia dapat membedakan antara “aku” dan “bukan aku,” memisahkan diri dari dunia materi, namun pada saat yang sama, manusia hanya dapat hidup dan bereksistensi dalam penyatuan kesadarannya dengan dunia jasmani. Bahasa paradoksal semacam ini sering ditemukan dalam filsafat Driyarkara.
Konsep “Manusia Mendunia” dan “Homo Homini Socius” sebagai Adaptasi Khas Indonesia: Driyarkara secara signifikan menantang pandangan eksistensialis Barat yang cenderung pada “homo homini lupus” (manusia adalah serigala bagi manusia lain) dengan memperkenalkan konsepnya “homo homini socius” (manusia adalah teman bagi manusia lain). Ia menekankan bahwa melalui hidup bersama manusia lain, individu dapat mencapai penyempurnaan diri. Ini merupakan contoh utama dari adaptasi filosofis yang mendalam. Driyarkara tidak hanya mengadopsi eksistensialisme Barat, tetapi secara aktif terlibat dengannya, mengkritik aspek-aspek pesimisnya, dan menafsirkan ulang prinsip-prinsip intinya (kebebasan, tanggung jawab) melalui lensa Indonesia dan Katolik yang khas. Proses ini menunjukkan sintesis intelektual yang canggih di mana kekhawatiran filosofis universal diselaraskan dengan nilai-nilai komunal lokal dan kepercayaan spiritual. Ini adalah kontribusi intelektual yang signifikan, menunjukkan bahwa eksistensialisme di Indonesia bukanlah impor pasif, melainkan situs aktif transformasi intelektual, yang mengarah pada munculnya tradisi filosofis nasional yang unik yang mencerminkan realitas budaya dan etika spesifiknya.
Empat Corak Manusia Mendunia: Driyarkara menguraikan empat corak fundamental keberadaan manusia di dunia:
- Corak ekonomi: Mengacu pada kecenderungan manusia untuk mengubah segala sesuatu yang dilihatnya menjadi berguna.
- Corak kebudayaan: Ekspresi manusia terwujud dalam alam jasmani, di mana manusia “merohanikan diri dengan dan dalam menjasmanikan diri”. Kebudayaan menjadi perwujudan kehidupan manusia, melahirkan kreasi seperti candi, sastra, dan musik.
- Corak peradaban: Mendorong manusia melampaui sekadar memenuhi kebutuhan dasar, mempertimbangkan apa yang baik dan indah, serta mulai menyadari aspek kenyamanan dalam hidup.
- Corak teknis: Didefinisikan sebagai pengaktifan dunia fisik sesuai dengan hukum-hukumnya, yang mengarah pada efisiensi.
Relevansi Pemikirannya dalam Pendidikan dan Moralitas: Pemikiran Driyarkara secara konsisten direlasikan dengan dunia pendidikan di Indonesia. Ia berargumen bahwa karena manusia bereksistensi dengan empat corak ini, maka manusia mutlak membutuhkan moralitas. Tanpa moral, keberadaan manusia di dunia akan kacau dan dapat terdegradasi. Hati nurani dianggap sebagai ukuran moralitas. Driyarkara juga mengajarkan pentingnya keberanian menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang arti hidup dan keberadaan, serta menolak pengalihan perhatian dari kesenangan fisik yang dangkal yang dapat menjauhkan manusia dari pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang ada atau tidak ada, tentang hidup dan mati.
Koneksi yang konsisten dan eksplisit antara filsafat Driyarkara yang dipengaruhi eksistensialisme dan bidang pendidikan mengungkapkan implikasi yang lebih dalam bagi peran pendidikan di Indonesia. Bagi Driyarkara, pendidikan melampaui sekadar transfer pengetahuan; ini secara fundamental tentang menumbuhkan eksistensi manusia yang otentik dan tanggung jawab moral. Dengan menekankan perlunya moralitas dalam “keberadaan-di-dunia” manusia dan pentingnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mendalam, ia memposisikan pendidikan sebagai kendaraan utama di mana individu dapat mengaktualisasikan kebebasan dan tanggung jawab mereka secara bermakna dan etis. Perspektif ini mengangkat pendidikan ke fungsi sosial yang kritis, tidak hanya untuk pengembangan intelektual tetapi untuk pembentukan holistik manusia yang mampu menavigasi kompleksitas hidup dengan integritas dan tujuan.
B. Intelektual dan Seniman Lainnya
Pengaruh eksistensialisme di Indonesia melampaui ranah filsafat akademis, meresap ke dalam sastra, seni, dan bahkan pemikiran keagamaan, melalui kontribusi berbagai intelektual dan seniman.
Sastra:
- Chairil Anwar (Puisi): Dikenal luas sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia yang sajak-sajaknya sarat dengan pengalaman eksistensial. Karya-karyanya memanifestasikan tema-tema individualitas, kebebasan pribadi, kegelapan, ketakutan akan kematian, kesepian tragis, dan kehampaan. Puisi-puisi seperti “Kesabaran,” “Hampa,” “Kawanku dan Aku,” “Sia-Sia,” dan “Sendiri” secara kuat menunjukkan nada eksistensial, mencerminkan pergulatan batin Chairil Anwar dalam menghadapi kefanaan hidup. Slogannya yang terkenal, “Aku mau hidup seribu tahun lagi,” mencerminkan perjuangan abadi melawan kefanaan dan pencarian makna yang abadi.
- Iwan Simatupang (Novel dan Drama): Novel “Ziarah” karya Iwan Simatupang secara eksplisit menceritakan perjalanan hidup seseorang yang merefleksikan perjalanan eksistensial. Dalam naskah dramanya, seperti “Bulan Bujur Sangkar,” Iwan Simatupang banyak mengadaptasi pemikiran filsuf eksistensialisme Barat seperti Sartre dan Albert Camus. Ia bahkan secara provokatif mengubah slogan Rene Descartes “Cogito Ergo Sum” (aku berpikir maka aku ada) menjadi “Cogito ergo” (aku membunuh oleh sebab itu aku ada), menunjukkan eksplorasi ide-ide irasional dan simbolis dalam konteks eksistensial.
- Pramoedya Ananta Toer (Novel): Roman “Bumi Manusia” karya Pramoedya Ananta Toer menggambarkan perjuangan eksistensial tokoh Minke di tengah sistem feodalisme Jawa dan penindasan kolonial. Novel ini merefleksikan tema-tema kebebasan manusia untuk memutuskan keinginan dan tindakan, serta pengalaman kecemasan, ketakutan, dan pemberontakan sebagai manifestasi eksistensi di tengah keterbatasan sosial dan politik.
- Sapardi Djoko Damono (Puisi): Puisi “Prologue” karya Sapardi Djoko Damono menunjukkan konsep ideologi eksistensialisme, khususnya kesadaran manusia akan diri, lingkungan, dan hubungannya dengan Tuhan. Puisi ini mengejawantahkan manusia yang “ada,” “berada,” dan “mengada” melalui tanda-tanda dan metafora.
Seni Rupa:
Seniman juga menggunakan eksistensialisme sebagai kerangka untuk ekspresi kreatif. Hilman Cahya Kusdiana, misalnya, menerapkan teori eksistensialisme Kierkegaard dalam seni lukis simbolisme, di mana gagasan kebebasan tertinggi adalah meleburkan diri dengan Tuhan. Konsep ini disimbolkan melalui lukisan ikan koki pada media non-konvensional seperti gitar dan rebab, menunjukkan upaya seniman untuk melampaui batasan konvensional dalam mencari makna. Seniman lain seperti Dedy Sufriadi juga dikenal karena karyanya yang mempertanyakan dan menampilkan gagasan hidup di tengah absurditas, mencerminkan pergulatan eksistensial melalui medium visual.
Pengaruh eksistensialisme yang luas dan mendalam di berbagai bentuk seni dan sastra Indonesia—puisi (Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono), novel (Iwan Simatupang, Pramoedya Ananta Toer), drama (Iwan Simatupang), dan seni rupa (Hilman Cahya Kusdiana, Dedy Sufriadi) —menunjukkan peran penting seni dalam penerimaan eksistensialisme. Berbeda dengan teks filosofis akademis murni, ekspresi artistik dapat menyampaikan ide-ide filosofis yang kompleks melalui pengalaman emosional, estetika, dan naratif, menjadikannya lebih mudah diakses dan relevan bagi khalayak yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya menyerap ide-ide eksistensialisme tetapi juga menjadi platform vital untuk mempopulerkan, menafsirkan ulang, dan memulai dialog sosial yang lebih luas tentang kekhawatiran mendasar manusia—kebebasan, tanggung jawab, kecemasan, dan pencarian makna—dalam konteks budaya spesifik Indonesia. Seni, dalam pengertian ini, bertindak sebagai cermin yang merefleksikan realitas eksistensial dan ruang untuk keterlibatan publik dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam ini.
Peran Penerjemah dan Penulis: Selain tokoh-tokoh sastra dan seni, penerjemah dan penulis seperti H. Muzairi dan A. Setyo Wibowo sangat penting dalam memperkenalkan dan mengulas pemikiran eksistensialisme Barat di Indonesia. A. Setyo Wibowo, yang juga seorang Jesuit , dikenal sebagai pembicara yang sering mengulas pemikiran Sartre. Peran berulang A. Setyo Wibowo sebagai penerjemah dan pembicara publik tentang eksistensialisme, khususnya Sartre, merupakan pola yang signifikan. Ini menyoroti bahwa intelektual religius, terutama mereka dari ordo yang dikenal karena ketelitian intelektualnya seperti Yesuit , memainkan peran penting dalam memediasi dan menafsirkan ide-ide filosofis Barat yang kompleks untuk audiens Indonesia. Keterlibatan mereka menunjukkan upaya strategis dan disengaja untuk memperkenalkan dan mengkontekstualisasikan pemikiran-pemikiran ini dalam masyarakat yang didominasi agama, seringkali menjembatani potensi kesenjangan ideologis. Hal ini menunjukkan bagaimana komunitas intelektual tertentu, seringkali dengan komitmen institusional dan etika yang kuat, menjadi saluran utama untuk transmisi dan adaptasi filsafat asing yang kompleks, membentuk penerimaan dan integrasinya ke dalam lanskap intelektual lokal.
Tabel 1: Tokoh Kunci Eksistensialisme di Indonesia dan Kontribusinya
| Nama Tokoh/Seniman | Bidang Kontribusi | Kontribusi Spesifik (Konsep/Karya/Peran) | Pengaruh Filsuf Eksistensialisme Barat |
| Driyarkara | Filsafat, Pendidikan | Konsep “Manusia Mendunia,” “Homo Homini Socius,” Empat Corak Keberadaan Manusia, Relevansi Moralitas dalam Pendidikan | Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre (dikritik dan diadaptasi) |
| Chairil Anwar | Sastra (Puisi) | Sajak-sajak dengan tema individualitas, kebebasan, kegelisahan, kematian, kehampaan (“Aku mau hidup seribu tahun lagi”) | Hendrik Marsman, Nada eksistensialis secara umum (mirip Sartre) |
| Iwan Simatupang | Sastra (Novel, Drama) | Novel “Ziarah,” drama “Bulan Bujur Sangkar” (mengadaptasi “Cogito Ergo Sum” menjadi “Cogito ergo”) | Jean-Paul Sartre, Albert Camus |
| Pramoedya Ananta Toer | Sastra (Novel) | Roman “Bumi Manusia” (perjuangan eksistensial Minke) | Eksistensialisme secara umum (kebebasan, tanggung jawab, pemberontakan) |
| Sapardi Djoko Damono | Sastra (Puisi) | Puisi “Prologue” (kesadaran manusia akan diri, lingkungan, Tuhan) | Eksistensialisme secara umum (kesadaran, keberadaan) |
| H. Muzairi | Penerjemah, Penulis | Menerjemahkan dan mengulas “Eksistensialisme Jean Paul Sartre” | Jean-Paul Sartre |
| A. Setyo Wibowo | Penerjemah, Penulis, Teolog | Menerjemahkan “Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre,” mengulas pemikiran Sartre, Jesuit | Jean-Paul Sartre, Teologi Kristen Eksistensial |
| Hilman Cahya Kusdiana | Seni Rupa (Lukis Simbolisme) | Mengaplikasikan teori eksistensialisme dalam lukis simbolisme (ikan koki pada gitar/rebab) | Søren Kierkegaard |
| Dedy Sufriadi | Seni Rupa | Mengeksplorasi dan menampilkan gagasan hidup di tengah absurditas | Albert Camus, Eksistensialisme secara umum |
| Muhammad Iqbal | Teologi Islam | Pemikiran yang menunjukkan karakter dasar eksistensialisme (meskipun tidak secara eksplisit menyebut diri eksistensialis) | Eksistensialisme teistik (mirip Kierkegaard) |
| Ali Syari’ati | Teologi Islam | Eksistensialis religius (manusia dinamis, aktif, bebas berkreasi dalam batasan takdir Islam) | Eksistensialisme religius |
| Hasan Hanafi | Teologi Islam | Eksistensialis teistik (manusia independen, teologi Islam sebagai basis nilai spiritual) | Eksistensialisme teistik |
IV. Manifestasi dan Adaptasi Eksistensialisme dalam Berbagai Bidang di Indonesia
A. Pendidikan
Filsafat eksistensialisme memiliki kaitan yang sangat erat dan relevan dengan bidang pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang terus bertumbuh dan berkembang secara dinamis.
Pengaruh pada Kurikulum dan Pendekatan Pembelajaran: Eksistensialisme menekankan nilai-nilai kebebasan, tanggung jawab pribadi, dan keaslian, yang menjadi elemen krusial dalam mendefinisikan dan membentuk pendidikan modern. Penerapan prinsip-prinsip eksistensialisme dalam kurikulum pendidikan modern terbukti memberikan dampak positif, terutama dalam mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif, personal, dan berorientasi pada pengembangan individu secara holistik. Pendekatan kurikulum eksistensialis menempatkan siswa sebagai agen aktif yang memberikan makna pada materi pembelajaran, bukan hanya penerima pasif. Siswa didorong untuk memasukkan subjek ke dalam dirinya sendiri dan menafsirkannya sesuai dengan proyeknya sendiri. Pendekatan ini menantang konsep pendidikan tradisional yang berpusat pada standar dan otoritas, mendukung perubahan menuju teori pendidikan modern yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan individu.
Pengembangan Kesadaran Diri, Kemandirian, dan Tanggung Jawab Siswa: Tujuan pendidikan, dari perspektif eksistensialisme, adalah untuk menumbuhkan “intensitas kesadaran” siswa, sehingga mereka menyadari penuh tanggung jawabnya untuk menentukan arah dan makna kehidupan mereka sendiri. Filsafat ini mendorong setiap siswa untuk mengembangkan semua potensi dirinya demi pemenuhan diri yang otentik, karena setiap individu adalah makhluk yang unik dan bertanggung jawab atas diri dan nasibnya sendiri. Peran guru dalam konteks ini berubah menjadi fasilitator, konselor, atau figur orang tua yang membimbing siswa dalam mengembangkan kesadaran diri, kemandirian, dan kemampuan untuk menerima konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka. Guru tidak boleh memaksakan nilai yang ia anut kepada peserta didik atau memperlakukan siswa seolah-olah bodoh, melainkan harus mendorong perkembangan peserta didik agar lebih mandiri.
Penekanan yang konsisten dan meresap pada “kesadaran diri,” “kemandirian,” dan “tanggung jawab” dalam wacana pendidikan di Indonesia menandakan pergeseran mendalam dalam filosofi pedagogis. Ini melampaui instruksi intelektual semata, bertujuan untuk menumbuhkan individu yang aktif dan menentukan diri sendiri. Bagi para pendidik Indonesia yang dipengaruhi oleh eksistensialisme, tujuan akhir pendidikan melampaui hafalan atau pencapaian standar. Ini menjadi proses memelihara manusia otentik yang mampu membuat pilihan yang sadar dan bebas serta memikul tanggung jawab penuh atas hidup mereka. Hal ini sangat penting bagi negara berkembang, karena menyiratkan pembentukan warga negara yang tidak hanya terampil tetapi juga beretika dan sadar diri, yang mampu berkontribusi secara bermakna bagi masyarakat.
B. Sastra dan Seni
Analisis Tema Eksistensial dalam Karya Sastra (Puisi, Novel, Cerpen, Drama):
Sastra Indonesia telah menjadi medium yang kaya untuk mengeksplorasi tema-tema eksistensial.
- Puisi: Chairil Anwar dan Sapardi Djoko Damono adalah contoh utama penyair Indonesia yang karya-karyanya memanifestasikan tema-tema eksistensial seperti individualitas, kebebasan, kegelisahan, kematian, dan pencarian makna hidup. Sajak Chairil Anwar, seperti “Sia-Sia” dan “Sendiri,” menunjukkan suasana suram, kesepian, dan keputusasaan, mengingatkan pada drama eksistensialis Sartre. Puisi “Prologue” karya Sapardi Djoko Damono, di sisi lain, menunjukkan konsep ideologi eksistensialisme yang berfokus pada kesadaran manusia akan diri, lingkungan, dan hubungannya dengan Tuhan.
- Novel: “Ziarah” karya Iwan Simatupang dan “Bumi Manusia” karya Pramoedya Ananta Toer secara mendalam mengeksplorasi perjalanan hidup, perjuangan individu, kebebasan, dan pemberontakan tokoh-tokohnya dalam konteks sosial-politik yang relevan. “Bumi Manusia” secara khusus menggambarkan perjuangan eksistensial Minke di tengah sistem feodalisme Jawa dan penindasan kolonial, merefleksikan kebebasan untuk memutuskan keinginan dan tindakan, serta pengalaman kecemasan dan pemberontakan sebagai manifestasi eksistensi.
- Drama: Naskah drama Iwan Simatupang, seperti “Bulan Bujur Sangkar,” menunjukkan pengaruh kuat dari pemikiran Sartre dan Camus. Iwan bahkan secara provokatif mengubah slogan Rene Descartes “Cogito Ergo Sum” menjadi “Cogito ergo” (aku membunuh oleh sebab itu aku ada), yang merefleksikan eksplorasi ide-ide irasional dan simbolis dalam bingkai eksistensial.
Ekspresi Kebebasan dan Absurditas dalam Seni Rupa:
Seni rupa juga menjadi ranah manifestasi eksistensialisme. Seniman seperti Hilman Cahya Kusdiana mengaplikasikan teori eksistensialisme Kierkegaard dalam seni lukis simbolisme, di mana gagasan kebebasan tertinggi adalah meleburkan diri dengan Tuhan. Konsep ini diwujudkan secara visual melalui simbolisme ikan koki pada media non-konvensional seperti gitar dan rebab, menunjukkan bahwa kebebasan sejati adalah keikhlasan. Dedy Sufriadi juga dikenal karena karyanya yang mempertanyakan dan menampilkan gagasan hidup di tengah absurditas, mencerminkan pergulatan eksistensial melalui medium visual.
Manifestasi eksistensialisme yang luas dan konsisten di berbagai bentuk seni Indonesia (puisi, novel, drama, seni rupa) menunjukkan peran seni yang lebih dalam dalam penerimaan eksistensialisme. Tidak seperti teks filosofis akademis murni, ekspresi artistik dapat menyampaikan ide-ide filosofis yang kompleks melalui pengalaman emosional, estetika, dan naratif, menjadikannya dapat diakses dan relevan bagi khalayak yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya menyerap ide-ide eksistensialisme tetapi juga menjadi platform vital untuk mempopulerkan, menafsirkan ulang, dan memulai dialog sosial yang lebih luas tentang kekhawatiran mendasar manusia—kebebasan, tanggung jawab, kecemasan, dan pencarian makna—dalam konteks budaya spesifik Indonesia. Seni, dalam pengertian ini, bertindak sebagai cermin yang merefleksikan realitas eksistensial dan ruang untuk keterlibatan publik dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam ini.
Tabel 2: Manifestasi Eksistensialisme dalam Karya Sastra dan Seni Rupa Indonesia
| Nama Tokoh/Seniman | Judul Karya/Jenis Karya | Tema Eksistensial yang Menonjol | Keterkaitan dengan Filsuf Barat (jika ada) |
| Chairil Anwar | Puisi: “Kesabaran,” “Hampa,” “Kawanku dan Aku,” “Sia-Sia,” “Sendiri” | Individualitas, kebebasan pribadi, kegelapan, ketakutan akan kematian, kesepian tragis, kehampaan | Jean-Paul Sartre (nada serupa), Hendrik Marsman |
| Iwan Simatupang | Novel: “Ziarah”; Drama: “Bulan Bujur Sangkar” | Perjalanan hidup, kebebasan, absurditas, ide irasional, tanggung jawab | Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Rene Descartes (diadaptasi) |
| Pramoedya Ananta Toer | Novel: “Bumi Manusia” | Perjuangan eksistensial, kebebasan, kecemasan, ketakutan, pemberontakan | Eksistensialisme secara umum |
| Sapardi Djoko Damono | Puisi: “Prologue” | Kesadaran manusia akan diri, lingkungan, dan Tuhan; keberadaan (“ada,” “berada,” “mengada”) | Eksistensialisme secara umum |
| Hilman Cahya Kusdiana | Seni Lukis Simbolisme (Ikan Koki) | Kebebasan, meleburkan diri dengan Tuhan, otentisitas, melampaui konvensi | Søren Kierkegaard |
| Dedy Sufriadi | Seni Rupa (lukisan) | Gagasan hidup di tengah absurditas | Albert Camus (implisit) |
C. Pemikiran Keagamaan (Islam dan Kristen)
Penerimaan eksistensialisme di Indonesia juga meluas ke ranah pemikiran keagamaan, di mana konsep-konsepnya diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam teologi Islam dan Kristen.
Penerimaan dan Adaptasi Konsep Eksistensialisme dalam Teologi Islam:
Meskipun filsuf Muslim yang secara eksplisit menyebut diri sebagai eksistensialis masih jarang, pemikiran yang menunjukkan karakter dasar eksistensialisme dapat ditemukan dalam sejarah filsafat Islam. Muhammad Iqbal, seorang pemikir Muslim, diidentifikasi sebagai salah satu eksistensialis Muslim, meskipun ia tidak pernah secara langsung menyebut dirinya demikian. Pemikirannya tentang aktivisme dinamis dan nilai utama Islam menunjukkan karakter eksistensialis.
Tokoh-tokoh seperti Ali Syari’ati dan Hasan Hanafi disebut sebagai eksistensialis religius dalam konteks Islam. Mereka menekankan manusia sebagai subjek yang dinamis, aktif, dan memiliki kebebasan untuk berkreasi, namun dalam batasan takdir dan nilai-nilai Islam. Hasan Hanafi, misalnya, membangun teologi antroposentris yang menempatkan manusia sebagai titik tolak untuk mengembangkan nalar religius-spiritual, menekankan kemandirian manusia dalam setiap tindakan dengan teologi Islam sebagai dasarnya. Mereka berupaya mengintegrasikan kebebasan individu dengan kewajiban agama, mengakui bahwa kebebasan manusia tidaklah tanpa batas, melainkan tertuju pada pengembangan ilmu pengetahuan untuk kebaikan diri dan masyarakat. Integrasi nilai-nilai eksistensialisme dalam pendidikan Islam dianggap berpotensi besar untuk mengembangkan potensi siswa, meskipun tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan berpikir radikal dengan kewajiban dan nilai-nilai agama yang telah ditetapkan.
Penerimaan dan Adaptasi Konsep Eksistensialisme dalam Teologi Kristen:
Pendekatan eksistensial pada teologi Kristen memiliki sejarah yang panjang, dengan akar pada pemikir seperti St. Agustinus, St. Thomas Aquinas, Blaise Pascal, dan tentu saja, Søren Kierkegaard. Eksistensialisme Kristen, berbeda dengan pandangan pesimis Sartre yang menganggap hidup tidak berarti, menekankan hubungan antara makna dengan individu dan kemanusiaan secara keseluruhan, mencari nilai dalam kehidupan melalui iman dan pengalaman dengan Tuhan.
Penelitian di Indonesia telah mengeksplorasi penerapan Filsafat Eksistensialisme Kristen (berdasarkan pemikiran Kierkegaard dan Sartre) dalam manajemen pendidikan Kristen. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang lebih reflektif, autentik, dan resilien dalam menghadapi tantangan kontemporer, dengan model yang mengintegrasikan prinsip-prinsip eksistensialisme untuk pendidikan yang inklusif dan dialogis.
Integrasi dan adaptasi konsep-konsep eksistensialisme dalam kerangka teologis Islam dan Kristen di Indonesia menunjukkan proses intelektual yang sangat canggih. Ini bukan sekadar adopsi, melainkan keterlibatan kritis di mana kekhawatiran eksistensial universal—seperti kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna—secara aktif dikontekstualisasikan ulang dan seringkali diselaraskan dengan ontologi agama, sistem moral, dan nilai-nilai spiritual tertentu. “Hibridisasi” ini menunjukkan vitalitas intelektual pemikiran keagamaan Indonesia, menunjukkan kapasitasnya untuk menyerap, mengkritik, dan mengubah filsafat asing untuk mengatasi tantangan spiritual dan etika kontemporer dari perspektif pribumi yang berbasis iman. Interaksi dinamis antara pemikiran filosofis dan kepercayaan agama ini merupakan karakteristik yang menentukan lintasan eksistensialisme di Indonesia.
D. Konteks Sosial, Politik, dan Budaya
Eksistensialisme juga menemukan relevansinya dalam diskursus sosial, politik, dan budaya di Indonesia, melampaui ranah akademis dan seni.
Hubungan Eksistensialisme dengan Nilai-nilai Pancasila: Nilai-nilai Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, sebagian besar memiliki keselarasan dengan filsafat eksistensialisme, terutama dalam penekanannya pada peran individu dan otonomi manusia. Ada kebutuhan yang diidentifikasi untuk mengkaji kembali hakikat manusia Pancasila menurut Notonagoro dalam perspektif eksistensialisme Søren Kierkegaard, serta relevansinya dengan pembentukan karakter bangsa Indonesia. Konsep manusia monopluralis Pancasila dapat diekstrak menjadi dua inti utama: otonom dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan penekanan eksistensialisme pada kebebasan dan akuntabilitas individu.
Koneksi eksplisit antara eksistensialisme dan Pancasila adalah contoh mendalam dari adaptasi dan integrasi filosofis. Ini menandakan upaya untuk mendamaikan filsafat Barat yang berpusat pada kebebasan dan tanggung jawab individu dengan ideologi negara Indonesia, yang juga menjunjung tinggi martabat dan otonomi manusia tetapi dalam kerangka komunal dan pluralistik. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensialisme menawarkan lensa filosofis yang berharga untuk mengartikulasikan, memperkuat, dan bahkan mungkin mengkritik identitas dan karakter nasional yang berkembang di Indonesia pasca-kemerdekaan.
Pengaruh pada Gerakan Mahasiswa dan Diskusi Publik: Pemikiran eksistensialisme, khususnya Jean-Paul Sartre, memiliki relevansi signifikan dalam konteks gerakan mahasiswa. Filsafat ini mendukung gagasan bahwa mahasiswa perlu terus bebas melawan penindasan dan siap memikul tanggung jawab atas kebebasan bergerak mereka, mendorong mereka untuk tidak menyerah pada kejenuhan dan tetap konsisten dalam perjuangan. Selain itu, diskusi tentang identitas budaya sebagai bagian dari eksistensi juga menjadi relevan, terutama bagi komunitas diaspora Indonesia di Eropa yang bergulat dengan pertanyaan mendalam “Who am I? Where do I belong?” dalam perjalanan panjang mereka.
Penerapan eksistensialisme pada gerakan mahasiswa dan diskursus tentang identitas diaspora menyoroti kegunaannya sebagai kerangka untuk analisis sosial dan politik yang kritis. Ini memberdayakan individu dan kelompok untuk mempertanyakan struktur kekuasaan yang ada, menegaskan agen mereka, dan menavigasi masalah identitas yang kompleks, menunjukkan peran eksistensialisme dalam membentuk tidak hanya pemikiran individu tetapi juga tindakan kolektif dan wacana nasional yang lebih luas.
IV. Kritik dan Relevansi Eksistensialisme Kontemporer di Indonesia
A. Kritik terhadap Eksistensialisme
Penerimaan eksistensialisme di Indonesia tidak lepas dari berbagai kritik, terutama dari perspektif keagamaan, yang menyoroti ketegangan antara kebebasan radikal eksistensialisme dan doktrin iman.
Kritik dari Perspektif Agama (Islam, Kristen):
Kritik utama seringkali ditujukan pada eksistensialisme ateistik, khususnya pandangan Jean-Paul Sartre yang menyatakan bahwa keberadaan Tuhan membatasi kebebasan manusia, dan manusia hanya bisa menjadi diri sendiri jika meniadakan Tuhan. Dari perspektif agama, ditekankan pentingnya belajar melalui pengalaman dengan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan untuk mengembangkan makna diri yang sejati dan bertanggung jawab. Filsafat eksistensialisme Sartre, yang menganggap kebebasan sejati hanya ada jika manusia menyangkal keberadaan Tuhan, dianggap perlu dipahami dalam konteks zamannya, dan manusia harus tetap bertanggung jawab atas kepercayaannya.
Dalam konteks Islam, muncul kritik terhadap pandangan yang mengabaikan batasan takdir dalam konsep kebebasan manusia, meskipun konsep kebebasan (al-hurriyyah) itu sendiri diakui dalam kerangka teologis. Teologi Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatannya, tetapi dengan batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan setiap perbuatan memiliki konsekuensi di dunia dan akhirat. Integrasi eksistensialisme dalam pendidikan Islam menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berpikir radikal dengan kewajiban dan nilai-nilai agama yang telah ditetapkan, seperti akhlak dan ketakwaan.
Ketegangan yang mendasar dan abadi dalam penerimaan eksistensialisme di Indonesia adalah bagaimana mendamaikan penekanan radikal filsafat ini pada kebebasan individu dan penciptaan diri (terutama varian ateistiknya) dengan doktrin agama yang mengemukakan kehendak ilahi, tatanan yang telah ditentukan, atau moral absolut. Negosiasi ini merupakan aspek krusial dari perkembangan eksistensialisme dalam masyarakat yang didominasi agama seperti Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat tersebut tidak diserap secara tidak kritis tetapi dikenakan pengawasan teologis yang ketat, yang mengarah pada adaptasi signifikan (misalnya, munculnya eksistensialisme religius yang mengintegrasikan kebebasan dengan iman) atau penolakan langsung terhadap dimensi ateistiknya yang lebih konfrontatif. Interaksi dinamis antara pemikiran filosofis dan kepercayaan agama ini merupakan karakteristik yang menentukan lintasan eksistensialisme di Indonesia.
Kritik dari Organisasi Keagamaan (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Gereja):
Meskipun tidak ada kritik eksplisit langsung dari Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah terhadap eksistensialisme secara spesifik dalam data yang tersedia, dapat diinferensikan bahwa organisasi keagamaan ini akan cenderung mengkritik aspek-aspek eksistensialisme yang bertentangan dengan doktrin agama atau tradisi keilmuan mereka. Misalnya, ideologi Muhammadiyah yang lahir dari Islam dan beradaptasi dengan zaman menyiratkan bahwa setiap pemikiran yang masuk akan disaring melalui lensa Islam. Kekhawatiran NU terhadap tradisi ngaji kitab yang mulai hilang juga menunjukkan kehati-hatian terhadap pemikiran yang tidak berakar pada tradisi keilmuan agama yang mapan. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menekankan persatuan Kristen dan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi dasar kuat untuk mengkritik atau merekontekstualisasi aspek ateistik atau nihilistik dari eksistensialisme, dengan fokus pada kesatuan dan pelayanan berdasarkan Firman Tuhan.
B. Adaptasi dan Kontekstualisasi di Era Modern
Pemikiran eksistensialis terus berkembang dan beradaptasi, memengaruhi berbagai bidang kontemporer seperti psikologi humanistik, terapi eksistensial, dan kritik sosial. Eksistensialisme menunjukkan relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi yang kompleks. Filsafat ini membantu individu dan masyarakat untuk menjaga kehidupan yang otentik di tengah tekanan konformitas dan menawarkan perspektif filosofis yang mendalam untuk mengatasi tantangan psikologis dan spiritual yang dihadapi manusia modern.
Dalam konteks pendidikan di era digital, eksistensialisme mendorong pengembangan pola pikir subjektivitas dan tanggung jawab atas diri sendiri, serta pemanfaatan potensi diri secara otentik di tengah maraknya citra semu di media sosial. Pendidikan harus mampu mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri dan bertanggung jawab atas pilihan mereka, bahkan di era yang penuh dengan informasi dan citra yang terkadang semu.
Pencarian Makna Hidup dan Identitas di Tengah Krisis Kontemporer: Eksistensialisme menekankan bahwa identitas dibentuk melalui pilihan, pentingnya autentisitas, kebebasan yang disertai tanggung jawab, identitas sebagai proyek yang berkelanjutan, peran interaksi dengan orang lain, kemampuan menghadapi ketidakpastian, potensi transendensi, serta pentingnya momen krisis identitas dan narasi diri untuk pertumbuhan. Konsep-konsep ini sangat relevan bagi Generasi Z dalam pencarian makna hidup di era digital, di mana mereka dihadapkan pada berbagai informasi dan tekanan sosial yang dapat memicu krisis identitas.
Relevansi eksistensialisme yang berkelanjutan di Indonesia kontemporer, khususnya dalam menavigasi kompleksitas era digital dan globalisasi , menunjukkan kegunaannya yang abadi sebagai kerangka untuk memahami dan mengatasi kondisi manusia modern. Prinsip-prinsip inti filsafat—otentisitas, tanggung jawab individu, dan keharusan pencarian makna—menjadi sangat kuat di era yang ditandai oleh kelebihan informasi, tekanan media sosial , dan potensi krisis identitas. Dalam konteks ini, eksistensialisme berfungsi tidak hanya sebagai pengejaran akademis tetapi sebagai “kompas moral” praktis, membimbing individu untuk menegaskan agen mereka, menemukan makna pribadi, dan mempertahankan otentisitas di tengah kompleksitas dan tekanan yang melekat dalam kehidupan kontemporer. Hal ini menyoroti kapasitas adaptifnya yang luar biasa dan perannya yang berkelanjutan dalam mengatasi kekhawatiran manusia universal dalam konteks modern yang berkembang pesat.
Tabel 3: Relevansi Eksistensialisme dalam Konteks Kontemporer Indonesia
| Aspek Kontemporer | Tantangan Spesifik yang Dihadapi | Solusi/Relevansi yang Ditawarkan Eksistensialisme | Contoh Penerapan/Diskusi |
| Era Digital dan Globalisasi | Konformitas, citra semu di media sosial, krisis identitas, disorientasi makna, dehumanisasi teknologi | Otentisitas, tanggung jawab pribadi, pencarian makna hidup, kesadaran diri, kebebasan memilih | Pengembangan kurikulum pendidikan di era digital, refleksi eksistensial bagi Gen Z, kritik sosial terhadap dampak teknologi |
| Pendidikan Modern | Kurikulum kaku, fokus kognitif semata, kurangnya pengembangan individu holistik | Kurikulum inklusif, personal, berpusat pada siswa; pengembangan kesadaran diri, kemandirian, tanggung jawab siswa | Peran guru sebagai fasilitator, pendidikan karakter berbasis eksistensialisme |
| Tantangan Psikologis/Spiritual | Kecemasan, kehampaan eksistensial, alienasi, pencarian jati diri | Penerimaan diri, transendensi, narasi diri, menghadapi ketidakpastian, menemukan makna dalam krisis | Terapi eksistensial, bimbingan spiritual, eksplorasi tema dalam seni dan sastra |
| Pembentukan Karakter Bangsa | Kecenderungan materialistis, hedonisme, individualistis, penolakan Pancasila | Penekanan pada otonomi dan tanggung jawab individu dalam kerangka Pancasila, pembentukan karakter otentik | Kajian hakikat manusia Pancasila dari perspektif eksistensialisme |
C. Warisan dan Prospek Masa Depan
Eksistensialisme terus membentuk pemikiran di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan, di mana ia berkontribusi pada pemahaman karakteristik dan keunikan individualitas siswa. Warisan ini menunjukkan bahwa filsafat eksistensialisme telah melampaui sekadar adopsi, menjadi bagian integral dari wacana intelektual dan praktik di Indonesia.
Disarankan agar penelitian lebih lanjut difokuskan pada studi kasus penerapan filsafat eksistensialisme di berbagai institusi pendidikan, serta pengembangan model kurikulum yang dapat menyeimbangkan kebebasan siswa dengan kebutuhan sistemik dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensialisme di Indonesia bukanlah artefak sejarah yang statis, melainkan tradisi filosofis yang dinamis, hidup, dan berkembang.
Seruan eksplisit untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan model kurikulum baru yang menyeimbangkan kebebasan siswa dengan kebutuhan sistemik , bersama dengan pengakuan atas pengaruh eksistensialisme yang berkelanjutan dalam memahami keunikan individu dalam pendidikan , menandakan bahwa eksistensialisme di Indonesia adalah tradisi filosofis yang dinamis, hidup, dan berkembang. Hal ini menunjukkan pergeseran dari sekadar adopsi dan interpretasi ke inovasi dan kontekstualisasi aktif. Lintasan masa depan menyiratkan bahwa pemikir dan pendidik Indonesia akan terus terlibat secara kreatif dengan ide-ide eksistensialisme, mengadaptasinya untuk mengatasi tantangan sosial yang muncul dan berkontribusi pada “eksistensialisme Indonesia” yang khas, yang berakar kuat pada realitas lokal sambil terlibat dengan kekhawatiran manusia universal. Ini menandai fase kematangan dalam perkembangan filsafat di negara ini.
Kesimpulan
Perkembangan pemikiran eksistensialisme di Indonesia merupakan sebuah narasi yang kaya tentang adaptasi, sintesis, dan relevansi yang berkelanjutan. Berawal dari konteks krisis global pasca-perang dunia, filsafat ini menemukan lahan subur di Indonesia yang baru merdeka, di mana pencarian identitas dan penegasan kebebasan individu menjadi sangat relevan. Melalui peran vital universitas, penerbitan buku, dan majalah ilmiah, eksistensialisme berhasil menyebar dan meresap ke dalam berbagai lapisan intelektual.
Tokoh-tokoh kunci seperti Driyarkara, dengan konsep “Homo Homini Socius” yang khas Indonesia, serta para sastrawan (Chairil Anwar, Iwan Simatupang, Pramoedya Ananta Toer, Sapardi Djoko Damono) dan seniman (Hilman Cahya Kusdiana, Dedy Sufriadi) telah secara kreatif mengadaptasi dan memanifestasikan tema-tema eksistensial dalam karya-karya mereka, menjadikan filsafat ini lebih mudah diakses dan relevan bagi masyarakat luas. Dalam ranah keagamaan, eksistensialisme memicu dialog dan hibridisasi, di mana konsep kebebasan dan tanggung jawab diintegrasikan ke dalam teologi Islam dan Kristen, meskipun dengan kritik dan adaptasi untuk menyelaraskan dengan doktrin iman.
Meskipun eksistensialisme menghadapi kritik, terutama dari perspektif agama yang menyoroti potensi konflik antara kebebasan radikal dan nilai-nilai ilahi, filsafat ini terus menunjukkan relevansinya yang kuat di era kontemporer. Eksistensialisme berfungsi sebagai kompas moral, membimbing individu untuk menemukan autentisitas, makna, dan tanggung jawab pribadi di tengah kompleksitas era digital dan globalisasi. Warisan eksistensialisme di Indonesia bukan hanya tentang adopsi pemikiran Barat, melainkan tentang inovasi dan kontekstualisasi yang berkelanjutan, membentuk sebuah tradisi filosofis yang dinamis dan relevan untuk masa depan bangsa.
Daftar Pustaka :
- The Philosophy of Existentialism: Individual Awareness in …, diakses Juli 1, 2025, https://radiant.polhas.ac.id/index.php/radiant/article/download/84/31/411
- EKSISTENSIALISME TEISTIK MUHAMMAD IQBAL – Digilib UIN SUKA, diakses Juli 1, 2025, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/56205
- Kebebasan Individu dalam Tinjauan Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre Muhamad Fauzan1, Radea Yuli A. Hambali2 1,2 Jurusa, diakses Juli 1, 2025, https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1543/1090
- The Philosophy of Existentialism: Individual Awareness in Indonesian Education, diakses Juli 1, 2025, https://radiant.polhas.ac.id/index.php/radiant/article/download/84/31
- RELEVANSI ALIRAN FILSAFAT EKSISTENSIALISME DALAM MEMBAHAS ISU KEBEBASAN BERAGAMA – OSF, diakses Juli 1, 2025, https://osf.io/fwb3x/download
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Eksistensialisme Sartre Secara etimologi eksistensi berasal dari kata “eks” yang, diakses Juli 1, 2025, https://repository.um-surabaya.ac.id/2470/3/BAB_II.pdf
- EKSISTENSIALISME DALAM PENDIDIKAN DASAR Oleh Listi Khairani Pohan Nanda Andriani Nurdiana Ulfah Riska Arila nandaandriani14@gmai – JURNAL TARBIYAH UINSU, diakses Juli 1, 2025, https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/almursyid/article/download/1208/871
- Artikel “Eksistensialisme” – Ensiklopedia Sastra Indonesia, diakses Juli 1, 2025, https://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Eksistensialisme
- BAB III PENGERTIAN EKSISTENSIALISME dan SEJARAH KEMUNCULAN EKSISTENSIALISME, diakses Juli 1, 2025, http://digilib.uinsa.ac.id/6389/6/Bab%203.pdf
- BAB 2 EKSISTENSIALISME RELIGIUS Pengantar – Perpustakaan Universitas Indonesia, diakses Juli 1, 2025, https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old16/127405-RB16H28e-Eksistensialisme%20religius-Literatur.pdf
- EKSISTENSI MANUSIA DI ERA DIGITAL PERSFEKTIF FILSAFAT EKSISTENSIALISME JEAN PAUL SARTRE, diakses Juli 1, 2025, https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jmi/article/download/6303/6963/7305
- Eksistensialisme – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Juli 1, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensialisme
- Gambaran Pemikiran Eksistensialisme Sartre Dalam Karakter Utama Komik One Piece Karya Oda Eichiro Moh. Rizchald Walidain1, Syih – Portal Jurnal Peneliti. net, diakses Juli 1, 2025, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/3455/2511/
- Kebebasan Manusia Didalam Filsafat Eksistensialisme Di Film “Soekarno” – Portal Jurnal Peneliti. net, diakses Juli 1, 2025, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/10433/6790/
- 0 0 TEMU MANTEN DALAM PANDANGAN EKSISTENSIALISME (Studi Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabu – Raden Intan Repository, diakses Juli 1, 2025, https://repository.radenintan.ac.id/33539/1/SKRIPSI%201-2.pdf
- Eksistensi Adalah: Memahami Makna dan Pentingnya dalam Kehidupan – Liputan6.com, diakses Juli 1, 2025, https://www.liputan6.com/feeds/read/5909092/eksistensi-adalah-memahami-makna-dan-pentingnya-dalam-kehidupan
- KONSEP DIRI DALAM EKSISTENSIALISME ROLLO MAY – eJournal of Sunan Gunung Djati State Islamic University, diakses Juli 1, 2025, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/viewFile/11669/5606
- Eksistensialisme Dalam Sajak Chairil Anwar | The Columnist, diakses Juli 1, 2025, https://thecolumnist.id/artikel/eksistensialisme-dalam-sajak-chairil-anwar-2727
- Filsafat Eksistensialisme Dalam Pandangan Soren Aabye Kierkegaard Terhadap Spiritualitas Pada Remaja Akhir Generasi Z, diakses Juli 1, 2025, https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpakk/article/download/390/547/2151
- HUMAN BEING DALAM DISKURSUS EKSISTENSIALISME BARAT DAN ISLAM: KOMPARASI PEMIKIRAN JEAN-PAUL SARTRE, GABRIEL MARcEL, MULLA SADRA, diakses Juli 1, 2025, https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/download/426/304/848
- Memahami Filsafat Eksistensialisme – Kompas.com, diakses Juli 1, 2025, https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/02/080000965/memahami-filsafat-eksistensialisme?page=all
- Freedom and responsibility in Jean-Paul Sartre’s existentialism: A philosophical review, diakses Juli 1, 2025, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JICC/article/view/40466
- Eksistensialisme Tuhan Analisis Terhadap Pandangan Dan Kritik Jean-Paul Sartre | Simbolon | Jurnal Teologi Cultivation – IAKN Tarutung, diakses Juli 1, 2025, https://e-journal.iakntarutung.ac.id/index.php/cultivation/article/view/219
- FILSAFAT PENDIDIKAN “Aliran Filsafat Pendidikan Eksistensialisme” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO FAKULTAS AGAMA ISLAM JUR, diakses Juli 1, 2025, http://eprints.umsida.ac.id/7644/1/Makalah%20Filsafat%20B1%20Aliran%20Pendidikan%20Eksistensialisme.pdf
- FILSAFAT EKSISTENSIALISME MARTIN HEIDEGGER DAN PENDIDIKAN PERSPEKTIF EKSISTENSIALISME – E-Journal STITPN, diakses Juli 1, 2025, https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa/article/download/1403/989
- ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT BARAT KONTEMPORER (POSTMODERNISME) Lailatul Maskhuroh STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang, diakses Juli 1, 2025, https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/UrwatulWutsqo/article/download/258/174/785
- Sholihul Huda – UMSurabaya Repository – Universitas, diakses Juli 1, 2025, https://repository.um-surabaya.ac.id/10080/2/8.%20Plagiasi%20Dasar_Filsafat_Dr._Sholikh_1.pdf
- Ferry Hidayat, Sketsa Sejarah Filsafat Indonesia (2nd Printing) – PhilPapers, diakses Juli 1, 2025, https://philpapers.org/rec/HIDSSF
- pengaruh filsafat nietzsche – Jurnal Universitas Gadjah Mada, diakses Juli 1, 2025, https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/download/3113/9365
- Sejarah Fakultas Filsafat UGM, diakses Juli 1, 2025, https://filsafat.ugm.ac.id/sejarah/
- View of Eksistensialisme Dalam Filsafat Ilmu : Hubungan Antara Manusia Dan Pengetahuan, diakses Juli 1, 2025, https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/4514/1952
- SEJARAH FAKULTAS FILSAFAT UGM – Garda.id, diakses Juli 1, 2025, https://www.garda.id/2024/10/sejarah-fakultas-filsafat-ugm.html
- View of Isu-isu Kontemporer Filsafat Sosial dalam Perpektif Aliran, diakses Juli 1, 2025, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/65130/29259
- Eksistensialisme Jean Paul Sartre – Balai Buku Progresif, diakses Juli 1, 2025, https://bukuprogresif.com/product/eksistensialisme-jean-paul-sartre/
- Eksistensialisme Jean-Paul Sartre (1905-1980) – Repository Driyarkara, diakses Juli 1, 2025, http://repo.driyarkara.ac.id/152/
- ETIKA DRIYARKARA DAN RELEVANSINYA DI ERA …, diakses Juli 1, 2025, https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/download/13221/9464
- KONSEP RELASI DALAM PEMIKIRAN EKSISTENSIALISME …, diakses Juli 1, 2025, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/4250
- Chairi Anwar: Penuturan Paradigma Eksistensialisme dalam Puisi – Indonesiana, diakses Juli 1, 2025, https://www.indonesiana.id/read/180466/chairi-anwar-penuturan-paradigma-eksistensialisme-dalam-puisi
- Perjalanan Eksistensial dalam Novel Ziarah Karya Iwan Simatupang | kumparan.com, diakses Juli 1, 2025, https://m.kumparan.com/intan-aura/perjalanan-eksistensial-dalam-novel-ziarah-karya-iwan-simatupang-23hthba6f7g
- Eksistensialisme Dalam Drama-Drama Iwan Simatupang (Sebuah Tinjauan Filsafat), diakses Juli 1, 2025, http://digilib.isi.ac.id/4870/
- Ideologi Eksistensialisme Pada Puisi “Prologue” Karya Sapardi Djoko Damono Existentialism Ideology in Sapardi Djoko – Protasis, diakses Juli 1, 2025, https://protasis.amikveteran.ac.id/index.php/protasis/article/download/17/14/24
- Eksistensialisme dalam Seni Lukis Simbolisme (Ikan Koki) – e-Jurnal ISBI Bandung, diakses Juli 1, 2025, https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/atrat/article/download/2315/1371
- 15 Seniman Muda Inovatif Indonesia di 2021, diakses Juli 1, 2025, https://www.luxuo.id/seni/15-seniman-muda-inovatif-indonesia-di-2021.html
- Jejaring Intelektual Jesuit dalam Membangun Semangat Kebangsaan dan Politik di Indonesia | VOX POPULI, diakses Juli 1, 2025, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/voxpopuli/article/view/21805
- EKSISTENSIALISME; PERANAN DAN REKONSTRUKSINYA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM Abstrak Pemikiran pendidikan eksist, diakses Juli 1, 2025, https://idr.uin-antasari.ac.id/5149/2/Ringkasan%20Penelitian.pdf
- Filsafat Eksistensialisme Kierkegaard Dan Implikasinya Terhadap Praktik Pendidikan Dalam Meningkatkan Spiritualitas Peserta Didi, diakses Juli 1, 2025, https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/download/2998/1886/7866
- Membincang Filsafat Eksistensialisme dalam Perspektif Islam | GEOTIMES, diakses Juli 1, 2025, https://geotimes.id/opini/membincang-filsafat-eksistensialisme-dalam-perspektif-islam/
- EKSISTENSIALISME DAN PENDIDIKAN ISLAM: MENGHADAPI TANTANGAN DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI SISWA Erfin Walida Rahmania UIN Sunan – Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya, diakses Juli 1, 2025, https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/24852/9395
- EKSISTENSIALISME DAN PENDIDIKAN ISLAM: MENGHADAPI TANTANGAN DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI SISWA | Studia Religia, diakses Juli 1, 2025, https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/24852
- Revitalisasi filsafat eksistensialisme Kristen dalam manajemen pendidikan kristiani: Merancang sistem pembelajaran yang resilien, diakses Juli 1, 2025, https://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/download/931/377/3870
- Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonagoro Dalam Perspektif Eksistensialisme Soren Aabye Kierkegaard Dan Relevansinya Dengan Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia – ETD UGM, diakses Juli 1, 2025, http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/193929
- Gerakan Mahasiswa dan Eksistensialisme ala Sartre, diakses Juli 1, 2025, https://lsfdiscourse.org/gerakan-mahasiswa-dan-eksistensialisme-ala-sartre/
- Kritikan Untuk Orang-orang NU Oleh: Gus Baha – ppm.alhadi.or.id, diakses Juli 1, 2025, https://ppm.alhadi.or.id/index.php/artikel/kritikan-untuk-orang-orang-nu-oleh-gus-baha/
- KRITIK TERHADAP EKSISTENSIALISME ATEISTIK TENTANG PENOLAKAN EKSISTENSI TUHAN – Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses Juli 1, 2025, https://digilib.uin-suka.ac.id/731/
- KONSEPTUALISASI PENDIDIKAN DALAM PANDANGAN ALIRAN FILSAFAT EKSISTENSIALISME – Journal of University of Muhammadiyah of Gresik, diakses Juli 1, 2025, https://journal.umg.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/93
- Relevansi Filsafat Eksistensialisme dalam Kehidupan Modern | Journal of Humanities, Social Sciences, and Education, diakses Juli 1, 2025, https://jurnal.yayasanmeisyarainsanmadani.com/index.php/JHUSE/article/view/61
- KONTEKSTUALISASI FILSAFAT EKSISTENSIALISME TERHADAP PRAKTIK PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL CONTEXTUALIZATION OF THE PHILOSOPHY OF EXI – UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, diakses Juli 1, 2025, https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqhzan/article/download/17864/pdf_81
- Pemikiran Kritis Filsuf Kierkegaard Tentang Manusia Eksistensialis dan Pendidikan – Jurnal UPI, diakses Juli 1, 2025, https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/download/54163/21576
- Analisis Pengaruh Filsafat Eksistensialisme Dalam Kurikulum Pendidikan Modern | QOSIM, diakses Juli 1, 2025, https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/442