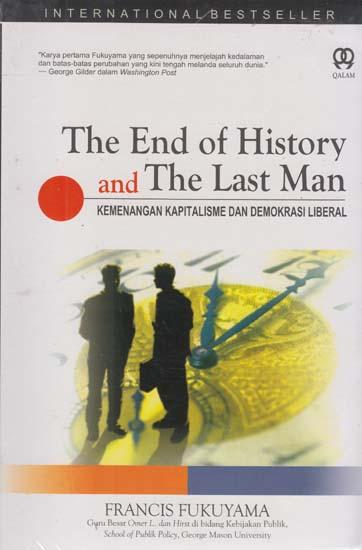Pendahuluan: Visi Pascakomunisme Fukuyama
Pada tahun 1992, Francis Fukuyama, seorang ilmuwan politik Amerika, menerbitkan buku yang sangat provokatif dan monumental berjudul The End of History and the Last Man. Publikasi ini hadir di tengah gejolak historis yang luar biasa, tepat setelah berakhirnya Perang Dingin. Keruntuhan Tembok Berlin pada tahun 1989 dan disusul dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 menandai berakhirnya pertarungan ideologi besar abad ke-20 antara komunisme dan demokrasi liberal. Suasana global saat itu dipenuhi dengan optimisme atas kemenangan demokrasi dan kapitalisme Barat, sebuah iklim intelektual yang dengan sangat efektif diabadikan oleh karya Fukuyama.
Tesis sentral buku ini—yang merupakan perluasan dari esai terkenalnya, “The End of History?”, yang diterbitkan di jurnal The National Interest pada musim panas 1989—menyatakan bahwa dengan kemenangan demokrasi liberal, evolusi ideologis umat manusia telah mencapai “titik akhir”. Fukuyama tidak mengklaim bahwa peristiwa-peristiwa akan berhenti terjadi, melainkan bahwa tidak akan ada lagi alternatif ideologis yang secara fundamental lebih baik atau lebih maju dari demokrasi liberal. Dengan demikian, semua negara, cepat atau lambat, akan bergerak menuju sistem pemerintahan yang mengadopsi prinsip-prinsip ini, menjadikan demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan final dan universal bagi umat manusia. “Akhir sejarah” dalam konteks ini merujuk pada berakhirnya perdebatan tentang bentuk pemerintahan ideal, bukan pada berakhirnya waktu atau peristiwa, seperti perang lokal atau konflik etnis, yang menurutnya tetap akan ada di sebagian dunia yang “masih terperosok dalam sejarah”.
Landasan Filosofis: Dari Dialektika Hegelian ke Thymos
Untuk membangun tesisnya yang ambisius, Fukuyama mengambil inspirasi mendalam dari filsafat sejarah Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang ia pahami melalui reinterpretasi Alexandre Kojève. Bagi Fukuyama, sejarah bukanlah sekumpulan peristiwa acak, melainkan sebuah proses evolusioner yang bertujuan, didorong oleh kontradiksi-kontradiksi ideologis yang ada dalam masyarakat manusia. Proses ini, yang dikenal sebagai dialektika, akan terus menghasilkan “tesis” (cara berpikir atau sistem sosial tertentu) dan “antithesis” (oposisi terhadapnya) hingga akhirnya tercapai “sintesis” yang menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi tersebut. Menurut Fukuyama, demokrasi liberal adalah sintesis akhir ini karena ia tidak mengandung kontradiksi mendasar dalam kehidupan manusia yang tidak dapat diselesaikan di dalamnya.
Motor penggerak utama di balik evolusi sejarah ini, menurut Fukuyama, adalah konsep Hegelian yang disebut thymos. Thymos adalah hasrat psikologis universal manusia untuk diakui dan dihargai martabatnya oleh orang lain. Ini adalah dorongan yang membedakan manusia dari hewan, yang hanya digerakkan oleh kebutuhan dasar dan keinginan (seperti makanan atau tempat tinggal).
Thymos memicu “perjuangan untuk pengakuan,” yang termanifestasi dalam dialektika “tuan-budak” Hegel, di mana orang-orang berjuang untuk membuktikan superioritas mereka, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa. Demokrasi liberal dianggap sebagai satu-satunya sistem yang dapat memuaskan thymos secara universal dan timbal balik, karena ia mengakui martabat semua individu secara setara melalui sistem hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hubungan kausal yang mendasari tesis Fukuyama adalah sebagai berikut: thymos memicu perjuangan untuk pengakuan, yang menggerakkan dialektika sejarah; dialektika ini pada akhirnya mengarah pada demokrasi liberal sebagai satu-satunya sistem yang dapat memberikan pengakuan universal yang dicari oleh thymos. Dalam kerangka ini, akhir sejarah tidak terhindarkan selama dorongan manusia untuk diakui tetap ada. Jika demokrasi liberal gagal memenuhi janji ini—misalnya, melalui ketidaksetaraan yang parah atau hilangnya pengakuan sosial—maka hal itu dapat memicu munculnya ideologi-ideologi baru yang menjanjikan pengakuan yang lebih besar, dan pada gilirannya, menggerakkan kembali roda sejarah.
Paradoks “Manusia Terakhir”: Kritik dari dalam Demokrasi Liberal
Selain tesis “Akhir Sejarah,” Fukuyama juga mengajukan tesis kedua yang, ironisnya, merupakan kritik internal terhadap hasil akhir sejarah itu sendiri: “Tesis Manusia Terakhir”. Konsep ini diambil dari filsuf Friedrich Nietzsche, yang mengkhawatirkan bahaya “penyusutan dan perataan” manusia Eropa. Nietzsche menggambarkan “Manusia Terakhir” sebagai individu yang terlalu puas, nyaman, dan acuh tak acuh, yang hanya hidup untuk kenikmatan-kenikmatan kecil dan tidak lagi mampu melakukan perjuangan heroik yang memberikan makna pada kehidupan.
Fukuyama mengakui adanya paradoks di dalam tesisnya. Dalam masyarakat pasca-sejarah, demokrasi liberal yang makmur akan memenuhi semua kebutuhan ekonomi dan psikologis dasar setiap warga negara. Namun, dengan tidak adanya perang, revolusi, atau perjuangan besar, manusia akan kehilangan kesempatan untuk heroik dan pengorbanan—manifestasi tertinggi dari thymos. Tanpa perjuangan yang mulia, manusia akan merasa hampa, terdegradasi menjadi “konsumen yang seperti sapi”. Paradoks ini menimbulkan pertanyaan kunci: akankah masyarakat yang damai dan makmur ini cukup untuk memuaskan jiwa manusia? Ataukah mereka pada akhirnya akan mencari perjuangan baru, bahkan jika itu berbahaya, hanya demi mendapatkan kembali pengakuan dan martabat yang hilang? Tesis “Manusia Terakhir” ini menawarkan sebuah analisis yang sangat prescient tentang beberapa fenomena modern, seperti dominasi fiksi distopia dan media yang berfokus pada kiamat. Hal ini menunjukkan adanya kegelisahan mendalam dalam masyarakat liberal, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya sumber-sumber makna yang lebih dalam di luar konsumerisme. Tesis ini adalah kritik dari dalam sistem itu sendiri, sebuah pengakuan bahwa kesuksesan liberalisme dapat menciptakan kondisi bagi kehancuran internalnya.
Menghadapi Kritik: Tantangan Terhadap Akhir Sejarah
Sejak diterbitkan, tesis Fukuyama telah mengundang banyak perdebatan dan kritik dari berbagai sudut pandang. Sejumlah peristiwa dan tren global sejak tahun 1992 menunjukkan bahwa sejarah mungkin belum benar-benar berakhir, atau setidaknya, jalan menuju demokrasi liberal tidak semulus yang diprediksi.
Tesis Bentrokan Peradaban Samuel Huntington
Kritik paling menonjol datang dari Samuel Huntington, mantan mentor Fukuyama. Dalam esainya yang terkenal, “The Clash of Civilizations?”, Huntington berargumen bahwa konflik besar di masa depan tidak akan lagi didasarkan pada ideologi, melainkan pada garis patahan budaya dan agama. Berbeda dengan pandangan Fukuyama bahwa ideologi liberal akan menyatukan dunia, Huntington melihat globalisasi sebagai pemicu gesekan dan ketidaksetaraan yang memaksa peradaban untuk mempertahankan identitasnya. Menurut Huntington, agama adalah faktor terpenting dalam mendefinisikan identitas dan ia melihat kebangkitan fundamentalisme agama, khususnya Islam radikal, sebagai ancaman serius terhadap nilai-nilai liberal. Sementara Fukuyama percaya pada universalitas
thymos yang dipuaskan oleh demokrasi liberal, Huntington menunjukkan bahwa keinginan akan pengakuan ini sering kali terwujud dalam identitas partikularistik yang tidak bisa disatukan oleh liberalisme.
Berikut adalah tabel perbandingan untuk merangkum perbedaan mendasar antara kedua tesis:
| Kriteria | Tesis “Akhir Sejarah” (Fukuyama) | Tesis “Bentrokan Peradaban” (Huntington) |
| Basis Argumen | Ideologi, khususnya liberalisme | Peradaban, budaya, dan agama |
| Pendorong Sejarah | Perjuangan untuk pengakuan (thymos) | Identitas kolektif dan agama |
| Proyeksi Masa Depan | Berakhirnya konflik ideologi, universalisasi demokrasi liberal | Konflik antar peradaban, khususnya antara Barat dan non-Barat |
| Peran Globalisasi | Katalis harmoni dan penyebaran nilai-nilai liberal | Pemicu konflik dan gesekan identitas |
Kebangkitan Tiongkok sebagai Alternatif Model
Tantangan empiris paling signifikan terhadap tesis Fukuyama adalah kebangkitan Tiongkok. Setelah menolak komunisme secara ideologis, Tiongkok tidak beralih ke demokrasi liberal, melainkan mengembangkan model “kapitalisme otoritarian” yang dikendalikan oleh Partai Komunis. Model ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan mengurangi kemiskinan bagi ratusan juta orang, sebuah bukti yang menantang premis Fukuyama bahwa kemakmuran ekonomi tidak dapat dicapai tanpa kebebasan politik. Model Tiongkok ini menawarkan alternatif yang kredibel bagi banyak negara berkembang, yang menunjukkan bahwa ada jalur menuju pembangunan yang tidak harus mengikuti model Barat. Keberhasilan Tiongkok menunjukkan bahwa sejarah mungkin tidak berakhir, melainkan memasuki fase dialektika baru di mana model politik-ekonomi non-liberal yang tangguh telah muncul sebagai antitesis terhadap demokrasi liberal.
Populisme, Nasionalisme, dan Krisis Internal Demokrasi Liberal
Sejak krisis finansial global 2008, tesis Fukuyama juga menghadapi tantangan dari dalam dunia Barat sendiri. Kebangkitan populisme sayap kanan, seperti yang dipimpin oleh Donald Trump, dan nasionalisme etnis yang kian menguat, merupakan penolakan terhadap tatanan globalis dan neoliberal yang seharusnya mendominasi era pasca-sejarah. Gerakan-gerakan ini sering kali berakar pada rasa frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan kelompok yang merasa “tertinggal” oleh globalisasi dan tidak diakui dalam masyarakat liberal. Fenomena ini dapat ditafsirkan sebagai manifestasi dari thymos yang tidak terpenuhi—ketika pengakuan universal yang dijanjikan oleh liberalisme tidak terwujud, orang-orang akan mencari pengakuan melalui identitas kelompok yang lebih sempit dan eksklusif, seperti bangsa atau etnis. Hal ini secara fundamental mengancam stabilitas demokrasi liberal, menunjukkan bahwa tantangan terbesar mungkin datang bukan dari musuh ideologis eksternal, melainkan dari penyakit internal yang menggerogoti fondasinya.
Relevansi dan Warisan Abadi: Fukuyama di Abad ke-21
Meskipun banyak kritikus menunjuk pada peristiwa seperti kebangkitan Tiongkok dan terorisme pasca-9/11 sebagai bukti kegagalan tesis “Akhir Sejarah,” karya Fukuyama tetap relevan sebagai titik referensi intelektual. Fukuyama sendiri telah mengklarifikasi dan merevisi pandangannya di buku-buku selanjutnya. Dalam Our Posthuman Future, misalnya, ia berpendapat bahwa bioteknologi yang memungkinkan manusia untuk mengendalikan evolusinya sendiri dapat mengakhiri demokrasi liberal dengan mengubah sifat manusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Fukuyama menyadari adanya tantangan-tantangan baru yang tidak ia prediksi pada tahun 1992.
Pertanyaan utamanya adalah apakah tantangan-tantangan ini adalah “peristiwa” sementara di sela-sela sejarah, seperti yang ia prediksi, ataukah mereka merupakan “antitesis” ideologis baru yang mengancam akhir sejarah. Di satu sisi, argumen pendukung demokrasi liberal, seperti teori perdamaian demokratis yang mengamati bahwa negara-negara demokrasi matang jarang berperang satu sama lain, masih memiliki bukti empiris yang kuat. Namun, di sisi lain, kebangkitan Tiongkok, populisme, dan ketidakstabilan internal demokrasi Barat menunjukkan bahwa pertarungan ideologi belum benar-benar selesai. Evolusi pemikiran Fukuyama dari seorang pemprediksi yang optimis menjadi seorang komentator yang lebih hati-hati tentang krisis demokrasi liberal modern secara tidak langsung mencerminkan kegagalan tesis awalnya. Alih-alih mengakhiri sejarah, ia menjadi salah satu pengamat terkemuka tentang tantangan-tantangan yang terus menghidupkan sejarah.
Kesimpulan: Sebuah Refleksi Kritis
The End of History and the Last Man karya Francis Fukuyama adalah sebuah karya yang mendefinisikan era pasca-Perang Dingin, menangkap optimisme zaman tersebut dan memberikan kerangka filosofis yang provokatif untuk memahaminya. Kekuatan terbesar dari buku ini bukanlah pada prediksinya yang sempurna, melainkan pada analisisnya yang mendalam tentang pendorong sejarah—thymos, hasrat manusia untuk diakui—dan paradoks yang melekat pada masyarakat pasca-sejarah, yang ia tangkap dengan sangat baik melalui konsep “Manusia Terakhir” Nietzsche.
Secara keseluruhan, tesis “Akhir Sejarah” yang diajukan Fukuyama, meskipun tidak terbukti secara universal, tetap menjadi titik awal yang tak terhindarkan untuk setiap diskusi tentang tatanan dunia. Ia prescient dalam memprediksi kemenangan demokrasi liberal atas rival utamanya pada saat itu (fasisme, komunisme), tetapi ia kurang melihat kebangkitan ideologi-ideologi tandingan yang berakar pada budaya, peradaban, dan agama (seperti yang dianalisis oleh Huntington) dan kemunculan model politik-ekonomi non-liberal yang tangguh seperti yang ada di Tiongkok.
Pada akhirnya, alih-alih berakhir, sejarah tampaknya terus berjalan, didorong oleh tantangan baru dan konflik lama yang belum terpecahkan. Karya Fukuyama, dengan segala kekuatannya dan titik butanya, tetap menjadi instrumen analisis yang vital dan referensi yang kaya untuk memahami kompleksitas dan perdebatan tentang masa depan tatanan global di abad ke-21.