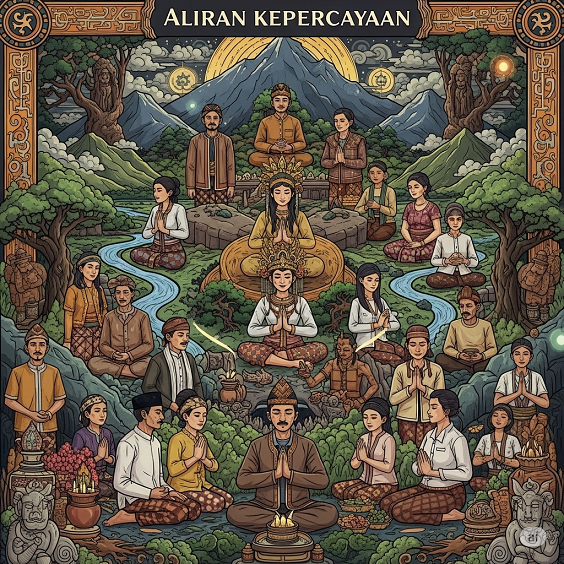Tulisan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai dinamika historis, yuridis, sosiologis, dan kultural Aliran Kepercayaan di Indonesia. Melalui sintesis data dari berbagai sumber, laporan ini menguraikan perjalanan panjang Aliran Kepercayaan, yang dikenal juga sebagai Penghayat Kepercayaan, mulai dari akar budayanya sebagai buah renungan leluhur hingga perjuangan konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan yang setara. Laporan ini secara spesifik menyoroti dampak transformatif dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menjadi tonggak penting dalam penegasan hak-hak sipil para penghayat. Analisis juga mencakup tantangan implementasi yang masih ada, peran strategis organisasi seperti Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI), serta kontribusi Aliran Kepercayaan dalam menjaga kearifan lokal, terutama dalam aspek etika lingkungan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan pemahaman yang utuh dan bernuansa tentang posisi Aliran Kepercayaan sebagai bagian integral dari keragaman bangsa Indonesia.
Definisi dan Konsepsi Aliran Kepercayaan
Aliran Kepercayaan, atau sering disebut sebagai Penghayat Kepercayaan, adalah suatu sistem keyakinan yang lahir dari proses panjang perkembangan budaya, filsafat, dan buah renungan mendalam para nenek moyang di Nusantara. Keyakinan ini kemudian diwariskan secara turun-temurun, membentuk adat istiadat yang mengakar kuat dalam masyarakat hingga kini. Keberadaan Aliran Kepercayaan bukanlah fenomena baru; ia telah hidup dan dianut oleh masyarakat Indonesia selama ratusan tahun, jauh sebelum era kemerdekaan.
Secara konseptual, Aliran Kepercayaan seringkali dibedakan dari “agama” formal berdasarkan beberapa kriteria yang diadopsi secara politis di masa lalu. Perbedaan ini mencakup aspek-aspek seperti ketiadaan kitab suci yang terkodifikasi, nabi atau pembawa ajaran yang spesifik, serta hukum tertulis yang baku. Sebaliknya, ajaran dalam Aliran Kepercayaan lebih berakar pada nilai-nilai yang diyakini dan dipercayai oleh leluhur, yang kemudian menjadi pedoman dan hukum tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat di suatu tempat. Praktik ritualnya pun cenderung tidak memiliki tempat ibadah khusus, berbeda dengan agama resmi. Namun, pandangan ini terus berkembang dan dikoreksi, terutama setelah adanya putusan hukum yang menegaskan kedudukan yang setara antara keduanya.
Latar Belakang Historis
Posisi Aliran Kepercayaan dalam lanskap pluralisme Indonesia memiliki sejarah yang kompleks dan penuh dinamika. Sejak awal kemerdekaan, Aliran Kepercayaan berada di persimpangan antara politik, budaya, dan hukum, di mana identitas spiritual mereka sering kali menjadi objek politisasi. Perjalanan sejarahnya dapat dibagi menjadi tiga periode utama: masa pra-kemerdekaan hingga Orde Baru, era Reformasi, dan era pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Setiap periode ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap evolusi status dan pengakuan Aliran Kepercayaan, dari diskriminasi terselubung hingga perjuangan terbuka untuk kesetaraan hak-hak konstitusional. Laporan ini akan mengulas setiap periode secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang holistik mengenai posisi Aliran Kepercayaan saat ini.
Kebangkitan Politik Aliran Kepercayaan di Masa Orde Lama (1950-1965)
Pada dekade 1950-an, Indonesia menyaksikan kebangkitan yang signifikan dari Aliran Kepercayaan, terutama Kejawen, di kalangan masyarakat ‘abangan’. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kalangan priyayi, tetapi juga meluas ke masyarakat awam, yang kemudian menjadi basis massa utama bagi Partai Komunis Indonesia (PKI). Keterkaitan politik ini memicu ketegangan yang mendalam dengan kelompok Islam, yang memandang PKI sebagai oposisi utama baik secara ideologi maupun politik. Pergulatan ini menjadi bagian dari ketegangan yang lebih besar antara kelompok nasionalis dan Islam dalam perumusan ideologi negara, yang pada akhirnya memuncak dalam penghapusan tujuh kalimat dalam Piagam Jakarta sehari setelah kemerdekaan.
Sebagai respons terhadap kebangkitan Aliran Kepercayaan yang dianggap membahayakan perjuangan politik kubu Islam, Departemen Agama pada tahun 1952 mengusulkan sebuah definisi minimal tentang agama. Definisi ini mensyaratkan adanya “nabi, kitab suci, dan pengakuan internasional,” yang secara implisit dan strategis hanya menguntungkan agama-agama besar seperti Islam dan Kristen. Langkah ini bukanlah murni tindakan teologis, melainkan sebuah manuver politik untuk menekan dan mengendalikan perkembangan Aliran Kepercayaan. Tujuannya adalah untuk meminggirkan para penganut kepercayaan dari ruang politik dan sosial, menjadikannya akar dari diskriminasi struktural yang akan berlangsung selama beberapa dekade berikutnya. Setelah kegagalan revolusi PKI pada tahun 1965, kekecewaan di kalangan ‘abangan’ memicu konversi massal ke agama Kristen. Peristiwa ini secara substansial menggeser persepsi kelompok yang dianggap ancaman bagi Islam, dari ‘abangan’ menjadi komunitas Kristen, yang kemudian memicu konflik fisik di awal masa Orde Baru.
Paradoks Pengawasan Negara di Masa Orde Baru
Meskipun Orde Baru terkenal dengan sifat otoriternya, kebijakan terhadap Aliran Kepercayaan menampilkan sifat yang paradoks. Pemerintah tidak mengakui Aliran Kepercayaan sebagai agama yang sah, namun pada saat yang sama membentuk sebuah lembaga negara untuk mengawasinya. Pada 5 Februari 1979, dibentuklah Direktorat Bina Hayat Kepercayaan (BHK), yang kemudian diubah namanya menjadi Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (PPK) pada tahun 1980. Kelembagaan ini, yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jelas dipisahkan dari enam agama resmi yang berada di bawah Kementerian Agama.
Kebijakan ini merupakan bentuk pengakuan terbatas yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Penempatan Aliran Kepercayaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara efektif memisahkan kepercayaan dari ranah spiritual dan menempatkannya sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Tindakan ini secara halus melanjutkan praktik pemerintahan kolonial yang memisahkan agama dari adat untuk tujuan pengawasan dan pengendalian. Dengan demikian, para penghayat diperlakukan sebagai entitas kebudayaan, bukan spiritualitas yang setara dengan agama, yang pada akhirnya membatasi akses mereka terhadap hak-hak sipil, termasuk dalam pendidikan dan layanan publik. Pembentukan direktorat ini secara jelas menunjukkan bagaimana negara mengunakan definisi agama sebagai alat untuk mengawasi dan membatasi, bukan untuk memberikan perlindungan penuh.
Ketidaksetaraan Hukum dan Diskriminasi Pra-Putusan MK
Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017, penganut kepercayaan di Indonesia mengalami diskriminasi yang mendalam dan terstruktur. Aturan hukum, khususnya dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, secara spesifik memerintahkan agar kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi penganut kepercayaan dikosongkan atau diisi dengan tanda strip (-). Praktik ini menciptakan kerugian konstitusional yang nyata bagi para penghayat, karena kolom identitas di KTP dan KK seringkali menjadi syarat wajib untuk mengakses berbagai layanan publik esensial.
Diskriminasi ini memiliki implikasi yang luas dan merusak. Para penganut kepercayaan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan layanan publik seperti pemasangan listrik, pembukaan rekening bank, pengurusan paspor, dan pelayanan pencatatan sipil lainnya. Lebih dari itu, mereka juga kesulitan untuk mencatatkan perkawinan secara legal, yang berimbas pada status hukum anak-anak mereka dan hak-hak waris. Salah satu kasus yang menonjol adalah pengalaman pasangan Gumirat Barna Alam dan Susilawati, penganut aliran kebatinan Perjalanan, yang selama 13 tahun perkawinan mereka tidak diakui secara hukum oleh negara. Akibatnya, anak-anak mereka tidak memiliki akta kelahiran yang sah dan tidak diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah mereka. Selain itu, stigma sosial yang muncul dari status tanda strip (-) tersebut seringkali membuat penganutnya dianggap “kolot, ateis, kafir, dan sesat,” yang semakin memperburuk diskriminasi yang mereka terima.
Tonggak Sejarah: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016
Tonggak sejarah yang mengubah lanskap hukum bagi Aliran Kepercayaan terjadi pada 7 November 2017, ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil atas Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan. Putusan ini merupakan sebuah revolusi hukum yang mengoreksi diskriminasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun, yang berakar dari interpretasi sempit terhadap undang-undang. MK secara tegas menyatakan bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara.
Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa kata “agama” dalam UU Adminduk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak menyertakan “kepercayaan”. Dengan demikian, putusan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak sipil yang setara. MK memerintahkan agar kolom agama pada KK dan KTP-el bagi penganut kepercayaan dapat diisi dengan status “Penghayat Kepercayaan” tanpa perlu merinci aliran yang dianut. Putusan ini merupakan penegasan kembali prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, yang menjamin kesetaraan di mata hukum bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Keberhasilan ini memindahkan perjuangan penganut kepercayaan dari ranah politik ke ranah hukum, menyediakan fondasi yang kokoh untuk menuntut pemenuhan hak-hak konstitusional mereka.
Implementasi dan Tantangan Administratif Lanjutan
Setelah Putusan MK, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berkewajiban untuk menjalankan putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut. Implementasi teknis dari putusan ini kemudian diatur lebih lanjut, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang mengatur tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Peraturan ini menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di berbagai daerah untuk melayani pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan, yang sebelumnya sangat sulit dilakukan.
Meskipun demikian, Putusan MK adalah titik awal perjuangan, bukan akhir. Kesenjangan antara regulasi hukum dan realitas implementasi di lapangan masih menjadi tantangan yang signifikan. Dibutuhkan harmonisasi peraturan di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk revisi undang-undang terkait perkawinan dan pendidikan, serta sosialisasi yang masif kepada aparatur sipil negara di seluruh tingkatan. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga birokratis dan sosial, yang membutuhkan waktu untuk diatasi.
Berikut adalah tabel yang merangkum linimasa perkembangan status hukum Aliran Kepercayaan:
| Periode | Peristiwa Kunci | Implikasi |
| 1950-an | Definisi minimal agama oleh Departemen Agama. | Diskriminasi terselubung dan marginalisasi politik terhadap Aliran Kepercayaan, terutama Kejawen. |
| 1979-1980 | Pembentukan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan (PPK). | Pengawasan dan kontrol negara yang paradoks; pengakuan terbatas sebagai bagian dari kebudayaan, bukan agama. |
| Pra-2017 | Pengosongan atau tanda strip (-) pada kolom KTP dan KK. | Kerugian konstitusional yang luas, diskriminasi dalam pelayanan publik, dan ketiadaan pengakuan hukum atas hak sipil. |
| 7 November 2017 | Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016. | Pengakuan hukum atas hak konstitusional penganut kepercayaan untuk mencantumkan identitasnya di dokumen kependudukan. |
| Pasca-2017 | Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019. | Implementasi hak sipil, seperti pencatatan perkawinan dan akta kelahiran, namun dengan tantangan harmonisasi regulasi dan sosialisasi yang terus berlanjut. |
Filosofi Dasar dan Ragam Keyakinan
Aliran Kepercayaan memiliki filosofi dasar yang kaya dan unik, yang seringkali mencerminkan perpaduan antara kepercayaan asli pra-Hindu, pra-Buddha, dan pra-Islam dengan unsur-unsur agama pendatang. Ini menghasilkan sebuah identitas spiritual yang sinkretis namun tetap otentik. Konsep ketuhanan dalam Aliran Kepercayaan bervariasi, namun banyak yang memiliki konsep monoteistik atau panteistik, seperti kepercayaan terhadap Sang Hyang Kersa pada Sunda Wiwitan atau Ranying pada Kaharingan. Ajaran-ajaran ini berpusat pada nilai-nilai moral, hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur, serta pencarian kesempurnaan batin.
Studi Kasus Aliran Kepercayaan Terkemuka
- Kejawen (Jawa): Kejawen adalah sebuah sistem kepercayaan yang berakar kuat dari kebudayaan Jawa, yang menggabungkan unsur-unsur mistik asli dengan ajaran Hindu, Buddha, dan Islam. Filosofi dasarnya dipegang teguh oleh para penghayat, termasuk konsep-konsep seperti
sangkan paraning dumadi (asal-usul dan tujuan hidup manusia), manunggaling kawulo Gusti (penyatuan hamba dengan Tuhan), dan memayu hayuning bawana (melestarikan alam dan menjaga keselamatan dunia, lahir maupun batin). Ritual penting yang dijalankan termasuk shalat daim, yaitu shalat yang tidak terputus dan tidak terikat waktu, tanpa ruku dan sujud, hanya berzikir dan bertafakur. Tradisi budaya seperti
ruwatan juga masih dilestarikan. - Sunda Wiwitan (Jawa Barat): Sunda Wiwitan merupakan sistem nilai ajaran kebudayaan yang telah ada di tanah Sunda sejak zaman purba, bahkan sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha. Ajaran intinya berfokus pada pemujaan terhadap roh nenek moyang dan keyakinan pada satu Tuhan yang disebut Sang Hyang Kersa. Filosofi utamanya mengajarkan bahwa alam semesta adalah titipan yang tidak boleh dieksploitasi, dan manusia harus hidup dalam harmoni dengan alam dan sesame Ritual utamanya adalah upacara syukur panen yang dikenal sebagai Seren Taun, yang juga merupakan hari raya bagi penganut Sunda Wiwitan.
- Malim/Parmalim (Sumatera Utara): Malim adalah nama kepercayaan asli suku Batak di Sumatera Utara, yang pengikutnya disebut Parmalim atau Parugamo Malim. Nama “Parmalim” sendiri berarti “bersih” atau “suci”. Kepercayaan ini berpusat di wilayah Batak Toba dan menganggap Danau Toba serta Pulau Samosir sebagai tempat suci. Mereka meyakini satu Tuhan bernama Debata Mulajadi Na Bolon, yang diartikan sebagai “Yang Maha Awal dan Yang Maha Besar”. Ajaran Parmalim memiliki kitab suci bernama
Pustaha Habonaron, yang berisi aturan dan panduan ibadah. Filosofi mereka juga mencakup keyakinan akan reinkarnasi dan hubungan erat antara dunia manusia dan dunia roh. Ritual penting dalam Parmalim meliputi upacara mingguan Marari Sabtu , serta perayaan Sipaha Sada dan Sipaha Lima sebagai wujud syukur atas hasil panen dan untuk mengumpulkan dana sosial. - Sapta Darma (Jawa Timur): Sapta Darma adalah aliran kepercayaan asli dari Jawa Timur yang muncul pada 27 Desember 1952 oleh Hardjosopoero. Nama Sapta Darma memiliki arti “tujuh kewajiban suci”, yang menjadi panduan hidup para pengikutnya. Ajaran ini menekankan nilai-nilai luhur seperti setia pada Pancasila dan undang-undang negara, menolong tanpa pamrih, berani hidup mandiri, bersusila, dan meyakini bahwa dunia ini tidak abadi atau anyakra manggilingan. Ritual utamanya adalah sujud yang dilakukan setidaknya sekali sehari, menghadap ke timur dengan posisi tangan sedakep.
- Buddha Jawi Wisnu (Jawa Timur): Buddha Jawi Wisnu adalah aliran kepercayaan yang berkembang sebelum masa pra-Islam di Jawa Timur, yang merupakan perpaduan ajaran agama Buddha dan Kejawen. Aliran ini memiliki keyakinan tentang jalan penyucian diri untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui pencapaian “guru sejati”. Para penganutnya menjalankan puja bakti dengan melantunkan paritta suci dalam bahasa Jawa dan melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri, mitoni, dan ruwatan. Saat ini, komunitasnya masih eksis di Dusun Kutorejo, Banyuwangi.
- Aluk Todolo (Sulawesi): Aluk Todolo adalah kepercayaan leluhur suku Toraja di Sulawesi. Ajaran utamanya berakar dari animisme, yang meyakini bahwa manusia, hewan, tumbuhan, dan unsur alam lainnya berasal dari langit dan diturunkan oleh nenek moyang bernama Datu’ Laukku. Pengintegrasian ajaran ini dengan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal telah membantu menjaga harmoni dan kerukunan sosial di masyarakat. Ritual yang dijalankan meliputi upacara adat dan gotong royong .
- Kaharingan (Kalimantan): Kepercayaan Kaharingan mulanya dianut oleh suku Dayak di Kalimantan. Filosofi utamanya diwakili oleh simbol
Batang Garing, atau Pohon Kehidupan, yang melambangkan keseimbangan abadi antara dunia atas (alam roh) dan dunia bawah (kehidupan di bumi). Ajaran ini memiliki kitab suci, tempat ibadah (Balai Basarah), dan ritual penting, salah satunya adalah upacara kematian Tiwah. Tiwah adalah upacara penguburan sekunder yang berlangsung selama puluhan hari, di mana tulang belulang jenazah digali, dibersihkan, dan diletakkan di mausoleum khusus yang disebut sandung, untuk menghantar arwah ke alam surg Selama ritual ini, tarian topeng Habukung dipertunjukkan untuk menghibur keluarga yang berduka. - Marapu (Sumba): Marapu adalah kepercayaan leluhur di Pulau Sumba yang filosofinya mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan arwah leluhur. Sebuah pepatah kearifan lokal yang dipegang teguh oleh penganutnya adalah
“Tana Beri Ina Mu” (tanah ibarat ibumu), yang menunjukkan etika lingkungan yang kuat dan penghormatan terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Tradisi seperti Festival Empat Gunung menjadi ruang bagi para Rato (pemimpin ritual) dan masyarakat untuk memperkuat spiritualitas dan solidaritas sosial, yang seringkali diisi dengan pertunjukan budaya, tarian, dan permainan tradisional.
Aliran Kepercayaan sebagai Penjaga Kearifan Lokal
Terdapat benang merah yang kuat yang menghubungkan filosofi berbagai Aliran Kepercayaan di seluruh Nusantara. Konsep seperti Memayu Hayuning Bawana (Kejawen), ajaran bahwa alam adalah titipan (Sunda Wiwitan), dan pepatah “Tana Beri Ina Mu” (Marapu) semuanya menunjukkan bahwa Aliran Kepercayaan memiliki etika lingkungan yang mendalam. Sistem nilai ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan alam sekitarnya, yang menjadi pondasi penting bagi pelestarian ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Perlindungan terhadap Aliran Kepercayaan, dengan demikian, tidak hanya soal hak asasi manusia, tetapi juga merupakan upaya vital untuk melestarikan kearifan lokal yang esensial bagi kelangsungan ekologi dan budaya bangsa.
Tabel 1. Ringkasan Aliran Kepercayaan utama di Indonesia:
| Nama Aliran | Lokasi Geografis & Suku | Filosofi/Ajaran Kunci | Ritual Penting |
| Kejawen | Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur) | Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawulo Gusti, Memayu Hayuning Bawana | Shalat Daim, Ruwatan, Sedekah Bumi |
| Sunda Wiwitan | Jawa Barat (Baduy, Kanekes, Cigugur) | Pemujaan roh leluhur, Sang Hyang Kersa, harmoni dengan alam | Upacara syukur panen (Seren Taun) |
| Malim/Parmalim | Sumatera Utara (Suku Batak) | Debata Mulajadi Na Bolon (Tuhan Yang Maha Besar), kitab suci Pustaha Habonaron, reinkarnasi | Upacara Sipaha Sada & Sipaha Lima, Marari Sabtu |
| Sapta Darma | Jawa Timur (Kediri, Banyuwangi) | Wewarah Pitu (tujuh kewajiban suci), yakin dunia berubah (anyakra manggilingan) | Sujud (menghadap timur) |
| Buddha Jawi Wisnu | Jawa Timur (Banyuwangi) | Gabungan ajaran Buddha & Kejawen, mencapai “guru sejati” | Puja bakti dengan paritta Jawa, tradisi Jawa (kenduri, ruwatan) |
| Aluk Todolo | Sulawesi (Suku Toraja) | Animisme, asal-usul dari langit (Datu’ Laukku), menjaga harmoni sosial | Upacara adat, gotong royong |
| Kaharingan | Kalimantan (Suku Dayak) | Konsep Batang Garing (Pohon Kehidupan), keseimbangan alam | Upacara kematian (Tiwah), tarian Habukung |
| Marapu | Pulau Sumba (Nusa Tenggara Timur) | Harmoni manusia, alam, dan leluhur; Prai Marapu (surga) | Festival adat, ritual tikam babi, tarian tradisional |
Stigma Sosial dan Ketakutan Kolektif
Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengakuan hukum, stigma negatif terhadap penganut kepercayaan masih sangat kuat di masyarakat. Mereka masih sering dicap sebagai penganut “agama sesat” atau “kolot”. Realitas ini menciptakan sebuah paradoks: hak untuk mencantumkan “Penghayat Kepercayaan” di KTP, yang secara hukum seharusnya menjadi tanda pengakuan dan kesetaraan, justru masih dianggap sebagai beban sosial yang dapat membawa kerugian. Akibatnya, banyak penganut, terutama generasi muda, merasa inferior dan memilih untuk menyembunyikan identitas keyakinan mereka, sebagaimana yang dialami oleh RF, seorang pemuda berusia 25 tahun. Ketakutan ini bersifat kolektif, di mana orang tua ragu-ragu untuk mewariskan ajaran leluhur kepada anak-anak mereka karena khawatir masa depan sang anak tidak terjamin. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan penganut kepercayaan telah bergeser dari ranah legislatif/yuridis ke ranah sosiologis, yang lebih sulit untuk diatasi dan membutuhkan perubahan sikap fundamental di tengah masyarakat.
Diskriminasi dalam Pendidikan dan Dunia Kerja
Diskriminasi terhadap penganut kepercayaan masih terjadi secara nyata di sektor pendidikan dan dunia kerja. Dalam ranah pendidikan, anak-anak penghayat sering kali dipaksa untuk mengikuti pelajaran agama mayoritas, dan guru-guru agama dari agama resmi bahkan ada yang secara terbuka mengejek atau memandang rendah kepercayaan mereka. Kasus yang terjadi di Cilacap, di mana seorang guru agama menyebarkan narasi bahwa pendidikan penghayat adalah “sesat” dan akan membuat siswa tidak mendapatkan nilai di rapor, adalah bukti nyata dari diskriminasi ini.
Dalam dunia kerja, pertanyaan mengenai agama di formulir pendaftaran masih menjadi hambatan yang menakutkan bagi para penghayat. Mereka khawatir identitas yang dicantumkan akan menjadi alasan untuk penolakan atau diskriminasi, seperti yang dialami oleh RF. Selain itu, laporan lain juga menunjukkan bahwa penganut kepercayaan terkadang tidak diizinkan mengambil libur pada hari peribadatan kepercayaan mereka. Lambatnya harmonisasi kebijakan di tingkat implementasi, seperti perjuangan untuk memasukkan pendidikan penghayat kepercayaan ke dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang drafnya sempat dihapus , mencerminkan bahwa kemajuan yang dicapai di tingkat hukum masih rentan dan belum sepenuhnya mengikat birokrasi di lapangan.
Peran Sentral Majelis Luhur Kepercayaan (MLKI)
Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) adalah sebuah organisasi yang memiliki peran sentral dan strategis dalam mengadvokasi hak-hak penganut kepercayaan di Indonesia. MLKI berfungsi sebagai wadah tunggal bagi ratusan organisasi penghayat yang ada di seluruh Nusantara. Organisasi ini tidak hanya fokus pada isu-isu internal, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi yang penting antara penganut kepercayaan dengan pemerintah dan berbagai lembaga lainnya.
Peran krusial MLKI terlihat jelas dalam perjuangan hukum, di mana organisasi ini menjadi salah satu aktor utama dalam mengadvokasi dilakukannya judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak sipil para penghayat. Keberhasilan MLKI dalam memenangkan putusan tersebut menjadi model bagi kelompok minoritas lain untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum dan kelembagaan. Di tingkat lokal, MLKI juga aktif mengonsolidasikan dan memperkuat pemahaman ajaran serta memfasilitasi pertukaran pikiran di antara anggotanya untuk mengatasi berbagai permasalahan. Keberadaan MLKI, yang memiliki struktur hingga tingkat provinsi, menunjukkan pergeseran dari kelompok-kelompok adat yang pasif menjadi aktor sipil yang terorganisir dan proaktif dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.
6.2. Data Statistik Penganut dan Sebaran Geografis
Data statistik mengenai penganut Aliran Kepercayaan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan setelah Putusan MK, yang mencerminkan keberhasilan pengakuan negara. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penganut kepercayaan tercatat sebanyak 102.508 jiwa pada Juni 2020 dan meningkat menjadi 117.412 jiwa pada akhir tahun 2022. Peningkatan jumlah penganut yang tercatat secara resmi ini merupakan indikator penting bahwa Putusan MK telah memberikan rasa aman dan dorongan bagi para penghayat untuk mencantumkan identitas keyakinan mereka secara jujur di dokumen kependudukan.
Sebaran geografis para penganut juga menunjukkan bahwa Aliran Kepercayaan bukanlah fenomena yang terbatas di Jawa, melainkan merupakan bagian integral dari keberagaman multietnis di seluruh Nusantara. Konsentrasi penganut tertinggi pada akhir tahun 2022 berada di Nusa Tenggara Timur, diikuti oleh Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Jawa Tengah. Fakta ini menegaskan bahwa perjuangan untuk kesetaraan dan perlindungan hak-hak Aliran Kepercayaan adalah isu nasional yang relevan di berbagai wilayah di Indonesia.
Tabel 2. Data statistik penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia pada tahun 2022:
| Indikator | Data Statistik | Sumber Data |
| Total Jumlah Penganut | 117.412 jiwa (setara 0.04% populasi) | Dukcapil Kemendagri (akhir 2022) |
| Sebaran 5 Provinsi Teratas | 1. Nusa Tenggara Timur: 34.251 jiwa 2. Sulawesi Selatan: 18.714 jiwa 3. Kalimantan Selatan: 8.986 jiwa 4. Maluku: 8.639 jiwa 5. Jawa Tengah: 6.128 jiwa | Dukcapil Kemendagri (akhir 2022) |
| Total Penganut Agama Lain | Islam: 86.87% Kristen: 7.49% Katolik: 3.09% Hindu: 1.71% Buddha: 0.75% Konghucu: 0.03% | Dukcapil Kemendagri (Juni 2020) |
Sintesis
Perjalanan Aliran Kepercayaan di Indonesia adalah narasi yang menggambarkan perjuangan panjang dari diskriminasi politik pasca-kemerdekaan hingga pengakuan hukum yang revolusioner. Semula, Aliran Kepercayaan dipinggirkan melalui definisi agama yang politis di era Orde Lama dan diawasi secara ketat sebagai entitas kebudayaan di era Orde Baru. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjadi tonggak penting yang menegaskan kembali hak-hak konstitusional mereka, memberikan landasan hukum yang kuat untuk kesetaraan. Meskipun demikian, laporan ini menunjukkan bahwa perjuangan belum selesai. Kesenjangan antara pengakuan hukum dan realitas sosial masih menjadi tantangan utama, di mana stigma negatif dan diskriminasi di sektor pendidikan dan pekerjaan masih menghantui para penghayat. Di sisi lain, Aliran Kepercayaan memiliki peran vital sebagai penjaga kearifan lokal dan etika lingkungan yang esensial bagi keberlanjutan bangsa. Peran MLKI sebagai wadah tunggal telah membuktikan bahwa perjuangan yang terorganisir melalui jalur hukum dan kelembagaan dapat membawa perubahan signifikan.
Daftar Pustaka :
- Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia, diakses Agustus 9, 2025, https://journal.lasigo.org/index.php/IJRS/article/download/119/56
- Macam-Macam Kepercayaan dan Perbedaannya dengan Agama – Tirto.id, diakses Agustus 9, 2025, https://tirto.id/jenis-jenis-kepercayaan-pengertian-apa-bedanya-dengan-agama-gaMf
- Aliran Kepercayaan apakah sebuah Agama, ditinjau dari perspektif …, diakses Agustus 9, 2025, https://suaraindonews.com/aliran-kepercayaan-apakah-sebuah-agama-ditinjau-dari-perspektif-budaya-luhur-bangsa/
- KETERSANDUNGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM POLITIK IDENTITAS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, diakses Agustus 9, 2025, https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/viewFile/21638/8472
- AGAMA, MODERNISME, DAN KEPENGATURAN: AGAMA LOKAL …, diakses Agustus 9, 2025, https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/panangkaran/article/download/0501-02/1808/5626
- Kemenag: Penghayat Kepercayaan Binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses Agustus 9, 2025, https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-penghayat-kepercayaan-binaan-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-alqrq
- Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat … – Notaire, diakses Agustus 9, 2025, https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/download/26214/pdf/119374
- Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan – Journal of Universitas Airlangga, diakses Agustus 9, 2025, https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/24687/pdf
- PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yan, diakses Agustus 9, 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf
- Soal Pencantuman … – Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses Agustus 9, 2025, https://setkab.go.id/soal-pencantuman-penganut-kepercayaan-di-ktp-presiden-jokowi-ingatkan-putusan-mk-final-dan-mengikat/
- IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pengosongan Kolom Agama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Bag – Mahkamah Konstitusi RI, diakses Agustus 9, 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_429_Ikhtisar%2097_2016.final.%20edit%20PM3.pdf
- DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PE – OJS UNR, diakses Agustus 9, 2025, https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/download/1224/1036/
- PERSOALAN HUKUM PENGAKUAN HAK-HAK PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – Artikel Hukum, diakses Agustus 9, 2025, https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/8.%20Muwaffiq%20Jufri.pdf
- Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Kepada …, diakses Agustus 9, 2025, https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2022/12/05/pencatatan-perkawinan-bagi-penghayat-kepercayaan-kepada-tuhan-yang-maha-esa/
- Sosialisasi Layanan Adminduk bagi Penganut Aliran Kepercayaan – Tempo Witness, diakses Agustus 9, 2025, https://witness.tempo.co/article/detail/8311/sosialisasi-layanan-adminduk-bagi-penganut-aliran-kepercayaan-.html
- SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman, diakses Agustus 9, 2025, https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga/article/download/6580/3017/20118
- Pendidikan Penghayat Kepercayaan Dinilai Penting Masuk di RUU Sisdiknas, diakses Agustus 9, 2025, https://www.voaindonesia.com/a/pendidikan-penghayat-kepercayaan-dinilai-penting-masuk-di-ruu-sisdiknas/6737780.html
- ALIRAN KEPERCAYAAN-DAHLIA LUBIS jafar.pmd – Repository UIN Sumatera Utara, diakses Agustus 9, 2025, http://repository.uinsu.ac.id/8473/1/9.%20BUKU%20ALIRAN%20KEPErcayaan%20final%20cetak.pdf
- Macam-macam Kepercayaan di Indonesia yang Masih Dianut Hingga Sekarang – kumparan, diakses Agustus 9, 2025, https://kumparan.com/ragam-info/macam-macam-kepercayaan-di-indonesia-yang-masih-dianut-hingga-sekarang-21bV5upbznX
- problematika aliran kepercayaan dan kebatinan sebagai agama asli indonesia – Padepokan Jurnal, diakses Agustus 9, 2025, https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/download/1739/version/1349/969/9767
- Mengenal Tradisi Kejawen, Aliran Kepercayaan Masyarakat Jawa – Mitrapost.com, diakses Agustus 9, 2025, https://mitrapost.com/2022/10/17/mengenal-tradisi-kejawen-aliran-kepercayaan-masyarakat-jawa/
- upaya pelestarian tradisi foklor budaya kejawen di dusun kalitanjung, kecamatan rawalo – ENDOGAMI:, diakses Agustus 9, 2025, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/download/55661/pdf
- DIMENSI KEILAHIAN SUNDA WIWITAN DALAM UPACARA SEREN TAUN DI CIGUGUR, diakses Agustus 9, 2025, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/download/20994/7985/64855
- Komunitas Ugamo Malim atau Permalim (di Desa Tomok dan Desa Hutatinggi Prov. Sumatera Utara) – Jurnal Harmoni, diakses Agustus 9, 2025, https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/182/157/390
- ALIRAN PARMALIM DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA WILAYAH SUMATERA UTARA SKRIP, diakses Agustus 9, 2025, http://repository.uinsu.ac.id/6884/1/SKRIPSI%20PERI%20AGUSTI%20%2842154006%29.pdf
- KONSEP MULAJADI NABOLON DALAM AGAMA PARMALIM:TINJAUAN TENTANG SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA, diakses Agustus 9, 2025, https://jurnalistiqomah.org/index.php/jppi/article/view/1401/1166
- Mengenal Parmalim, Agama Asli Suku Batak yang Mirip dengan Yahudi – Bangsapedia, diakses Agustus 9, 2025, https://bangsapedia.com/posts/mengenal-parmalim-agama-asli-suku-batak-yang-mirip-dengan-yahudi
- BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Parmalim adalah satu aliran kepercayaan pada masyarakat batak toba yang masih berta – Repository UHN, diakses Agustus 9, 2025, http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2546/Marini%20Dolok%20Saribu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Marapu Cerminkan Harmoni Manusia, Alam, dan Leluhur dalam Budaya Sumba – BRIN, diakses Agustus 9, 2025, https://brin.go.id/news/122432/marapu-cerminkan-harmoni-manusia-alam-dan-leluhur-dalam-budaya-sumba
- Prosesi Ritual Kematian Umat Hindu Kaharingan Suku Dayak Dusun Di Kabupaten Barito Utara, diakses Agustus 9, 2025, https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/WK/article/download/315/171/
- tradisi habukung upacara kematian agama hindu kaharingan – Universitas PGRI Palangka Raya, diakses Agustus 9, 2025, https://jurnal.uppr.ac.id/index.php/PUPPR/article/download/34/32/
- Agama di Indonesia – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia …, diakses Agustus 9, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia
- Festival “Empat Gunung”: Menghidupkan Spiritualitas Marapu di Tanah Humba | WALHI, diakses Agustus 9, 2025, https://www.walhi.or.id/festival-empat-gunung-menghidupkan-spiritualitas-marapu-di-tanah-humba
- Diskriminasi di Tengah Keberagaman: Nasib Penghayat … – Konde.co, diakses Agustus 9, 2025, https://www.konde.co/2025/04/diskriminasi-di-tengah-keberagaman-nasib-penghayat-kepercayaan-di-indonesia/
- Nasib Malang Pendidikan Penghayat Kepercayaan: Penyuluh Dilarang Mendidik, Murid Dipersekusi, Hingga Problematika RUU Sisdiknas – INFID, diakses Agustus 9, 2025, https://infid.org/nasib-malang-pendidikan-penghayat-kepercayaan-penyuluh-dilarang-mendidik-murid-dipersekusi-hingga-problematika-ruu-sisdiknas/
- Masalah Diskriminasi Peserta Didik Penganut Kepercayaan Di Kota Makassar – ETDC, diakses Agustus 9, 2025, https://etdci.org/journal/JREP/article/download/2068/1139/10111
- sarasehan majelis luhur kepercayaan indonesia (mlki) – Disdikbud Kabupaten Pati, diakses Agustus 9, 2025, https://disdikbud.patikab.go.id/berita/detail/sarasehan-majelis-luhur-kepercayaan-indonesia-mlki
- Daftar MLKI Provinsi – Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, diakses Agustus 9, 2025, https://www.mlki.or.id/daftar-mlki-provinsi/
- Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diakses Agustus 9, 2025, https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/download/3723/2153/9107
- PERSADA (PERSATUAN WARGA SAPTA DARMA) Kelembagaan – Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, diakses Agustus 9, 2025, https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/persada-persatuan-warga-sapta-darma
- View of Resistensi Majelis Luhur Kepercayaan TErhadap Tuhan, diakses Agustus 9, 2025, https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/eips/article/view/14277/8389
- Lebih dari 102 Ribu Penduduk Indonesia Menganut Aliran Kepercayaan pada Juni 2021, diakses Agustus 9, 2025, https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/fc661f846d7069e/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021
- Jumlah Penghayat Kepercayaan Paling Banyak di NTT pada 2022, diakses Agustus 9, 2025, https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-penghayat-kepercayaan-paling-banyak-di-ntt-pada-2022
- Tokoh lintas agama Indonesia melawan diskriminasi terhadap aliran kepercayaan, diakses Agustus 9, 2025, https://indonesia.ucanews.com/2022/11/23/tokoh-lintas-agama-indonesia-melawan-diskriminasi-terhadap-aliran-kepercayaan/